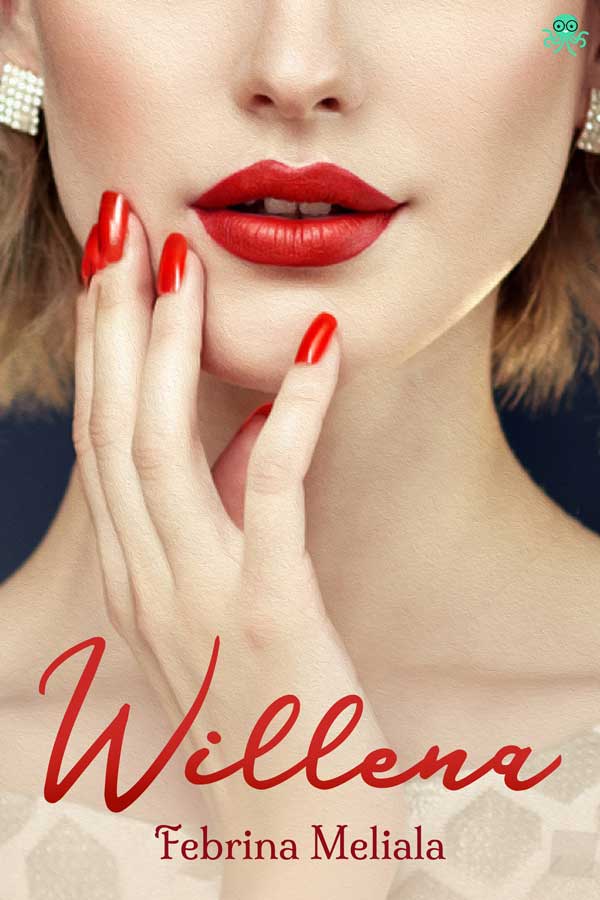
Willena
By febrinameliala
Prolog
Aku seharusnya berpikir untuk mengganti nama, dulu. Mengantisipasi kalau-kalau hari seperti ini akan datang, hari di mana aku bertemu lagi dengan Marthalena, cinta pertamaku.
Wajah baruku mungkin bisa mengelabuinya—aku bukan William yang tambun dan dekil lagi—tapi nama yang kusandang tidak akan bisa mengelabuinya. Terlebih nama belakangku, Pratama.
“Lena, kenalin, ini William Pratama,” kata Roy saat memperkenalkanku pada Lena.
“William Pratama?” gumam Lena. Wajahnya mulai berkerut mengingat-ingat. Bahkan dengan kerutan sebanyak itu pun dia tetap saja luar biasa cantik. Aku tidak yakin napasku yang tertahan sekarang adalah akibat dari harap-harap cemas menunggu respons selanjutnya, atau justru karena aku lagi-lagi terpesona padanya. Lesung pipi kecil di dekat bibirnya itu … masih bekerja seperti selalu, menyedot semua perhatian.
“Oh iya, Pratama, Len. Kamu mungkin kenal orangtuanya. Om Yudha Pratama, konsultan arsitek yang sering kerja sama sama perusahaan keluarga kamu juga,” tambah Roy. Membongkar rahasia yang sebenarnya ingin kukubur dalam-dalam.
Lena yang sekarang masih seperti Lena yang dulu. Dia terlalu ekspresif. Aku bisa menebak isi kepalanya hanya dengan melihat raut wajahnya yang penuh kekesalan itu.
Dia masih membenciku. Terlihat jelas dari tampangnya. Matanya yang bulat penuh itu seperti siap untuk menerkamku hidup-hidup. Tapi apalah dayaku, kalau sorot matanya yang kejam itu pun hampir membuatku gila, ingin rasanya aku memberikan kecupan ringan pada kelopaknya agar bisa membantunya menurunkan tegangan tinggi di sana.
“Halo, Lena. Lama tidak bertemu.” Pasrah, akhirnya aku bersuara juga.
Ini mungkin sudah waktunya.
Setelah bertahun-tahun yang lalu aku setia menguntitnya dan berakhir menyerah karena dia sudah bahagia bersama kekasihnya, Gery, mungkin sekarang waktunya kami dipertemukan lagi. Agar aku bisa menebus kesalahan fatal yang telah kuperbuat padanya.
Aku mengulurkan tangan berharap Lena bisa membaca niat baikku. Bahwa aku bukan William yang dulu. William yang sekarang, datang untuk membawa perdamaian, Lena.
Tapi apa yang bisa kuharapkan? Lena akan membalas uluran tanganku dengan senyum manisnya? Mana mungkin!
Sesuai dugaanku, Lena mengabaikanku.
Kalau saja bukan sedang dalam misi perdamaian, ingin rasanya kudekap punggungnya yang menjauh itu dalam pelukanku. Tidak akan kulepas, sampai habis jatah oksigen untukku dari Yang Maha Kuasa ….
1
“KAMU JAHAAAT!!! AKU BENCI SAMA KAMUUU!!!”
Itu mungkin suara paling tinggi yang pernah kuperdengarkan. Aku sendiri tidak pernah menyangka punya suara semelengking itu. Padahal biasanya aku memproduksi suara bulat penuh, khas announcer yang rajin olah vokal.
Gery berusaha menenangkanku sekali lagi. Ditariknya aku kuat-kuat, masuk ke dalam pelukannya. Tapi aku meronta. Menggeliat. Gelisah. Amarahku sudah di ubun-ubun. Melampiaskannya dengan teriakan saja rasanya tidak cukup. Maka kulayangkan tinju di sekujur tubuh Gery. Tidak cukup kuat untuk membuatnya tersiksa, sebenarnya, apalagi tenagaku tidak maksimal karena energiku harus dibagi dengan tangisan.
Aku melenguh sambil sesenggukan. Kepalan tanganku masih saja mendarat di sekujur tubuhnya.
Gery bergeming. Menerima pasrah semua seranganku. Sesekali dia meringis, mungkin karena pukulanku mengenai bekas memar yang memenuhi sekujur tubuhnya.
Sambil mengusap air mata cepat, kulihat bercak hitam di punggung tanganku. Pasti bekas maskara yang sudah luntur dan berserak di pipi. Entahlah bagaimana penampilanku sekarang, aku tidak mengerti. Tidak cukup antusias untuk mengerti juga. Karena aku lebih suka melampiaskan amarahku dulu.
Sekali lagi kukumpulkan sisa-sisa tenaga untuk memukul tubuh Gery. Seperti kehabisan bahan bakar, pukulanku semakin melemah setelah menit kesepuluh. Tangisku pecah semakin menjadi-jadi.
Kenapa pukulan-pukulan ini rasanya sia-sia? Aku hanya menghabiskan energi untuk hal yang tidak berguna ….
“Kenapa kamu tega banget sama aku, Ger …. Kamu bilang kamu sayang sama aku ….” Kali ini lengkingan itu sudah hilang, digantikan lirih. Kupegangi jaket denimnya kuat agar tidak terjatuh karena lemahnya pertahananku sekarang. Berdiri saja rasanya aku tidak mampu.
“Aku minta maaf, Len …,” Gery menundukkan kepalanya dalam.
Dengan penglihatan yang kabur karena masih digenangi air mata, kulihat setetes air mata Gery tumpah membasahi pipinya.
Aku biasanya luluh setiap kali air mata buayanya itu mengambil peran. Setiap kali dia ketahuan selingkuh, air mata buayanya itu selalu menjadi penyelamat hubungan kami. Tapi kali ini, sebesar apa pun efek air matanya itu pernah meluluhkanku, hubungan kami tidak bisa selamat.
“Keluarga Gista sudah menemui keluargaku, mereka minta pertanggungjawaban atas kehamilan Gista. Aku nggak bisa mangkir lagi, Len ….” Perkataannya itu sekaligus menjawab kenapa tampangnya penuh dengan lebam. Dia pasti dipukuli ayahnya yang pensiunan Angkatan Darat. “Aku nggak bisa melawan Papa, kamu tahu itu. Aku nggak mungkin permalukan Papa ….”
Aku terduduk lemah di bibir tempat tidur. Memegangi jaket denimnya saja pun aku tidak sanggup lagi. “Tapi kamu tega nyakitin aku …?”
Gery bersimpuh di depanku. Menyejajarkan wajahnya di depan wajahku. Ditangkupnya wajahku dengan telapak tangannya yang terasa bergetar, lantas berkata, “Kamu pasti dapat yang lebih baik dari aku, kamu akan baik-baik saja, Lena ….”
**
“Sori, tapi gue harus bilang syukur, deh,” Naya, sahabatku, memberi pendapat setelah kuceritakan padanya akhir hubunganku dengan Gery. “Dari dulu juga kan gue bilang lo terlalu baik untuk dia, Len …. Dia itu brengsek! Berkali-kali ketahuan selingkuh! Lo-nya aja yang bego mau balikan terus-terusan.”
“Lo gimana, sih? Bukannya menghibur malah makin nyudutin Lena. Kasian kan dia …,” Siva, sahabatku yang lainnya, mencoba membela. Kami memang berkumpul di rumahku hari ini untuk sesi curhat. Aku perlu seseorang untuk menghibur, atau paling tidak mendengar curhatku.
“Kenapa coba orang kalo sakit dikasi pil pait? Disuntik? Dioperasi? Jelas-jelas menyiksa kan, tapi nggak papa, yang penting cepet pulih. Sama! Gue juga bicara nyelekit dan mungkin bikin lo makin sakit hati, tapi percayalah, gue lakuin itu demi kebaikan lo. Biar sadar. Dan cepat move-on,” tutur Naya membela diri.
Naya ada benarnya.
Hati ini mungkin tidak akan seremuk ini kalau dari dulu, sejak zaman putih abu-abu, aku tegas untuk putus dengan Gery setiap kali dia selingkuh. Nyatanya, segala perlakuannya selalu berhasil meluluhkanku. Dia memperlakukanku kelewat hati-hati. Membuatku sulit percaya kalau dia seberengsek yang orang-orang bilang.
Semasa pacaran di zaman sekolah, dia hanya memegangi tangan dan kecup kening, beranjak menjadi anak kuliahan baru berani cium bibir, giliran sudah bekerja sebagai musisi dia justru semakin hati-hati memperlakukanku. Tidak berani mencelakai, katanya.
Jadi bagaimana aku bisa percaya kalau laki-laki seperti dia bisa menghamili wanita lain begitu mudahnya?
“Gery dulunya baik, sih, guys.” Sekali lagi Siva menengahi. “Ingat kan, gimana dia minjemin jaket pas baju seragam Lena jadi terawang karena guyuran hujan? Gimana dia selalu nganterin Lena pulang sebelum jam sembilan malam, gimana sopan santunnya di hadapan orangtua Lena. Tapi dia mulai berubah sejak jadi anak band. Gue nggak heran, sih. Anak band yang sering kerja sama sama EO gue juga pada kadal gitu modelnya.”
“Profesi nggak bisa dijadikan pembenaranlah. Intinya dia tetap aja brengsek, udah hamilin anak gadis orang. Dan intinya, dia khianatin lo, Len. So, get over him! Hempaskan aja dia ke rawa-rawa biar digerogoti kecebong!” ucap Naya berapi-api.
Satu cengiran lolos dari bibirku saat mendengarnya. Bukan karena aku serta merta pulih, melainkan karena aku menghargai usaha Naya.
“Nah, gitu, dong! Senyum! Kalo lo senyum gitu kan, jadi ketahuan kalo lo emang yang paling cantik di antara kita semua!” Naya langsung antusias.
“Sekarang waktunya buka lembaran baru, Len. Buka lagi daftar antrean cowok yang selama ini udah nunggu-nunggu lo putus dari Gery. Mereka pasti dengan senang hati berbaris lagi buat cari perhatian lo,” imbuh Siva.
Siva tidak berlebihan. Aku memang sepopuler itu di masa sekolah, di lingkungan kuliah, bahkan di tempatku bekerja sekarang. Hanya saja terjebak dengan Gery membuatku tidak bisa berpaling darinya. Tidak bisa kumungkiri kelebihan terbesarku terletak pada parasku yang rupawan. Secara kasatmata, aku mirip dengan perempuan metropolis kebanyakan: putih, rambut panjang, tinggi, dan ramping. Daya pikat terbesarku adalah lesung pipi samar di dekat bibir. Tidak terlalu besar dan dalam, tapi cukup mencolok saat aku sedang tertawa. Mirip lesung pipi milik Jennifer Lawrence dan Nia Ramadhani.
“Lo mungkin bisa pertimbangkan Haris, Len. Sampai sekarang kan dia masih cinta mati tuh sama lo,” saran Naya, menyebutkan nama ketua OSIS zaman kami SMA dulu.
Di acara reuni tiga bulan lalu, Haris masih saja menggodaku untuk menerima perasaannya. Tapi aku yang masih terikat pada Gery menolaknya mantap. Padahal Haris cukup tampan, pekerjaannya juga lumayan: dokter umum.
“Oh, gue tahu!” Siva menepuk tangan satu kali, seperti baru saja berhasil memikirkan ide brilian. “Handoko aja, Len. Lo kan suka tuh liat montir-montir seksi. Ingat nggak sih waktu kita ke bengkelnya bulan lalu? Bodinya yang seksi berlumur oli, ngelelehin bangeeet ….” Siva gemas sendiri.
Ya, Handoko memang seseksi itu. Tapi sekadar enak dipandang. Aku tidak pernah memikirkannya lebih dari itu.
“Aaah … Mas Tyo aja, kali, Len. Pergerakannya bakal gampang dideteksi. Dia kan satu radar terus tuh bareng kita. Nggak bakal kesulitan deh jagain dia, nggak kayak jagain mantan lo yang anak band begajulan itu,” Naya mengusulkan nama yang lainnya.
Mas Tyo adalah station manager di radio tempatku bekerja. Dia sudah terang-terangan menyatakan perasaannya sejak setahun yang lalu. Tapi aku tidak bisa menerimanya. Syukurlah dia profesional. Tidak mencampur urusan pribadi dan pekerjaan. Jadi aku masih nyaman bekerja dengannya sampai sekarang.
“Enggak dulu deh, guys. Gue masih mau sendiri dulu.”
**
Aku benar-benar serius dengan perkataanku pada kedua sahabatku Naya dan Siva tempo hari, tentang kesendirian. Mengabaikan semua sindiran Mama tentang kelakuan Gery, aku memutuskan untuk pergi berlibur seorang diri.
Aku mengerti kekecewaan Mama. Dia sudah terlalu banyak berharap pada hubunganku dan Gery. Bagaimana tidak? Gery menjadi satu-satunya laki-laki yang menjalin hubungan denganku hingga usiaku cukup matang untuk menikah, 25 tahun. Mama bahkan sering kali menyinggung tentang rencana pernikahan setiap kali Gery datang ke rumah. Diberi tanggapan positif oleh Gery membuat harapan Mama semakin melambung. Sayangnya harapannya itu harus terempas ke inti bumi, melahirkan kekecewaan yang teramat dalam.
“Tapi dia nggak pernah gituin kamu juga kan, Len? Bisa nggak laku lagi, lho, kamu!” Mama mulai menginterogasi lagi.
“Ma, please …. Lena nggak mau bahas Gery dulu, ya. Mama tenang aja, Lena masih segel, kok. Anak gadis Mama pasti masih punya daya jual di pasaran,” kataku sambil menyusun isi koper yang akan kugunakan untuk berlibur. “Tapi enggak sekarang.”
“Kamu pergi karena ini?” Mama memungut undangan pernikahan yang tergeletak mencolok di atas nakas.
Jelas warna hijau terang undangan itu bukan pilihan Gery. Dia pasti akan memilih warna-warna elegan seperti gading, maroon, atau gold, seperti yang sudah kami bicarakan dulu. Ah, mengingatnya saja sudah menciptakan luka baru di hatiku. Kapan hati ini akan pulih kalau belum sembuh saja masih dicabik-cabik terus seperti ini?
“Apa, sih, yang ada di pikirannya sampai ngundang kamu segala? Dia mau kamu pingsan di acara pernikahannya dan jadi viral, gitu? Biar mendongkrak popularitas bandnya sekalian? Kampungan!” Suara Mama memang cukup tinggi, tapi aku bisa merasakan getar di antara suaranya. Disusul dengan setetes air yang tiba-tiba meluncur dari sudut matanya.
Aku lantas mengabaikan koper yang sedang kugeluti guna mendekap Mama. Aku tahu Mama juga cukup terluka dengan semua kenyataan ini.
“Mama tenang aja, Lena kan lagi di Kuala Lumpur pas acara nikahannya nanti. Jadi nggak akan ada drama viral-viral begitu,” ucapku sambil mengusap lembut punggung Mama.
“Kamu nggak usah nonton acara gosip di sana nanti, ya! Nggak usah ngecek-ngecek akun lambe-lambe atau kepo di Youtube. Pokoknya kamu liburan aja, cari cowok baru, kalau bisa.”
“Iya, Ma, iya ….”