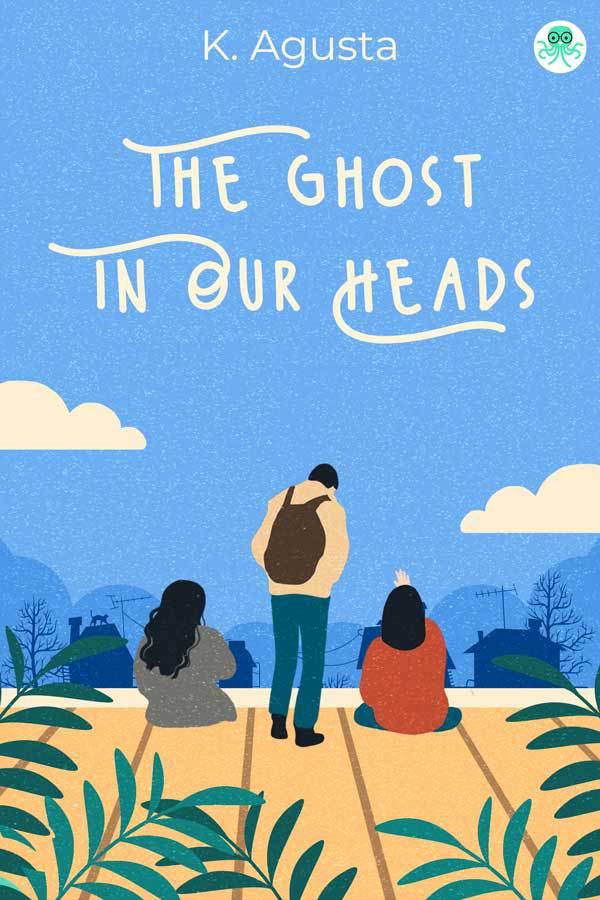
The Ghost in Our Heads
By kamalagusta
Warning: konten sensitif, depresi, bunuh diri, dsb.
PROLOG
Pada pertengahan bulan Desember, saat usiaku baru 10 tahun, peristiwa yang mengubah kehidupanku itu terjadi.
Siang itu cuaca sangat terik. Seragam sekolah yang kukenakan sudah lengket dan sedikit basah oleh keringat. Terburu-buru aku memasukkan sepeda ke garasi, lalu berlari masuk ke rumah. Pintu tidak terkunci sebab seminggu ini Ibu tidak bekerja karena sakit. Setelah melepas sepatu dan meletakkannya di rak, aku berlari kecil ke dapur. Tujuanku adalah mengisi gelas dengan air dari dispenser. Sungguh, kerongkonganku sudah perih karena menahan haus sejak tadi.
Setelah menandaskan segelas air, aku membilas gelas dan meletakkannya di rak pengeringan. Aku mengintip isi tudung saji. Sudah ada makanan. Sepertinya tadi pagi sebelum berangkat ke kantor, ayah menyempatkan diri untuk memasak. Cacing di perutku berbunyi, tapi aku teringat pesan Ibu untuk mengganti seragam sekolah sebelum makan. Aku menutup Kembali tudung saji, lalu keluar dari dapur, berjalan menuju kamarku.
Namun, saat melewati kamar orangtuaku, langkahku terhenti. Aku menatap pintu kamar yang tertutup rapat. Perasaan sedih menyelubungiku mengingat Ibu yang akhir-akhir ini lebih sering menghabiskan waktu di dalam kamar. Aku mendekat, menempelkan kuping ke daun pintu, tak mendengar suara apa-apa. Mungkin Ibu sedang tidur, pikirku. Aku meraih kenop pintu, menekannya ke bawah, bermaksud untuk melihat kondisi Ibu sebentar. Daun pintu berayun terbuka.
Tiba-tiba tubuhku membeku. Tatapan mataku tertuju pada satu titik. Meski keadaan kamar sedikit gelap dan pengap karena jendela tertutup rapat oleh tirai, aku masih mampu melihatnya. Di sana ada Ibu.
Namun, Ibu tidak sedang berbaring di ranjang seperti dugaanku. Ibu sedang menatapku dengan mata terbuka lebar, dan tergantung oleh seutas tali.
Terakhir yang kuingat, sebelum jatuh pingsan adalah aku menjerit sekeras-kerasnya.
***
SATU
Bagiku, sendiri jauh lebih baik. Sendiri berarti tidak perlu berbagi apa pun dengan yang lain. Sendiri berarti menutup kesempatan orang lain. Sendiri berarti rahasia yang kusembunyikan selama ini terjaga selamanya. Kesepian hanya hal sepele dibandingkan rahasiaku.
Namun, Bu Vira, guru Bahasa Indonesia sekaligus wali kelasku tidak sepemikiran denganku.
“Kelompok belajar ini akan bertahan sampai naik kelas. Tujuannya agar kalian saling membantu dan mendukung jika mengalami kesulitan belajar.”
“Tapi, Bu. Saya mau sekelompok dengan Ayu,” protes salah satu murid laki-laki di pojok kelas. Hal itu memicu keriuhan kelas. Namanya Danu.
“Ayu yang ogah dekat-dekat sama kamu!” balas gadis berambut sebahu, yang merupakan sahabat sekaligus teman satu kelompok gadis bernama Ayu tersebut.
“Sudah-sudah, jangan ribut!” Bu Vira mencoba meredam keributan kelasnya. “Danu, Ibu sudah merancang kelompok belajar ini sebaik mungkin. Ibu memasangkan sesuai kelebihan dan kekurangan kalian. Dengan begitu kalian dapat saling melengkapi. Mengerti?”
Danu menggaruk kepalanya dan mengangguk.
Sementara aku menatap dua orang yang duduk di hadapanku, lalu menghela napas. Berpasangan saja aku tidak mau, apalagi harus bertiga. Terlebih harus satu kelompok dengan dua orang ini. Kata Bu Vira kelompok belajar ini sudah dirancang agar kami saling melengkapi. Untuk kelompok kami, aku meragukannya.
Aku buru-buru menunduk, pura-pura fokus pada buku cetak saat tatapan dingin Milo terarah kepadaku. Coba lihat, Milo saja terlihat tidak menyukaiku. Begitu pun dengan Cessa, anggota lain kelompok belajar ini. Gadis berambut pirang itu malah asyik menatap ke luar jendela. Sama sekali tidak peduli dengan pelajaran.
Sepertinya saat istirahat nanti aku harus menemui Bu Vira. Membicarakan tentang kelompok belajar ini. Jika perlu, aku meminta izin pada Bu Vira agar tidak perlu ikut kelompok belajar. Aku meminta dispensasi agar mengerjakan semua tugas seorang diri.
Ya, itu jauh lebih mudah dibandingkan harus bersama Milo dan Cessa.
***
Ketika bel istirahat aku langsung bergegas menuju ruang guru.
Di SMA Persada, ruang guru terletak di lantai bawah, diapit oleh ruang tata usaha dan ruang bimbingan konseling. Selama bersekolah di SMA Persada, aku selalu menghidari ruang guru. Seingatku, hanya sekali aku masuk ke ruang ini. Waktu itu aku kelas X, aku dipanggil oleh wali kelas karena tidak masuk selama tiga hari tanpa keterangan.
Sesampainya di ruang guru, aku mendekati meja Bu Vira. Wali kelasku itu terlihat sedang berbicara dengan Monika, salah satu murid terpandai di kelasku. Sepertinya mereka sedang membahas mengenai tugas yang diberikan tadi. Menyadari ada pihak yang mendengar obrolan mereka, Bu Vira menoleh ke arahku. Aku melemparkan senyum canggung seraya mengangguk.
“Ada perlu sama Ibu, Shaki?” tanya Bu Vira.
Mendengar namaku di sebut, Monica ikut menoleh. Aku meresposn pertanyaan Bu Vira dengan anggukan.
“Tunggu sebentar, ya,” pinta Bu Vira ramah.
Bu Vira memiliki paras yang ayu. Tutur katanya pun selalu lemah lembut. Setiap bertemu, guru muda itu selalu tersenyum ramah, memperlihatkan cekungan di kedua pipi mulusnya. Tidak mengherankan jika banyak murid-murid SMA Persada yang memilih Bu Vira saat pemilihan guru favorit.
Selagi menunggu Bu Vira berbicara dengan Monika, aku mengedarkan pandangan. Terakhir kali aku memasuki ruang guru, dindingnya dicat warna biru laut. Sekarang warnanya masih sama, hanya mulai memudar dan di beberapa tempat mulai mengelupas. Suasana di dalam ruangan cukup bising, mulai dari obrolan beberapa guru yang berkumpul di meja Pak Togar, juga ditimpali oleh denting sendok yang beradu dengan piring. Aroma hangat nasi uduk bercampur ayam dan bawang goreng menggelitik penciumanku. Mendadak cacing di perutku meronta-ronta.
Dua menit berselang, akhirnya urusan Monika dan Bu Vira selesai juga. Setelah dipersilakan, aku duduk di tempat yang tadi diduduki Monika.
“Ada yang bisa Ibu bantu, Shaki?”
Alih-alih menjawab pertanyaan Bu Vira, aku malah menunduk, menatap jemari yang saling meremas di pangkuan. “Apa bisa saya tidak ikut kelompok belajar, Bu? Maksudnya … saya bisa mengerjakan semua tugas itu sendirian.”
Saat aku punya keberanian mengangkat kepala, Bu Vira menatapku dengan senyum lembut.
“Kenapa?” Bu Vira bertanya.
Aku menarik napas, lalu mengembuskannya pelan. “Saya hanya tidak terbiasa bekerja sama. Lagi pula … kami tidak cocok.”
“Begini saja, Shaki. Kita coba dulu selama sebulan, bagaimana? Jika nanti kalian memang tidak cocok, Ibu akan mengganti teman kelompokmu.”
Sebulan tentu saja itu waktu yang lama bagiku. Duduk bersama selama 2 jam pelajaran bersama Milo dan Cessa saja, rasanya seperti setahun. Namun, saat menatap Bu Vira, aku sadar ini tawaran terbaik yang bisa guru itu berikan. Pada akhirnya aku mengangguk lalu berpamitan untuk kembali ke kelas.
“Shaki!”
Langkahku berhenti, lalu memutar tubuh Kembali menghadap Bu Vira. Guru itu tersenyum tipis dan berkata, “Tidak selamanya kita bisa melakukan semuanya sendirian. Ada kalanya kita butuh seseorang. Suatu saat nanti, Ibu harap kamu tahu bahwa kelompok belajar ini akan membantumu.”
***
Malam itu Ayah pulang lebih awal dari biasanya. Aku segera membantu Ayah membawa kantong belanjaan berisi bahan makanan. Seperti biasa, saat pulang cepat Ayah akan memasak untuk makan malam kami. Selagi menunggu Ayah mandi, aku mengeluarkan beberapa bahan makanan yang akan diolah nanti. Sementara sisanya dimasukkan ke lemari pendingin.
Aku sedang mencincang bawang putih saat Ayah muncul di dapur dengan rambut basah. Aroma sabun tercium dari tubuhnya yang mengenakan kaus oblong cokelat kayu. Ayah melirik pekerjaanku sesaat, lalu mengambil pisau di rak, dan mulai membersihkan ikan.
“Bagaimana sekolah hari ini?” Ayah menoleh sambil mencuci ikan di bak cuci piring.
“Seperti biasa, Yah. Banyak tugas. Tapi, semua aman.”
Aku memutuskan untuk tidak membicarakan tentang kelompok belajar yang mengganggu pikiranku kepadanya. Ayah tidak perlu tahu masalah itu. Pekerjaan sudah terlalu menyita pikirannya, dan aku tak ingin menambahnya dengan permasalahanku.
“Sebentar lagi mau ujian tengah semester, kan?”
Aku mengangguk, “Sebulan lagi.”
“Kalau ada tugas yang tidak bisa kamu kerjakan, beritahu ayah. Nanti ayah bantu.”
Tawaran itu selalu diberikan Ayah, tapi aku tidak pernah menggunakannya. Aku berusaha untuk menyelesaikan tugasku sendiri. Aku tidak ingin merepotkan Ayah.
Semua bahan makanan sudah disiapkan. Ayah menyuruhku untuk belajar selagi ia memasak. Aku menurut. Setelah mencuci tangan, aku keluar dari dapur.
Sejak Ibu pergi, urusan memasak memang jadi tugas Ayah. Sementara bagianku adalah membersihkan semua pekakas kotor setelah kami makan nanti.
***
Aku sedang menatap keluar jendela saat terdengar suara ketukan papan tulis. Saat aku menoleh ke depan kelas, Farel, ketua kelas, berdiri sambil mengetuk-ngetuk papan tulis dengan penghapus.
“Bu Vira nggak masuk. Ada rapat guru,” Farel mengumumkan. Kelas seketika pecah oleh sorakan.
“Ke kantin, yuk!” aku mendengar Ayu mengajak Sesa. Lalu kedua gadis itu bergandengan tangan keluar kelas. Namun, di depan pintu Danu mengadang. Cowok badung itu cengengesan, tapi Sesa menatapnya jijik. Satu kelas sudah tahu kalau Danu naksir Ayu.
Aku kembali mengalihkan pandangan keluar jendela. Dari sini aku bisa melihat lapangan basket. Ada beberapa anak yang sedang bermain. Beberapa gadis duduk bergerombolan di tepi lapangan, bergosip sambil sesekali bersorak saat ada bola yang masuk ke keranjang. Semua terlihat senang dengan adanya jam kosong ini, tapi aku malah merasa bosan. Jam kosong membuat waktu seakan melambat.
Tiba-tiba seseorang berdiri di samping mejaku. Ternyata Cessa.
“Bagianku,” katanya sambil meletakkan selembar double polio di atas meja. Aku membaca tulisnya, ternyata ulasan buku yang minggu lalu ditugaskan Bu Vira.
Aku menerima kertas itu lalu menggumamkan terima kasih. Cessa mengangguk lalu kembali ke kursinya. Aku menatap punggung Cessa yang menjauh dan menghela napas. Seminggu telah berlalu tapi kami sama sekali tidak akrab. Tadi itu adalah interaksi pertama kami sejak kelompok ini dibentuk. Aku menaruh kertas tugas Cessa ke dalam tas. Tinggal Milo yang belum menyerahkan bagiannya. Sejak tugas ini diberikan, kami sepakat untuk mengerjakan bagian masing-masing.
Aku menoleh ke belakang, tempat Milo duduk. Kepala cowok itu rebah di atas meja, dengan mata terpejam. Apa dia udah mengerjakan bagiannya? tanyaku dalam hati. Terserahlah, putusku akhirnya, memilih tidak peduli. Lagi pula, aku sudah mengerjakan semuanya sendirian. Antisipasi jika Cessa dan Milo tidak mengerjakan bagian mereka. Aku kembali menghadap ke depan, lalu ikut merebahkan kepala.
***