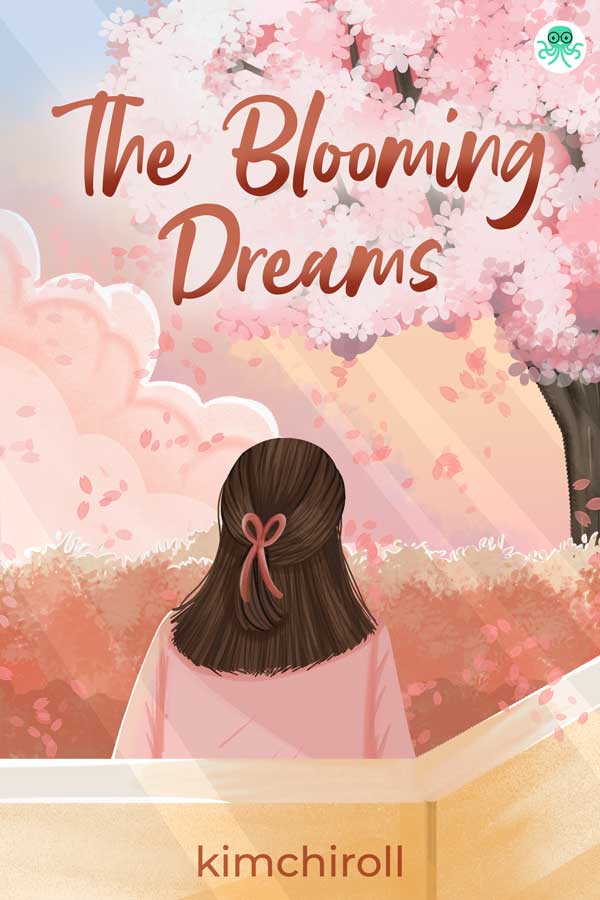
The Blooming Dreams
By Kimchiroll
“Aku beneran nggak boleh ikut Mama pergi dinas, nih?”
Wening mengerucutkan bibirnya sembari menatap perempuan berusia empat puluhan yang sedang mematut diri di depan cermin besar dekat lemari pakaian. Wanita nyaris paruh baya itu selesai merapikan setelan blus dan syal bercorak garis-garis yang serasi dengan warna hitam pada celana kulot. Dia menata rambut dengan hairspray sampai kaku dan tidak ada helai-helai mencuat keluar. Wening berpikir kalau tatanan rambut mamanya tampak kuno, seperti guru berpakaian serba merah muda yang ada di film bocah sihir terkenal itu.
“Mbak Mala, kan, bakal datang lusa. Kamu sendirian cuma hari ini sama besok, kok, Ning.” Sang mama mengambil lipstik dari meja rias dan memulasnya hati-hati di bibir. Dia mencecap beberapa kali, memastikan warna peach itu tidak menempel ke gigi.
“Tapi habis itu Mbak Mala juga bakal kerja. Dia, kan, balik dari liburan, bukan mau liburan, Ma.” Wening masih cemberut sambil menepuk-nepuk bantal bulat yang berantakan di atas ranjang berseprai kelabu dengan corak bunga-bunga putih.
Destyana menoleh pada putri bungsunya lalu tertawa kecil. “Maaf, Sayang, tapi di sana Mama bakal tinggal dengan roommate. Agak susah untuk bawa kamu. Mama juga cemas kalau ninggalin kamu sendirian di sana. Kan, Mama juga bakal sibuk seminar ini itu. Nanti Mama belikan oleh-oleh. Oke?”
Wening mengembuskan napas kencang, pertanda pasrah dan menyerah. Kalau tinggal dengan orang lain, tentu sang ibu tidak bisa leluasa. Pun, Wening tidak akan selesa untuk beraktivitas di sana. Ibunya akan pergi ke Beijing untuk melakukan pekerjaan dan memakan waktu sekitar satu bulan. Ini kesempatan besar dari perusahaan setelah Destyana bekerja selama bertahun-tahun. Ada dua klien dari perusahaan di sana yang ingin melakukan ekspansi dan mereka meminta advokat dari firma tempat Destyna bekerja untuk mengatur langkah-langkah kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
Wening mungkin belum pernah bekerja, tapi dia tahu betapa penting pekerjaan bagi orang dewasa dan tidak ingin menyusahkan sang mama. Dia tidak ingin mengacaukan peluang yang belum tentu bisa datang dua kali.
“Uang sakumu sudah Mama transfer, pakai dengan bijak. Meski liburan, bukan berarti kamu bisa boros, ya,” ujar Destyana sambil memasang anting-anting jepit di telinga. “Sembako juga sudah Mama siapkan. Ada makanan kaleng kalau kamu malas bikin yang segar. Ya, paling kakakmu lagi yang bakal repot masak, tapi—”
“Iya, Ma. Aku nggak boleh nyusahin Mbak Mala.” Sekali lagi, Wening merengut meski membenarkan dalam hati. Dia memang kurang pandai urusan rumah karena biasanya sudah terlalu letih untuk melakukannya.
“Dan jangan lupa minum vitaminmu. Mama serius,” kata Destyna lagi dengan raut sungguh-sungguh. “Jangan kelelahan dan jangan main sampai malam. Kamu ingat kata Mbak Mala, kan? Angin malam nggak bagus buatmu.”
Wening memonyongkan bibir, tapi mengangguk. Dia mendesah dan berpikir betapa tidak enaknya dipandang sebagai anak yang lemah. Mau bagaimana lagi? Pun, itu sebabnya dia tidak mengikuti ekstrakurikuler di sekolah yang kebanyakan memakan banyak waktu dan tenaga karena padatnya aktivitas. Dia harus tinggal di rumah ketika sebagian besar murid lain mengikuti klub sepak bola, basket, voli, fotografi, bela diri, dan sebagainya. Wening bahkan tidak bisa ikut klub melukis begitu sang mama tahu kalau dalam sebulan sekali ada kegiatan luar.
Sekali waktu, pernah Wening membandel dan iseng ikut ketika klub fotografi melakukan pendakian ke pegunungan untuk mencari objek gambar. Bukan pendakian ekstrem karena pegunungan tersebut juga bukan termasuk wilayah yang berat. Bahkan, seorang pendaki pemula pun bisa melakukannya. Namun, Wening yang tidak terlatih secara fisik dan mental, akhirnya kolaps ketika melangkah setengah perjalanan. Dia dilarikan ke rumah sakit dan Destyna terpaksa batal pergi ke Manado untuk menjaga putrinya.
Beberapa hari kemudian, Wening mencuri dengar percakapan ibunya dengan atasan di kantor. Dari suara sang mama, Wening tahu kalau wanita itu mendapat teguran keras, dan sejak saat itu, gadis tersebut tidak mau menyusahkan lagi.
Destyana bekerja sebagai pengacara dan belum lama diangkat sebagai rekanan senior. Jam kerjanya bertambah seiring penghasilannya. Wening senang ketika tahu keadaan finansial mereka membaik. Namun ternyata, tidak semua hal berjalan mulus. Mamanya mulai sering pulang larut dan kelihatan stres. Meski termasuk penyabar, satu dua kali Destyana bisa sangat kesal pada hal-hal kecil di rumah. Wening menarik diri dan tidak mau mengganggu sang ibu sejak saat itu, dan sepertinya Destyana menyesal.
“Maafkan Mama karena begitu sibuk selama ini.” Destyana duduk di tepi ranjang dan membelai kepala anak bungsunya dengan lembut. Ekspresi wanita berambut ikal itu tampak rumit, lelah, sekaligus seolah-olah meminta pengertian.
Wening menarik napas kemudian tersenyum, berusaha menenangkan sang mama. “Nggak masalah. Mama pantas mendapat peluang ini. Mama sudah berusaha begitu keras, kan?”
Wening melihat mata ibunya berkaca-kaca kemudian memeluknya. Sejenak, gadis itu merasa kesal pada sang ayah yang meninggalkan keluarganya, dua tahun silam. Untuk perempuan lain yang hanya lima tahun lebih muda dari mamanya. Wening enggan menyimpan dendam, tetapi perasaan marah dan kesal tidak mudah diempaskan, terutama ketika melihat sang ibu sempat terpuruk dan mengalihkan diri pada pekerjaan, habis-habisan. Sang ayah seolah-olah membuang mereka dari kehidupannya karena jarang menghubungi, bahkan untuk sekadar bertanya keadaan anak-anaknya. Sejak saat itu, Wening juga bersikap tak ambil peduli dan hanya menatap sang mama yang banting tulang untuk mempertahankan kewarasan keluarga pascacerai.
Wening melepas pelukan dan sang mama membelai rambutnya pelan. Gadis itu terenyuh melihat wajah wanita yang melahirkannya belasan tahun silam. Garis-garis halus mulai muncul di sekitar sudut mata Destyana. Sorot lelah, bahagia, semua campur aduk ketika Wening melihat pantulan dirinya di sana. Dia mengawasi sang ibu yang kemudian mengecek koper dan tas tangan di dekat meja rias. Mengamati ketika sang mama masih sempat mengangkat telepon dari klien juga membalas E-mail di komputer.
Lima belas menit kemudian, taksi pesanan Destyana datang dan Wening membantu membawakan koper sampai ke pintu lobi apartemen. Resepsionis yang sedang membetulkan lipstik, menyapa Destyana ketika mereka melintas. Wening melihat sedan terparkir di depan gedung. Dia merasakan sesak memenuhi rongga dada saat Destyana mengecup pipinya kemudian masuk ke taksi dan melambai dari balik jendela mobil, sebelum kendaraan itu meraung pergi dari gerbang.
“Bu Destyana jadi berangkat?”
Wening menoleh dan menemukan sekuriti apartemen berbadan besar dengan mata sipit yang ramah. Itu Pak Yohan, satpam favorit penghuni apartemen Camellia. Pria itu berusia tiga puluhan akhir, memiliki istri yang sama menyenangkan, juga putri kecil berusia tiga tahun yang kadang-kadang datang untuk menyapa sang ayah di tempat kerja sambil membawa kotak makanan di gendongan sang ibu.
“Iya, Pak,” sahut Wening sambil mengangguk, berusaha agar air yang mengambang di pelupuk matanya tidak jatuh.
“Jadi sendirian, ya, di rumah?”
“Besok Mbak Mala datang kok, Pak,” jawab Wening sambil bersandar ke tembok.
“Hati-hati di rumah sendirian, ya. Kunci pintu dan pastikan jendela terkunci. Pintu balkon juga jangan lupa. Bu Destyana sudah titipkan Nak Wening ke Bapak. Katanya, Nak Wening nggak boleh pulang di atas jam sepuluh malam. Jadi, Bapak bakal mengawasi, loh.” Pak Yohan menyunggingkan cengiran. “Kalau butuh makanan rumah, bilang saja. Nanti istri Bapak bisa buatkan.”
Wening tersenyum. “Makasih banyak, Pak. Eh, aku masuk dulu, ya, Pak.”
Sekuriti itu mengangguk lalu berjalan kembali ke pos jaga. Wening menarik napas panjang dan menyeret kakinya yang terbalut sandal ke lift, naik ke apartemennya yang sepi.
***
Wening menggulir layar ponsel, selesai membaca pesan dari kakak perempuannya yang masih berada di Thailand. Kakaknya seorang dokter dan memutuskan untuk libur sejenak setelah setahun bekerja keras. Nurmala alias Mala—atau para pasiennya memanggil dengan sebutan Dokter Mala—memiliki klinik kecil tak jauh dari apartemen. Kepribadiannya tenang dan anggun, cocok dengan kerudung merah muda dan jas dokter warna putih yang berpadu serasi. Mala dikenal ramah pada pasien dan itu membuat kliniknya cukup terkenal.
Melihat foto kakaknya yang terlihat senang dengan latar Wat Arun, Wening mengembus napas panjang. Meski bangga memiliki kakak yang baik dan pintar, terkadang Wening merasa terbebani. Mama dan kakaknya begitu cemerlang. Satu pengacara, satu dokter. Kalau sedang berkunjung ke rumah sang nenek dan bertemu tetangga, mereka suka sekali berkomentar soal betapa beruntung kakek-neneknya memiliki anak dan cucu perempuan yang pandai juga sukses. Setelah itu, para tetangga akan melirik Wening dan bilang kalau gadis itu kelak harus lebih sukses dari ibu dan kakaknya.
Wening hanya bisa tersenyum kemudian perlahan menyingkir ke dapur untuk pura-pura sibuk membereskan piring-piring.
Sejujurnya, Wening belum tahu apa yang akan dilakukannya setelah lulus sekolah. Dia sama sekali belum punya bayangan. Nilai-nilainya tidak jelek meski ada beberapa mata pelajaran yang dianggap menyulitkan. Prestasi di bidang olahraga tidak begitu cemerlang sehingga pilihan menjadi atlet juga dirasa bukan yang terbaik. Bahasa? Wening suka mempelajarinya, tetapi tidak yakin apakah kemampuannya cukup untuk level penerjemah atau membawanya untuk kuliah di luar negeri. Melukis? Wening masih ragu terutama ketika ada tetangga yang berkomentar, “Memang bisa dapat gaji berapa kalau jadi pelukis?”
Wening meletakkan ponsel di atas meja persegi dengan kaca di dekat sofa kemudian memejamkan mata. Rasanya tak sabar menunggu Mala pulang. Sang kakak biasanya punya saran bagus soal keluhan. Kalaupun tidak, wanita berhidung mancung itu akan di sana, mendengarkan penuh perhatian sembari meyakinkan sang adik kalau semua akan baik-baik saja.
Wening membuka mata dan menatap langit-langit. Berpikir keras, apa yang bakal dilakukannya pada liburan kali ini? Libur sekolahnya agak unik dan sedikit lebih panjang dari sekolah biasanya. Kalau tidak punya kegiatan, hari-hari akan terasa membosankan.
Di sekolah Wening, siswa kelas 12 tidak hanya sibuk dengan persiapan ujian nasional, tetapi juga konseling dan bimbingan khusus bagi mereka yang memiliki pilihan di luar universitas. Para guru akan memandu mereka dalam menentukan jurusan universitas. Sementara bagi mereka yang memang ingin langsung bekerja, akan diarahkan untuk magang di tempat-tempat yang memiliki koneksi dengan pihak yayasan. Mereka juga akan dibantu untuk mengurus dokumen-dokumen terkait pengajuan beasiswa dan sejenisnya.
Tidak hanya itu, akan ada pekan di mana para guru mendampingi siswa untuk melakukan survei ke beberapa kampus sehingga siswa yang berminat bisa benar-benar melihat lingkungan kampus sasaran mereka. Selama jangka waktu tersebut, siswa kelas 10 dan 11 akan mendapat libur.
Beberapa pihak mungkin berpikir kalau cara demikian terbilang ribet, tetapi Wening berpendapat kalau detail-detail itu bisa membantu banyak. Wening mendengar dan merasakan kegelisahan para senior yang tampak tegang menjelang ujian nasional, karena bukan hanya itu kecemasan mereka. Banyak siswa kelas 12 yang masih bingung dalam menentukan langkah. Beberapa dari mereka bimbang untuk masuk universitas karena masalah biaya—sebab meski ada tunjangan pendidikan, mereka harus memenuhi kebutuhan lain dengan uang pribadi—dan ada juga yang merasa pesimis untuk terjun di dunia kerja karena minim pengalaman.
Banyak orang dewasa berpikir, hal-hal ini wajar dan harus dihadapi dengan sabar. Namun, bagi remaja yang belum tahu banyak perihal dunia kerja atau dunia kampus, tentu saja masalah ini bisa sangat memusingkan. Wening bersyukur para guru mau bekerja keras karena setelah sesi konseling atau kunjungan, para senior biasanya mulai bisa menentukan arah langkah mereka.
“Astaga!” Wening refleks bangkit ketika sebuah pesan muncul di layar. Dia menepuk kening dan menggeram saat membaca teks itu.
Ning, kamu udah nentuin tema buat tugas esai liburan sekolah?