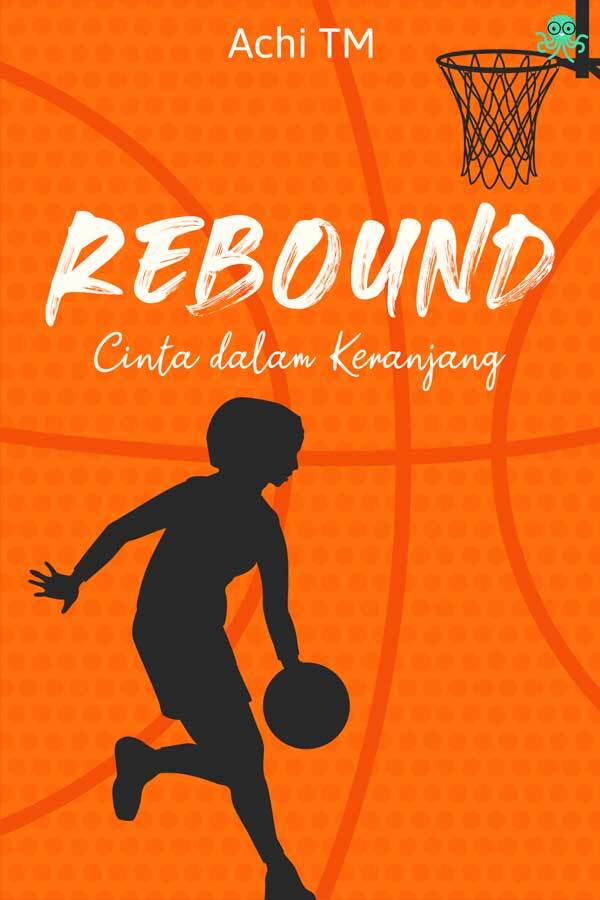
Rebound - Cinta dalam Keranjang
By achi-tmpenulis
Prolog
Tangerang, 2017
Priiit!
Suara peluit terdengar nyaring bersamaan dengan suara dribel bola basket yang menggema di sebuah gedung olahraga daerah Tangerang. Dian berdiri di pinggir lapangan sambil bersedekap. Ia memakai jaket bertudung, berukuran jumbo sehingga terlihat gombrong, dengan celana jeans yang juga lebar dan sepatu kets.
Satu poin lagi maka kemenangan akan menjadi milik tim suaminya.
Ya, suaminya tengah berada di sana, mendribel bola dengan gagah perkasa. Otot-otot tangannya terlihat kekar dan kuat saat melemparkan bola basket ke dalam ring. Bola melesat, dan, ah … gagal masuk lagi. Bola hanya berputar di pinggir ring lalu jatuh ke lapangan.
Dian menatap kecemasan di wajah suaminya. Ini adalah pertandingan terakhir suaminya sebagai seorang atlet daerah. Dia tidak boleh kalah. Dian meremas bola basket di tangannya, bola basket yang menjadi saksi cinta dia dan suaminya.
Kisah cinta mereka berawal dari basket.
Sepuluh tahun yang lalu, tahun 2007, ketika media sosial belum populer dan bermain basket menjadi hal menyenangkan untuk menghabiskan waktu. Dari sinilah kisah cinta Dian dimulai.
Pada suatu hari ….
1. Hari Gini Masih Dijodohin? Basi, Tau!
From 2007
Dian masih berdiri suntuk di depan pagar rumahnya. Pagar besi berukir yang tingginya dua kali lipat badan Dian. Rumah orang tuanya sangat luas, tingkat dua dan mempunyai gaya Eropa klasik yang terlihat megah. Biasanya sepulang sekolah, Dian langsung masuk ke dalam rumah dan memilih rebahan melepas lelah di atas kasur empuknya. Tapi kali ini ia melipat tangan di dada sambil bersungut. Kakinya mengentak-entak ke tanah. Sesekali jilbabnya melambai diterpa angin. Matanya memicing kesal ke dalam rumahnya. Nadine yang berdiri di samping Dian jadi ikutan gelisah. Berulang kali Nadine membetulkan jilbabnya yang agak miring-miring.
“Yan, sebenernya mau ada aksi apa lagi, sih? Kok aku disuruh nemenin kamu di depan rumah kamu sendiri? Aku pengin pulang, nih!”
“Pulang aja, tapi besok lo kagak bakal dapet senyuman dari gue forever!” ketus Dian tanpa menoleh sedikit pun pada Nadine.
Nadine mengangkat bahu lalu ikutan merengut meski sebenarnya aksi keroncongan di perutnya lebih keras mengentak daripada aksi ngambek Dian saat ini. Tapi membayangkan Dian akan memusuhinya seumur hidup membuat lapar di perut Nadine pelan-pelan menghilang. Bagaimanapun, Nadine adalah remaja pemalu yang susah sekali berteman. Baginya Dian adalah sahabat satu-satunya.
Seorang wanita setengah baya dengan dandanan cantik ala ibu pejabat, keluar dari rumah Dian. Wanita itu tersenyum manis ke arah Dian, lalu menghampirinya.
“Sayaaang .… Kok nggak masuk ke rumah? Mas Eddy udah nungguin kamu dari tadi,” sapa wanita itu. Jilbab wanita itu diikat ke belakang, di dadanya terkalung bandul-bandul yang terbuat dari ruby.
“Dian nggak akan pernah masuk ke rumah kalau Mama dan Papa belum membatalkan rencana pertunangan konyol ini!” tegas Dian.
Nadine menahan tawa dan mengangguk-angguk. Ooh …. Ngambek kagak mau ketemu calon tunangannya, toh .… Hihihi .… Nadine terkikik dalam hati.
Wanita setengah baya itu, Bu Cipto alias mamanya Dian, mengangguk tanda mengerti. Bu Cipto merangkul Dian dan berbisik, “Dian .… Kamu, kan, belum ketemu sama Mas Eddy. Orangnya ganteng, lho. Mama aja sampai kepengin ….”
“Ya udah, kalo gitu si Eddy-Eddy itu buat Mama aja,” Dian menjawab asal. “Dian mau ke lapangan, mau main basket! Kalau si Eddy udah pulang, baru Dian balik ke rumah.” Dian beralih pada Nadine. “Ayo, Nad, temenin gue.”
Dian menarik tangan Nadine, rok seragam abu-abunya menyapu tanah. Dian dan Nadine berbalik badan. Nadine berpamitan pada Bu Cipto. Bu Cipto tersenyum maklum. Dian segera naik sepedanya dan mengayuh pergi. Nadine mengikuti Dian dari belakang dengan sepedanya sendiri. Sebenarnya, Dian sering diantar ke sekolah naik mobil bersama sopir keluarga. Kalau sedang bosan, ia memilih naik sepeda bersama Nadine.
“Dian! Dian!” Bu Cipto mau mengejar tapi baru melangkah lebar-lebar, kakinya sudah ngilu. Ia lupa kalau sedang pakai stiletto yang lancip. “Oalaaah .… Anak gadis cuma satu susah banget diurusnya.” Bu Cipto menyeka keringat di dahi.
“Dian sudah pulang, Bu?” sapa seorang lelaki tampan di belakang Bu Cipto.
Bu Cipto berbalik badan. “Belum, Mas Eddy. Aduh, saya minta maaf banget, ya, membuat Mas Eddy menunggu lama …,” jawab Bu Cipto.
“Oh .… Nggak apa-apa, kok, Bu, saya siap menunggu. Kalau pertunangan ini jadi, saya juga harus menunggu Dian lulus SMA dulu. Ya, kan, Bu?” Eddy tersenyum lebar. “Jadi, ya, saya mau, kok, nungguin Dian pulang. Saya penasaran banget, pengin tahu yang mana wanita yang akan jadi calon tunangan saya ….”
“He’eh, Mas Eddy….” Bu Cipto tersenyum kaku.
Eddy membalas dengan senyum kaku pula. Sementara itu, di depan pintu rumah, Pak Cipto hanya bisa memilin-milin jenggotnya yang semakin panjang menuju jakun.
***
Di lapangan RT, masih dengan seragam sekolah dan jilbab yang menjuntai hingga dada, Dian asyik mendribel bola. Di kanan-kiri Dian, berdiri Nadine dengan perut keroncongannya, Bondan yang memakai kaus basket dan celana selutut, serta Coki, cowok ceking, tinggi, berkacamata, tak berotot namun bercita-cita menjadi seperti Yao Ming, soalnya matanya agak-agak sipit.
“Coba, nih, ya, lo bertiga bayangin. Gue masih kelas dua SMA dan udah dijodoh-jodohin ama orangtua gue! Bete nggak, sih?!” Dian curhat pada ketiga sohibnya. Dian lalu melempar bola ke dalam ring. Meleset. Bola menampar papan ring, lalu berbalik ke arah Bondan.
Dengan cekatan Bondan melakukan rebound, yaitu menangkap bola yang gagal dimasukkan ke ring dan memantulkan bola kembali ke dalam ring. Shoot! Masuk!
Bola melesak ke dalam ring lalu jatuh ke tanah dan memantul. Dian segera menggaet bola itu dan memutar-mutarnya di ujung telunjuk tangan kanannya.
“Lo pada dengerin gue, dong! Gue lagi curhat, nih!” Dian protes.
“Aduuh .… Yan, aku laper. Aku pulang, ya …,” Nadine memohon dengan tampang hopeless.
Dian menatap Nadine kesal. Nadine yang aslinya memang penurut banget alias Dianholic jadi diam saja sambil memegangi perut.
“Plis, dooong. Kalo di film-film, ada temen curhat tuh ditanggepin! Ayo, dong .… Ada yang mau nanggepin curhat gue?!”
“Gue.” Bondan menyerang ke arah Dian, menjulurkan tangan pada bola basket di tangan Dian dan mulai mendribel. “Gue mau bilang, Diaaan .… Ini waktunya kita main basket, Bro! Yihaaa!” Bondan mengoper bola pada Coki.
Coki menangkap dan memantulkan bola sambil memainkannya dengan atraksi kaki dan tangan. Setelah itu, Coki melompat dan bergaya untuk melakukan slam dunk. Bola mengenai pinggiran ring, terpental kembali ke arah Coki dan duaaag! Tepat menerjang kacamata Coki.
“Oh my God …. Oh my God! Kacamata gue, retak lagi … retak … ooooh!” Coki mengerang sambil membuka kacamatanya yang retak.
Wajah Dian mengeras karena bete seketika.
“Diaaan …,” Nadine kembali mengeluh.
“Ya udah, lo pulang aja. Gue juga mau sendiri.” Dian berjalan ke pinggir lapangan dan mengambil ranselnya dengan kesal.
Nadine jadi serba salah dan mengikuti langkah Dian meninggalkan lapangan.
Dari kejauhan Bondan berteriak, “Dian! Besok siang latihan basket di klub! Jangan lupa!”
“Yeaaah…,” sahut Dian pelan.
***
“Mama sama Papa, kan, udah naik haji. Seharusnya Mama sama Papa juga tahu, dong, kalau di dalam Islam itu nggak ada istilah tunangan!” protes Dian ketika Bu Cipto dan Pak Cipto mengajak Dian diskusi pada malam harinya. Semua kakak lelaki Dian ikut nimbrung.
“Imron setuju sama Dian, Ma,” Imron, abang pertama Dian, angkat bicara. “Menurut Imron, rencana pertunangan itu nggak masuk akal. Selain nggak ada dalam Islam, Dian juga masih terlalu dini untuk nikah!”
“Tapi, kan, nikahnya bisa nanti setelah lulus SMA. Kalau Dian masih mau kuliah pun Mas Eddy bisa, kok, nungguin Dian!” bela Mama.
“Kenapa, sih, Mama sama Papa ngotot banget mau ngejodohin Dian?” tanya Reza, abang kedua Dian.
“Yaaa ….” Pak Cipto berdeham. “Yaaa …. Begini. Papa sudah tua dan Dian adalah anak perempuan Papa satu-satunya. Eddy itu adalah anak bos Papa. Orangnya baik. Jadi, Papa pikir dia bisa melindungi Dian selepas Papa meninggal nanti. Lagi pula, tahun depan Papa akan pensiun. Papa takut tidak bisa menguliahkan Dian. Kalau Dian tunangan dengan Eddy, bos Papa berjanji akan membiayai sekolah dan kuliah Dian.”
“Setuju, Pa, biar Dian kagak ngerepotin gue!” timpal Bayu, abang ketiga Dian.
“Maksud Papa dan Mama juga begitu,” Bu Cipto tersenyum.
“Hmmm .… Gimana, ya. Betul juga, sih. Nanti aku, kan, bakal balik ke Amrik,” gumam Reza.
“Ma, Pa, Imron masih bisa ngurusin Dian. Lagi pula siapa yang tahu kapan Papa dan Mama akan meninggal? Siapa tahu saja masih berumur panjang ….”
“Kalau Mama, sih, mungkin masih ada umur, masih sehat. Tapi Papa sudah tua … lebih tua sepuluh tahun dari Mama … sudah sakit-sakitan ….” Pak Cipto terbatuk- batuk.
“Apa pun alasan Papa dan Mama, Dian tetap menolak!” tegas Dian.
Ibu dan Pak Cipto memandang ke arah Dian dengan pandangan yang sangat dalam seolah ingin bilang, “Nak, turutin aja deh kemauan orangtua kamu!”
Suasana menjadi hening seketika. Semua kakak Dian saling pandang.
Imron berdeham. “Udah waktunya buat tidur, kan? Udah jam sepuluh lewat, nih. Mungkin Dian punya tugas sekolah yang harus dikerjakan?” Imron berusaha mengakhiri perdebatan.
Imron menatap Dian. Pak Cipto berdiri, Bu Cipto berusaha memapahnya.
Pak Cipto mulai batuk-batuk. Setelah batuknya selesai, Pak Cipto mengembangkan senyum, lalu tertawa. “Dian … Dian. Bagaimanapun kamu tetap anak Papa dan Mama. Sekarang masuk saja ke kamar. Hari Minggu besok Mas Eddy akan datang lagi. Dia ingin sekali bertemu kamu. Hahaha .… Papa rasa kamu yang keras kepala dan suka meledak-ledak memang cocok diberikan pada Mas Eddy….”
Setelah berkata begitu, Pak Cipto berjalan memasuki kamar utama di dekat ruang keluarga.
Dian merengut. ‘Diberikan pada Mas Eddy’? Emangnya gue barang kardusan yang gampang dikasih ke sembarang orang? Huh…! Maaf, ya, Papa, Mama, but I don’t want it! Ihhh…!