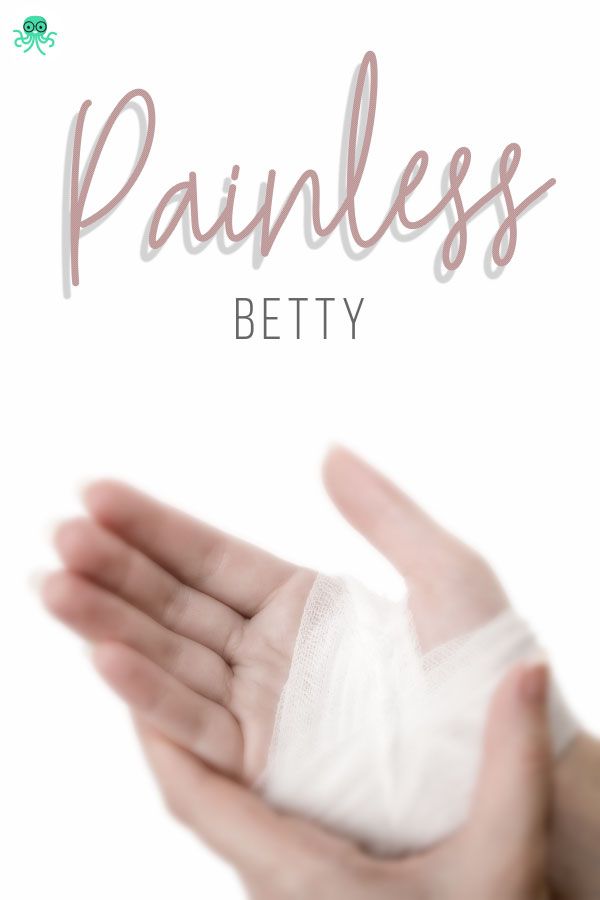
Painless
By Betty
“Hai, Super Girl. Pagi amat datangnya?” Kristi menyapa Nira yang sudah duduk manis di bangkunya. Hari pertama sekolah. Kelas baru, suasana baru, sekolah baru. Nira sudah tak sabar ingin segera memakai seragam putih abu-abunya sejak beberapa hari yang lalu.
“Hai. Ayah berangkat pagian. Jadi, aku ikut aja,” jawab Nira sambil menutup buku yang dibacanya.
“Ayahmu yang berangkat pagian, atau kamu yang nggak sabar pengen segera berangkat?” Kristi yang sudah mengenal Nira dengan baik menggodanya. Nira nyengir.
“Nira, Kristi, kalian mau gabung ekstrakurikuler karate, nggak?” Dita, salah seorang teman mereka dari kelas sebelah mendatangi bangku Nira dan Kristi.
“Karate? Kayaknya keren, tuh. Jadi pendekar,” komentar Nira sambil menatap Kristi menunggu persetujuan.
“NO! Eh, sorry ya, Dit. Kita tahu ekstra karate sekolah kita memang keren, sering menang turnamen. Kita sebenarnya pengen gabung, tapi kayaknya nggak mungkin, deh,” Kristi menjawab dengan cepat sambil mencengkeram lengan Nira. Dita menatap mereka dengan wajah penuh tanya.
“Emangnya kenapa? Kalian belum gabung klub apa pun, kan?” tanya Dita.
“Ehm, sebenernya kita baru mau daftar klub jurnalistik sama bahasa. Mungkin teater atau komputer juga bisa. Lagian Nira juga pernah cedera kaki, nggak boleh olahraga yang berisiko tinggi,” Kristi melontarkan alasan yang terlintas di benaknya. Dita menatap mereka dengan kecewa.
“Oke, deh. Kalau kalian berubah pikiran, hubungi aku, ya.” Dita meninggalkan dua lembar formulir pendaftaran di meja Nira, lalu melangkah pergi.
“Ahh, aku nggak bisa ikut ekstra yang keren,” keluh Nira setelah Dita keluar dari kelas mereka.
“Nira, aku nggak mau lihat kamu celaka, ya. Please. Kamu masih inget, kan, waktu kelas satu SMP? Kamu gabung ekstra wall climbing tanpa persetujuan Ibumu. Tahu-tahu kamu udah diantar rame-rame ke IGD gara-gara jatuh dan patah tulang bahu. Apalagi kalau sekarang kamu gabung klub karate. Bisa patah semua tulang-tulangmu gara-gara main banting-bantingan.” Kristi menatap Nira tajam. Nira memutar bola matanya dengan sedikit kesal.
“Kamu, cucok banget, ya, sama Ibuku. Beneran, deh. Ibu harus kasih kamu gaji, soalnya kamu udah jadi body guard aku yang bener-bener bisa diandalkan,” Nira mengomel dengan setengah bercanda. Kristi tertawa.
“Emang. Seharusnya bayaranku gede, nih. Susah, tahu, ngejagain anak macam kamu ini. Keras kepala, tukang ngomel, suka nekat….” Omelan Kristi terhenti karena Nira sudah menyerbunya dengan cubitan yang mengarah ke pinggang dan lengannya.
Nira dan Kristi sudah jadi teman sekelas sejak TK. Rumah mereka juga di kompleks perumahan yang sama, hanya berbeda blok. Orang tua mereka pun sudah saling mengenal dengan baik, seperti saudara kandung. Kalau ada yang sedang memerlukan bantuan, keluarga satunya pasti akan memberikannya tanpa diminta. Apalagi karena kedua orang tua Nira tak lagi punya seorang pun kerabat.
Ibu Nira sangat bersyukur bisa menemukan Kristi dan memercayakan pengawasan Nira padanya. Setidaknya, sedikit beban berkurang dari pundak ibu Nira. Walaupun kadang kesembronoan dan keingin tahuan mereka sebagai remaja masih beberapa kali mencederai Nira, tapi untungnya tak ada yang serius. Nira dan Kristi terus bersahabat baik sampai kini mereka masuk SMA.
***
“Kak Stef, aku pengen banget gabung. Tapi ada syaratnya.” Nira berbisik pada Steffi, kakak kelasnya. Ketika jam istirahat pertama berbunyi tadi, Kristi didatangi sekelompok anak dari klub bahasa yang memberi kesempatan bagi Nira untuk menyelinap pergi dari pengawasan Kristi.
“Syarat apaan?” Steffi menatap Nira heran. Dia menyadari bahwa Nira sebenarnya adalah gadis yang cantik. Di balik kacamata, rambut panjang berponi, kaus kaki selutut, dan sweater kedodoran yang selalu dikenakannya sepanjang waktu tak peduli apa pun cuacanya, Nira memang gadis yang cantik. Bopeng bekas luka yang menghiasi sekujur tubuhnya hanyalah sebagian bukti petualangannya selama ini. Bukti ketangguhan yang ditunjukkan bahwa tidak mudah baginya untuk bertahan selama 15 tahun hidupnya ini.
“Jangan bilang Kristi kalau aku gabung cheers,” Nira berbisik lebih pelan lagi. Steffi belum tahu apa-apa tentang Nira. Dia hanya tahu bahwa di kelas X ada anak baru yang tubuhnya dipenuhi bekas luka dan dandanan yang aneh. Tapi Steffi cukup objektif melihat postur Nira yang langsing dan tinggi itu memenuhi syarat untuk menjadi anggota cheers. Karena itu Steffi mau menerima Nira.
“Oke. Nggak masalah.” Walaupun tak sepenuhnya paham, Steffi tetap mengangguk menyanggupi persyaratan yang diajukan Nira.
Steffi menerima formulir pendaftaran yang diserahkan Nira. Jadwal latihan cheers cukup padat. Dua kali seminggu, tiap Selasa dan Kamis sepulang sekolah, bisa jadi lebih sering bila akan ada pertandingan. Beruntung, jadwal itu berbarengan dengan ekstrakurikuler jurnalistik. Nira bisa berpura-pura ikut klub jurnalistik bila Kristi bertanya. Nira tak suka berbohong, apalagi pada sahabat baiknya sendiri. Tapi dia ingin sekali ikut ekstrakurikuler yang sedikit lebih menantang. Dia sudah bosan terus menerus dibatasi. Di SMP, ibunya berhasil memaksanya masuk klub kesenian dan membuat tim karate menolaknya.
“Stef, kenapa kamu terima dia?” Klarisa, salah seorang pentolan klub cheers menyeret Steffi ke salah satu pojok aula tempat mereka berlatih sore itu.
“Iya. Kenapa harus dia? Bukannya anak cheers harus berpenampilan menarik, pede, menonjol, segala macem?” Pinkan, teman sekelas Klarisa ikut nimbrung.
“Kenapa nggak? Semua orang kan berhak masuk cheers asalkan mau kerja keras dan ikut aturan kita. Masih inget Kak Rara?” Steffi menyebutkan salah satu kakak kelas mereka yang lulus dua tahun lalu.
Rara selalu menjadi ikon tak terpisahkan dari cheers SMU Tunas Harapan. Posturnya yang tambun, berlawanan dengan image anggota cheers ideal yang langsing, tinggi semampai. Tapi urusan kelincahan, jangan ditanya. Kelenturan Rara ketika melakukan stunt kayang, split, scorpion maupun bow and arrow sangat luar biasa untuk anak dengan berat badan lebih dari 70 kg itu. Akibatnya, Rara tak pernah bisa jadi flyer karena syarat utama untuk menjadi flyer adalah berat badan antara 35-40 kg. Tapi, dia tetap merupakan anggota cheers yang mengesankan.
Klarisa dan Pinkan terdiam. Tentu saja mereka ingat Rara. Foto-fotonya masih terpajang rapi di hall of fame ruang cheers.
“Kita lihat saja apa anak-anak baru nanti bisa ikutin latihan dan aturan kita dengan baik. Kalau mereka nggak bagus, kan tinggal dikeluarkan aja,” Steffi menambahkan. Untung ketua cheers itu adalah anak yang adil. Dia tak pernah diskriminatif dan sok populer.
Latihan cheers perdana sore hari itu baru berupa pengenalan dan orientasi. Lima belas anggota baru yang berhasil direkrut mengikuti pemanasan dan berlatih gerakan-gerakan dasar cheerleading. Ternyata menjadi seorang pemandu sorak tidaklah mudah. Mereka tidak hanya berteriak-teriak di pinggir lapangan, mengayun-ayunkan pom-pom dengan ekspresi lucu. Tapi juga perlu stamina prima, kedisiplinan tinggi, dan kerja sama tim yang solid. Jika tidak, mereka tak akan ada bedanya dengan penonton atau suporter biasa.
“Kamu lumayan juga.” Steffi mendekati Nira di akhir latihan. Peluh membasahi seragam olahraga yang dikenakannya. Handuk kecil warna hijau muda tersampir di bahu kiri setelah digunakan untuk menyeka wajahnya yang berkeringat.
“Bener, Kak? Tapi kalian keren banget. Aku jadi mikir lagi, bisa nggak ya aku jadi selincah dan selentur Kakak.” Nira juga menyeka wajahnya dengan handuk kecil yang dibawanya. Sore itu Nira tampak lebih muda karena tak mengenakan kaca matanya. Rambut panjangnya diikat dan digelung ketat di belakang kepala agar tak mengganggu gerakan. Poninya ditahan dengan bandana putih. Steffi dapat melihat jelas beberapa codet dan bekas luka lain di dahi, pelipis, dan wajah Nira. Tapi Steffi tetap berpendapat bahwa semua itu bukan masalah besar dan tak akan mengurangi kecantikan Nira.
“Pasti bisa. Asal kamu rajin dan disiplin, pasti bisa kayak kita. Bahkan mungkin lebih. Kita semua juga pernah jadi anak baru kok.” Steffi menepuk bahu Nira.
Nira mengucapkan terima kasih atas dukungan Steffi. Dia membereskan perlengkapannya dan bersiap untuk pulang ketika Steffi bertanya.
“Mmm, aku boleh nanya sesuatu, nggak?” tanya Steffi agak ragu.
“Nanya aja, Kak.” Nira menegakkan tubuh dan menyampirkan tas di bahu kanannya. Dia sudah menduga ke mana arah pertanyaan Steffi. Bukan pertama kalinya orang menatapnya dengan rasa ingin tahu dan bertanya tentang bekas luka di wajahnya.
“Pasti semua bekas luka ini, kan?” Nira mendahului Steffi karena melihatnya agak tak enak hati mengutarakan pertanyaannya. Steffi mengangguk dan menyeringai segan. Nira duduk di bangku pinggir aula. Steffi mengikuti duduk di sebelah Nira. Anak yang lain satu per satu meninggalkan aula dan pulang ke rumah masing-masing.
“Aku nggak enak juga sebenernya sama Kak Steffi. Serba salah. Kalau aku ngomong jujur, aku takut Kak Stef nggak akan ngasi aku izin buat gabung cheers. Atau kasi izin, tapi bakal ngelarang aku ini itu. Tapi kalau nggak bilang, nanti kalau ada apa-apa, Kak Stef nggak bisa nolongin aku,” Nira memulai penjelasannya. Steffi jadi agak waspada. Nira menatap Steffi yang mengangguk, menunggu kelanjutan cerita Nira.
“Aku punya kelainan, Kak. Aku nggak bisa ngerasain nyeri. Jadi apa pun yang aku lakuin, jatuh sampai tulangku patah, latihan ngotot sampai betisku keram, atau manuver sampai ligamenku sobek, aku nggak akan ngerasain apa pun. Bekas luka-luka ini buktinya. Jatuh, kebentur, sobek, dijahit, memar, retak, sampai patah tulang, udah jadi makanan sehari-hari waktu aku kecil.” Steffi ternganga mendengar penjelasan Nira.
“Tapi itu artinya kan bahaya banget. Kamu seharusnya nggak boleh ikut kegiatan fisik. Termasuk cheers. Ini risiko cederanya kan tinggi. Apalagi buat kamu.” Steffi seketika menyadari risiko yang dihadapinya.
“Aku tahu, Kak. Makanya aku nggak bilang. Aku pengen banget ikut cheers. Dari dulu aku nggak boleh ikut kegiatan yang berisiko tinggi. Aku bosen, Kak,” Nira memohon.
“Tapi kalau kamu kenapa-napa, bukan cuma kamu yang kena. Aku juga. Mungkin semua anak cheers juga bakalan kena akibatnya.” Steffi berusaha mencerna informasi yang baru saja didapatnya dan mengambil keputusan yang terbaik. Untuk Nira dan untuk timnya.
“Kak, aku udah ngelewatin banyak hal buat bertahan hidup sampai umur segini. Orang tuaku udah ngajarin aku untuk ngenalin kegiatan apa aja yang berbahaya buat aku, apa aja batas-batasnya, dan gimana harus periksa badanku sendiri buat deteksi cedera,” Nira berusaha meyakinkan Steffi yang masih berpikir keras.
“Kakak kasih aku kesempatan buat coba dulu beberapa bulan. Kalau aku sampai cedera, aku rela dikeluarin dari cheers.” Nira membulatkan tekad. Steffi menatap mata Nira lekat-lekat. Dia dapat melihat kesungguhan dan keinginan besar dalam diri Nira. Steffi tak tega menolaknya.
“Tapi kamu harus nurut kataku. Kalau aku bilang jangan, ya jangan.” Nira mengangguk kuat-kuat bahkan sebelum Steffi menyelesaikan kalimatnya.
“Makasih, Kak.” Spontan Nira memeluk Steffi erat. Steffi tertawa dan menepuk punggung Nira.
“Jangan senang dulu. Kalau sampai kamu cedera, bisa-bisa aku yang digorok sama orang tuamu nanti.”
Nira menyeringai polos. Bagaimanapun dia ingin tumbuh seperti remaja lain seusianya. Mencoba apa pun yang tampaknya menarik, melakukan apa pun yang diinginkan, tanpa dihalangi oleh keterbatasan. Nira berharap dia bisa melewati masa SMU ini dengan kenangan indah seperti yang dikatakan orang. Larangan-larangan itu hanya akan membentengi hidupnya dan membuat hari-harinya jadi monoton dan membosankan. Apa yang akan terjadi, biarlah terjadi. Kata pepatah, better regret the things you’ve done, than regret the things you haven't done, kan?
***