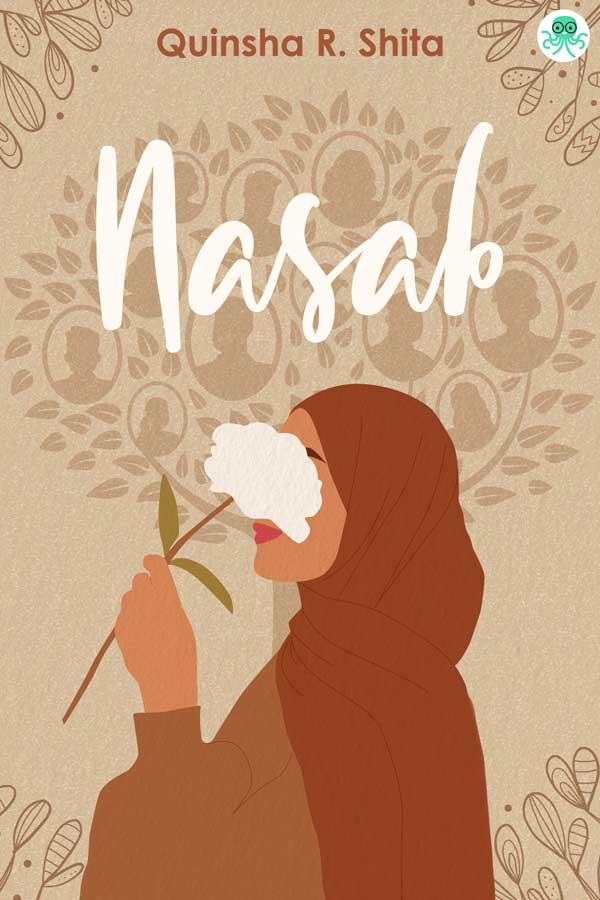
Nasab
By Quinsha R. Shita
Aku bukanlah cewek yang seratus persen alim atau lulusan pondok pesantren. Namun, aku sama sekali nggak pernah meragukan kebenaran firman-Nya. Seperti ayat yang terjemahannya berbunyi, ‘Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan?’. Begitu pula Tuhan telah melimpahkan rahmat-Nya padaku.
Kehidupanku terbilang sempurna. Aku memiliki orang tua dengan stok kasih sayang berlimpah. Jika ditinjau secara finansial, keluarga kami tergolong berkecukupan. Papa punya usaha mebel yang pelanggannya sampai ke luar pulau. Kehidupan sosial dan akademikku juga tidak punya masalah berarti. Sejak dulu aku selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangiku. Mulai dari Papa, Mama, teman-teman, guru, juga seseorang yang sangat spesial.
“Dor! Senyam-senyum sendiri! Kenapa, sih? Kesambet, ya?” Baru juga dipikirin, dengan tidak sopannya Bisma menepuk punggung tanganku sampai berjingkat. Tak terima dikagetkan seperti itu, kubalas perbuatannya dengan cubitan maha dahsyat di lengan atas.
“A-aw! Ampun!” Bisma mengaduh kesakitan. Sambil meringis, ia mengusap bekas jariku yang pasti meninggalkan jejak memerah. “Sadis banget sih, jadi pacar! Disayang, kek, dipeluk, kek.”
Aku menjulurkan lidah menanggapi protesnya. “Enak aja main peluk-peluk! Emangnya guling? Kalo mau, halalin dulu, gih!” tantangku. Berani bertaruh, ia pasti mengelak. Tuh, kan! Lihat saja wajahnya yang cuma cengar-cengir tanpa dosa!
Gertakanku barusan terbang bersama angin yang berkesiur dari celah pepohonan. Malam ini, Bisma mengajakku makan di Taman Tabanas sambil menikmati keindahan kota Semarang. Biar kayak orang-orang yang lagi pacaran, katanya. Padahal kami memang sudah menjalin hubungan tersebut selama empat tahun lebih. Meski dalam perjalanannya jauh dari kata romantis atau mesra.
“Nah, kan. Ngelamun lagi!” Kali ini tangan Bisma tidak usil mengagetkanku, tetapi suaranya saja sudah cukup menarikku dari lautan imaji. Aku meringis sambil meraih gelas es jeruk yang tinggal separuh dan sudah berembun. Akibat terlalu lama dianggurin hingga dingin dari es batunya memencar.
“Ya udah. Ayo, aku halalin kamu.”
Hampir saja aku tersedak. Kebiasaan Bisma membuat lelucon di saat yang tidak tepat. Kuraih sendok kotor di atas piring bekas makan kami yang masih berserak di meja. Lantas menggetokkannya ke punggung tangan Bisma. “Ngaco!”
“Dih, nggak percaya! Tadi aja nantang-nantang!” tukasnya sambil mengusap tangan. “Serius, Ay. Di kantor aku terbuka besar peluang buat lanjut kuliah di luar negeri. Aku juga udah mulai nyiapin berkas buat apply beasiswa sekaligus daftar S2. Tapi sebelum itu, aku mau kita menikah dulu biar bisa ngajak kamu ikut ke sana, kalau sewaktu-waktu aku harus berangkat.”
Kelopak mataku berkedip-kedip, padahal jelas tidak ada sebutir debu pun yang menyangkut di sana. Selama beberapa menit aku hanya melongo seperti kerasukan jin mendadak. Begitu kesadaranku pulih, langsung kuraih centong kayu dan melayangkannya bertubi-tubi ke lengan Bisma.
“Aduh! Kamu kenapa sih, Ay? Nggak percaya lagi?” protes Bisma sambil mengernyit tak mengerti.
Aku memasang wajah cemberut. Kudaratkan pantat kembali sambil melempar ‘senjata’ secara asal ke meja. “Kesel aja! Habis kamu ngelamarnya nggak romantis sih, pake banget!” tukasku jujur yang langsung disambut tawa olehnya.
|***|
Meski adegan lamaran itu nggak se-‘so sweet’ Belva Devara yang jauh-jauh ke Massachusetts demi memberi kejutan pada sang kekasih, tetap saja hatiku seperti taman sakura yang penuh bunga berkelopak merah jambu bermekaran. Tak sedetik pun bibirku melepas senyum. Bahkan ketika Bisma terus mengoceh tentang beasiswa dan kampus yang akan ditujunya, pikiranku sudah terbang lebih jauh ke langit ketujuh.
“Ay, kamu dengerin aku nggak sih?” Tiba-tiba Bisma menceletuk. Aku menoleh dan menatapnya yang juga melihat ke arahku. Kebetulan mobil kami berhenti di persimpangan lampu merah.
“Eng ...,” Aku menggaruk kepala yang tak gatal. Lantas menyengir dengan tampang tak berdosa. “Sampai mana ya tadi?”
Bisma mengacak-acak kepalaku gemas. Jilbab segi empat yang kupakai sampai miring-miring karenanya. Untung saja lampu segera berganti warna jadi hijau sehingga ia tidak meneruskan aksinya.
“Kamu tuh, ya. Kebiasaan deh kalau udah seneng, nggak ingat sekitar!” celetuk Bisma sambil memindahkan persneling. Mobil pun mulai melaju perlahan. “Aku tadi cerita soal rencanaku lanjut ke Belgia. Aku nemu info soal beasiswa VLIR-UOS. Enaknya kita bisa apply beasiswa sekaligus studinya, jadi nggak perlu kerja dua kali.”
Aku manggut-manggut, padahal dalam hati bertanya-tanya sejak kapan ia punya rencana untuk mengambil gelar Master di negara Eropa tersebut. Namun, tak lama rasa penasaran itu menguap. Sejak dulu Bisma memang jarang melibatkan aku saat mengambil keputusan. Sebaliknya, untuk memilih sepatu saja aku perlu masukan dari orang lain. Mungkin itu sebabnya kami cocok. Bisma dengan segala kemandiriannya, dan aku yang seolah tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain.
Sekitar tiga puluh menit kemudian laju mobil mulai melambat. Suara roda yang menggilas batu-batu kecil menandakan kami sudah memasuki pekarangan rumah. Belum sempat mesin berhenti menggeram, aku sudah melompat turun. Berani taruhan, Bisma pasti sedang tertawa melihat tingkahku yang kegirangan seperti bocah baru pulang dibelikan mainan.
“Paa! Maa!” Tidak terdengar sahutan dari ruang tamu. Aku melangkah lebih dalam sambil kembali berteriak. “Papaaa!! Mamaa!!”
“Masyaallah, Ayaa! Ini udah malem dan kamu malah teriak-teriak kayak lagi di hutan!”
“Hehe.” Kutanggapi teguran Papa dengan cengiran lebar. Lantas kupeluk erat tubuh tambunnya agar beliau tidak marah lagi sekaligus menyalurkan rasa gembiraku.
“Assalaamualaikum, Om ….” Bisma rupanya sudah menyusul dan berdiri beberapa langkah di belakang. Papa menjawab salamnya sambil melirik jam di atas gawang pintu, sekadar memastikan cowok berkacamata itu mengembalikan putri kesayangannya tepat waktu. Pukul sembilan kurang lima menit, pas.
“Pa, Mama mana? Malem ini Aya sama Bisma bawa kabar gembira, loh!” tuturku bersemangat. Tak lama kemudian Mama muncul dari ruangan dalam sambil membetulkan jilbab instannya yang sedikit miring.
“Kabar gembira apa? Kulit manggis kini ada ekstraknya?” Mama malah bercanda sambil menaikkan kedua alisnya usil.
Aku berdecak. “Itu mah kabar basi, Mamaa!”
“Lha terus apa lagi? Jangan bilang kalau kalian berdua sudah kasih Papa sama mama cucu sekarang!?” Mama malah semakin ngawur. Saking kesalnya, aku mencubit lengan Mama gemas.
Sementara Bisma menikmati pertikaian kecil kami sambil tertawa. Tinggal menunggu waktu saja sampai ia juga menjadi bagian dari keluarga kecil ini. Ah, bibirku jadi melengkung lagi membayangkan hal itu.
Papa mengajak kami duduk di sofa ruang tamu. Aku bersebelahan dengan Bisma, menghadap Papa dan Mama yang tersekat meja persegi panjang. Kami saling melempar pandang seolah bertelepati menyepakati siapa yang maju menjadi juru bicara.
Bisma pun memulai dengan berdeham kecil. “Sebelumnya, saya minta maaf sama Om dan Tante jika ini terkesan mendadak dan kurang sopan. Insyaallah, secepatnya saya akan mengajak keluarga besar untuk acara resminya.”
Aku melirik ke kiri, memperhatikan wajah Bisma yang tegang padahal sudah jelas orang tuaku pasti menerima lamarannya. Rasanya lucu melihat cowok berkacamata bulat yang selalu percaya diri itu tiba-tiba kesulitan merangkai kata saat hendak menyampaikan tujuan.
“Ehm, jadi begini. Saya dan Aya tadi sudah bicara, dan ... kami sepakat untuk membawa hubungan ini ke tingkat yang lebih lanjut.
“Saya meminta restu dan izin dari Om dan Tante untuk menikahi Cahaya.”
Aku menahan napas selama beberapa detik. Kukira respons Papa dan Mama akan sama bahagianya seperti aku tadi. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka tidak ada yang bergerak ataupun bersuara. Aku sampai khawatir kalau mendadak orang tuaku terkena stroke saking terkejutnya anak mereka dilamar.
“Ma? Pa?” tanyaku setelah sekian lama hening. Aku berniat bangkit memeriksa kondisi mereka. Namun, Papa lebih dulu bergerak menepis kekhawatiranku terhadap hal-hal buruk yang mungkin terjadi.
“Ah, eh, iya. Wah, sudah malam ya ternyata. Nggak kerasa.” Lho, kok Papa malah ngomong ngelantur, sih?
Bisma tampak tidak kalah bingung. Namun yang bikin aku tidak habis pikir, ia malah menanggapi racauan Papa. “Eh iya, Om. Sudah malam ….” Lalu menggaruk tengkuknya dengan ekspresi sulit kuartikan. “Kalau gitu, saya pamit dulu, ya.”
“Lho, kok pamit, sih?” Aku yang berdiri tak terima. Kulirik Papa dan Mama yang sepertinya tidak berminat menahan calon menantunya bertahan lebih lama. Ada apa ini? Padahal sebelum-sebelumnya Papa sering menyinggung soal pernikahan saat Bisma datang ke rumah. Mama bahkan sering bilang ingin segera menimang cucu, meski diucapkan sambil setengah bercanda. Bukankah ini langkah paling masuk akal untuk segera mewujudkan harapannya?
“Nggak papa, Ay. Kayaknya Papa sama Mamamu juga ngantuk. Kapan-kapan aja dilanjut lagi.” Bisma tersenyum pengertian sambil menyentuh tanganku. Sebaliknya, justru aku yang merasa berkali-kali lipat tak enak dengannya.
Usai berpamitan dengan Papa dan Mama, aku mengantar Bisma sampai ke depan pagar. Perasaanku yang tadi semringah seperti dapat paket facial gratis selama setahun di salon langganan mendadak berantakan. Kutahan tangan Bisma sebelum ia membuka kunci mobilnya.
“Bisma, aku minta maaf banget, ya. Nggak tau kenapa Papa sama Mama kok kayak gitu. Mungkin mereka lagi ada masalah kali, ya. Atau ada tunggakan jatuh tempo yang lupa dibayar,” ujarku berusaha melucu. “Tapi aku bakal mastiin kok, kalau lamaran kamu diterima. Awas aja kalo enggak, nanti aku bakal mengeluarkan diri sendiri dari KK!”
Bisma tertawa kecil sambil mengusap kepalaku yang terbalut kerudung dengan lembut. “Nggak papa, Ay. Aku ngerti kok. Mungkin mereka kaget dan belum siap soalnya kamu putri satu-satunya.”
Aku tersenyum kecut. Kuraih tangannya yang masih berada di puncak kepala dan menangkupkannya ke pipiku. “Makasih banget, ya. Kamu emang calon suami yang paling pengertian.”
Bisma kemudian pamit dan meninggalkanku yang masih berdiri di depan pagar rumah. Senyum di bibirku menghilang bersamaan dengan bagian belakang mobil yang tak lagi tertangkap indra penglihatan. Aku segera berbalik dengan wajah dongkol.
“Papa sama Mama ada masalah apa, sih? Sampai kayak gitu sama Bisma!” protesku tanpa ba-bi-bu. Untung saja mereka belum kembali ke kamar. Jika tidak, mungkin aku cuma bisa meluapkan kekesalanku pada kursi. Sepertinya mereka juga baru selesai membicarakan sesuatu.
Papa dan Mama tampak tidak tersinggung dengan aksi kasarku barusan. Mereka malah saling melempar pandang, sebelum akhirnya kompak menjatuhkan tatapan padaku.
“Aya, sini deh. Mama sama Papa mau bicara penting sama kamu.”
Demi mendengar kalimat Mama barusan, rasa jengkelku langsung menguap. Puluhan tanda tanya berganti memenuhi kepala. Apa yang sebenarnya terjadi? Jangan-jangan Papa dan Mama sudah menjodohkanku dengan seorang CEO tampan yang berhati dingin. Atau yang lebih parah, diam-diam mereka telah menjualku pada pria tua beristri sembilan demi menutup hutang-hutang usaha? Hiiyh ....
Aku sudah hendak mengatakan keberatanku atas segala rencana perjodohan mereka saat Papa lebih dulu bersuara, “Seharusnya papa dan Mama sudah mengatakan ini sejak lama. Tapi ... kami selalu mengundur-ngundur, sampai tanpa sadar kamu sudah tumbuh dewasa dan sebentar lagi menikah.”
Aku masih diam menunggu sampai Papa selesai dengan ucapannya. Menyiapkan hati dan argumen kalau-kalau diperlukan. Lelaki baya itu tampak menarik napas berat, sementara Mama mengusap lengannya memberi dukungan.
“Aya, sebenarnya ... kamu bukan anak kandung kami.”