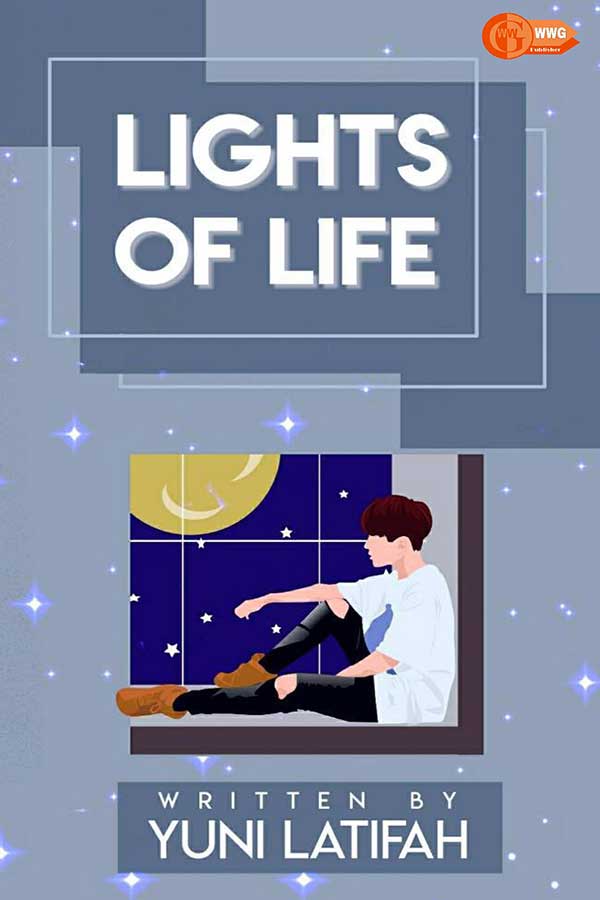
Lights of Life
By wwgpublisher
Ingar bingar musik masih mengentak-entak-membisingkan pendengaran dari sebuah pub di tengah kota Semarang. Meski waktu sudah lewat tengah malam, tetapi N-Pub—nama yang tertera di baliho besar di depan gedung dengan warna merah marun itu—masih diramaikan oleh lautan manusia yang sedang mencari kenikmatan duniawi. Manusia-manusia penikmat dunia malam. Perempuan-perempuan dengan pakaian setengah telanjang terlihat sedang meliuk-liukkan tubuh sintal mereka mengikuti dentuman musik yang dimainkan oleh seorang disc jockey. Sedangkan para lelakinya menatap mereka seperti seekor kucing liar yang lapar dan siap menerkam mangsanya.
Aroma nikotin hingga alkohol menguar dari berbagai sudut N-Pub. Mereka yang tidak ikut turun ke atas lantai dansa, lebih memilih menghabiskan seloki-seloki minumannya. Seperti salah seorang di antara mereka yang memilih duduk di sudut-sudut. Padang Purnama saat ini sedang jengah karena digodai oleh seorang wanita berambut ombre—wanita kelima malam ini yang berusaha merayunya.
Wanita itu belum menyerah, walaupun Padang sudah menolaknya secara halus. Menurutnya, laki-laki seperti Padang adalah tangkapan yang bagus untuk bisa diajak bersenang-senang meraih kenikmatan surgawi. Bagaimana wanita tersebut mampu menolak pesona seorang Padang Purnama yang berwajah rupawan? Padang dengan segala pesona dan kharismanya yang diakui oleh semua orang. Di kalangan para penikmat dunia malam, nama Padang Purnama sudah sangat dikenal. Para wanita menggilainya, sedangkan para lelaki segan kepadanya.
Padang menyesap cocktail rasa buah ceri miliknya. Malam ini dia tidak boleh banyak minum alkohol karena harus pulang ke rumah adiknya. Tatapan dingin masih dia berikan kepada wanita ombre yang kini duduk menyilangkan kedua pahanya yang mulus dan sengaja menarik ke atas rok span mininya yang sudah pendek.
“Do you wanna ‘eat’ me, Babe?” bisik wanita itu provokatif, membuat Padang sedikit tersedak cocktail-nya.
Padang tidak menyangka jika wanita yang merayunya kali ini akan begitu berani. Ya, seberani dia mengecat rambutnya dengan warna yang kontras dengan kulit sawo matangnya.
“Thanks for your offering, but I won't,” jawab Padang tegas.
Saat ini dia sedang tidak ingin bermain-main dengan wanita mana pun. Bukan. Dia bukan seorang pemain wanita— atau apa pun itu sebutannya—yang sedang malas bercinta dengan wanita. Namun, Padang hanya merasa tidak ingin meladeni rayuan mereka. Padang Purnama adalah orang yang setia, dia telah mengikrarkan diri hanya pada satu wanita. Ialah Hanggini, wanita yang baru saja beranjak dari lantai dansa dan saat ini sedang berjalan anggun ke arahnya.
Ujung gaun satin berwarna hitam yang dikenakan Hanggini jatuh bergerak-gerak seirama langkahnya. Matanya yang dibingkai maskara menatap penuh selidik ke arah wanita ombre yang duduk di samping Padang Purnama, prianya yang tak boleh disentuh siapa pun.
Hanggini tersenyum lalu duduk di atas pangkuan Padang dan mengecup bibirnya sekilas. Wanita itu ingin menunjukkan siapa di sini yang berkuasa atas Padang Purnama, lelakinya. Bahwa hanya Hanggini-lah yang boleh menyentuh laki-laki bermata hitam itu, bahwa Padang adalah miliknya. Hanya miliknya seorang.
Sang wanita ombre sedikit merengut melihat adegan di depannya. Meski kesal karena kali ini tidak bisa bersenang-senang dengan pria incarannya, wanita ombre itu pun berlalu, kembali ke kerumunan orang-orang yang sedang asyik berdansa.
“Kamu nggak godain dia, kan, Darl?” tanya Hanggini masih bergelayut di atas pangkuan Padang.
Padang tidak menjawab dan malah meraih leher jenjang Hanggini kemudian melumat singkat bibir merahnya. “Kenapa? Kamu takut aku berkhianat?”
“Aku tahu kamu nggak akan bisa melakukan itu, Darl.” Yakin Hanggini mantap dan kedua matanya menatap kedalaman mata Padang.
Padang menarik ujung bibirnya mendengar jawaban Hanggini. Sebuah senyum simpul yang memiliki banyak makna. Padang tahu dia tidak akan bisa pernah lepas dari jerat seorang Hanggini Claudia. Jerat yang awalnya cukup menyiksa, tetapi lama kelamaan sangat dia nikmati.
“Darl,” bisik Hanggini dengan suara parau, tapi masih terdengar jelas di telinga Padang. Tatapan matanya tiba-tiba berubah sayu. “I want you, now.”
Padang mengerti apa maksud Hanggini. Sebuah hasrat yang menuntut untuk dipuaskan. Sebuah naluri alami manusia yang memang diberikan oleh Sang Pencipta. Namun, atas hasutan setan dan iblis, mereka memuaskan naluri-naluri itu dengan cara yang salah. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Padang dan Hanggini yang saat ini sedang asyik bercumbu di remang-remang sudut N-Pub.
***
Padang Purnama tengah memarkirkan sepeda motornya di teras rumah. Gerakannya begitu pelan seakan takut suara sekecil apa pun akan membangunkan seseorang di dalam rumah. Suara tadarus berganti azan subuh yang terdengar sayup-sayup dari masjid yang berada tidak jauh dari rumahnya, menyadarkan laki-laki itu bahwa hari sudah menjelang pagi.
Benci. Itu yang dia selalu rasakan ketika mendengar seruan salat. Seruan yang membuatnya seperti ditohok berkali-kali dan merasa gelisah karenanya.
Dengan langkah sedikit tergesa, laki-laki dengan tatapan mata tajam itu membuka pintu rumah dan masuk. Keadaan di dalam rumah masih temaram, hanya lampu ruang tengah yang dinyalakan. Sepertinya Cahya belum bangun, batin Padang.
Dia berniat membangunkan adik perempuannya itu, satu-satunya keluarga yang dia miliki saat ini. Mereka hanya tinggal berdua saja, sedangkan orang tua mereka sudah meninggal beberapa tahun lalu.
Padang memutar kenop pintu kamar Cahya pelan, berusaha mengintip ke dalam. Adiknya itu tengah salat di samping tempat tidur. Padang terpaku melihat bagaimana adiknya itu salat dengan khusyuk. Gerakan salatnya yang terlihat mantap dan tidak terburu-buru, seolah tidak terganggu oleh hal apa pun. Sekali lagi hati Padang seperti ditampar. Sudah berapa lama dia tidak menghadap Allah?
Dalam hati kecilnya dia ingin sekali bisa kembali berhadapan dengan Sang Pencipta di dalam salat, tapi egonya terlalu besar. Egonya tidak pernah mengizinkan dia. Seketika dia teringat peristiwa lima tahun lalu yang membuatnya hancur seperti ini. Membuat dia tidak ingin percaya lagi dengan Kemahakuasaan Allah.
Beberapa menit Padang terpaku di tempatnya hingga Cahya mengakhiri salatnya dengan salam. Cahya yang menyadari keberadaan Padang di ujung daun pintu kamarnya langsung menghampiri laki-laki itu. Diambilnya tangan kanan Padang lalu mencium punggung tangannya.
“Mas Una baru pulang to?” tanya Cahya dengan logat Jawa yang kental. Senyum semringah pun tak lupa dia berikan pada kakaknya.
Padang tersenyum sekilas dan mengangguk. Selalu ada perasaan hangat yang dia rasakan ketika melihat Cahya tersenyum. Rasanya dia bisa menukar kebahagiaannya sendiri asal adik yang dia sayangi ini selalu bahagia. Ah, bukankah itu yang diam-diam telah dia lakukan selama ini untuk Cahya?
“Bosnya Mas Una kerjane apa to? Mesti, kok, lembur terus. Pergi pagi, pulang pagi,” gerutu Cahya.
“Kan, Mas udah sering bilang kalau kerjaan Mas jadi asisten pribadi bos. Jadi, kalau si bos belum selesai kerja, ya Mas belum bisa pulang,” jawab Padang. Ada sedikit rasa bersalah ketika dia membicarakan masalah pekerjaannya dengan Cahya. Sebagian memang benar, tapi sebagian lagi adalah sebuah kebohongan.
“Ya, tapi, kan Mas bisa izin pulang duluan gitu sama bose. Mosok bose ora ngizinke? (Masa bosnya nggak mengizinkan?) Kebangetan banget.”
Padang tertawa kecil. Adiknya jika sudah menggerutu seperti ini tidak akan habis-habis.
“Eh, malah ketawa? Aku itu serius, Mas.”
“Iya, Dek. Maafin Mas kalau lebih sering nggak ada di rumah.” Padang berusaha melunakkan Cahya yang sedang merajuk.
“Minta maaf aja terus sampai lebaran kucing.”
“Mana ada lebaran kucing, Dek?” Padang terkekeh sebentar.“Ojo nesu, mundhak ilang ayune (jangan ngambek, nanti cantiknya hilang).”
Cahya menghela napas pelan. Ada yang ingin dia bicarakan dengan Padang, tapi dia bingung. Takut-takut kalau menyinggung perasaan kakaknya.
“Kenapa Cahya Wulansabit?” tanya Padang kemudian saat bola mata adiknya bergulir berkali-kali ke kanan-kiri.
“Aku cuma ndak mau orang-orang ngomongin jelek tentang Mas Una,” aku Cahya dengan suara pelan.
“Maksudnya apa?” Padang menaikkan sebelah alisnya. “Orang-orang pada ngrasani (menggunjing) kalau Mas Una itu laki-laki panggilan. Bisa dibayar buat gituan sama tante-tante.”
Padang menelan ludahnya dengan berat. Entah kenapa kata-kata Cahya begitu menonjok perasaannya. Padang tidak pernah peduli apa kata orang lain tentang dirinya, meski sebagian gunjingan mereka benar, tapi orang-orang itu tidak pernah tahu apa yang Padang harus lalui untuk sampai di sini. Akan tetapi mendengar langsung dari mulut Cahya membuatnya seperti sedang melakukan sebuah dosa besar. Ah, benar. Apa yang sudah dilakukannya memang merupakan sebuah dosa besar. Apa dia peduli? Cih, Allah saja tidak peduli padaku.
“Udah, Dek. Kamu nggak usah dengerin gosip kayak gitu lagi,” ucap Padang sambil mengelus kepala Cahya yang tertutup mukena. “Kamu percaya sama Mas, kan?”
Cahya mengangguk. “Iya, aku percaya. Nafkah yang Mas Una kasih itu halal, to?”
Lebih tepatnya aku mencoba untuk percaya, Mas, batin Cahya. Bukannya Cahya selama ini tidak curiga dengan pekerjaan apa yang dilakoni Padang, dia hanya mencoba untuk tetap khusnudzon kepada masnya. Beberapa kali Cahya memang pernah melihat Padang saat dijemput seorang wanita dewasa dengan menggunakan mobil mewah keluaran Eropa. Cahya berusaha berprasangka baik bahwa itu adalah bosnya.
“Bagus,” gumam Padang. “Kalau begitu Mas mau ke kamar dulu, ya?”
Padang kemudian beranjak menuju kamarnya. Sebelum dia mencapai kenop pintu kamarnya, sebuah kalimat yang keluar dari Cahya kembali menohok hatinya.
“Mas, salat subuh dulu.”
Padang termangu. Tanpa menoleh Ke arah Cahya dia mengangguk kaku. Cahya yang ingin mengajak Padang untuk salat subuh berjamaah karena sudah iqomah, terpaksa menelan kembali kalimatnya melihat Padang yang langsung memasuki kamarnya tanpa kata-kata lagi. Ada rasa kecewa mendapati kenyataan bahwa kakak laki-lakinya kini jauh dari Sang Rabb.
***
“Mas, kamu tahu kenapa Bapak kasih nama kamu sama adikmu Padang dan Cahya?” Seorang pria paruh baya dengan kopiah putih sedang duduk berhadapan dengan anak lelakinya yang masih mengenakan seragam putih-biru yang terlihat lusuh oleh debu.
Padang yang meringis sambil mengelus pipi kirinya yang tampak lebam hanya menggeleng pelan. “Mboten (tidak), Pak.”
Bapak menghela napas pelan dan memberi jeda sejenak sebelum melanjutkan kembali perkataannya. “Bapak berharap kamu sama adekmu bisa jadi padange ngalam ndunyo (terangnya alam dunia). Bukan cuma buat Bapak sama Ibu, tapi buat orang-orang di sekitar kalian. Bapak pengin kalian bisa jadi terang buat orang-orang yang kalian sayangi.”
Padang remaja menunduk, lebih ke arah malu karena dia sudah mencoreng nama baik Bapak—yang lebih sering dipanggil Pak Haji itu—dengan berkelahi di sekolah tadi
“Sekarang Bapak nanya, cita-citamu pengen jadi apa kalau tiap hari kerjaannya berantem terus?”
“Dokter, Pak,” jawab Padang dengan suara pelan namun mantap.
“Bisa kalau mau jadi dokter tapi ndak serius belajar, malah tukaran (bertengkar) terus?”
Padang menunduk semakin dalam. Kepalanya sudah cukup pusing akibat pukulan yang diterimanya tadi.
“Ora iso, to? (Nggak bisa, kan?)” tanya Bapak retoris.
Padang menggeleng lagi sebagai tanggapan pertanyaan Bapak.
“Mau sepinter apa pun kamu, kalau ndak bisa serius belajar, ndak bakal bisa sekolah kedokteran.” Bapak menjeda kalimatnya. “Sekarang kamu mau gimana? Mau lanjut tukaran terus atau kamu berubah, Mas?”
Padang mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Bapak. Ada raut lelah di wajah teduhnya. Wajah Bapak terlihat jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Lelah mengurus anak lelakinya yang badung, lelah mengurus pekerjaan, lelah mengurus semuanya. Kini Padang tahu dia harus memilih apa.
“Belajar dengan serius, Pak.”