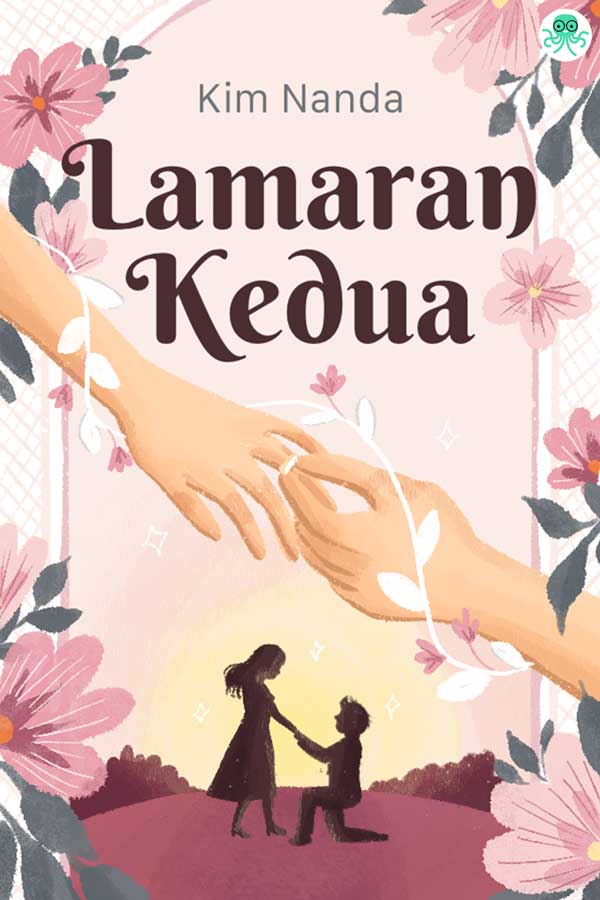
Lamaran Kedua
By Nanda Kim
Dari balkon kamarku, aku bisa dengan jelas melihat mobil putih terparkir di halaman depan. Tidak lama, dua orang laki-laki berbeda generasi keluar dari mobil. Laki-laki yang seusia Papa mengenakan batik lengan panjang berwarna hitam. Sementara yang posturnya tegap dan tinggi itu lebih kasual dengan celana bahan hitam dan kemeja biru pucat. Aku kenal keduanya, bahkan tanpa perlu menajamkan penglihatanku.
Sekarang aku mengerti kenapa Mamak sangat sibuk sejak pagi. Membersihkan segala penjuru ruang tamu, memesan makanan dan sejam yang lalu memintaku berganti pakaian rapi.
“Atri!”
Aku menghela napas panjang. Panggilan Mamak menjelaskan segala pertanyaan yang bergelayut di kepalaku. Belum sempat menyahut, teriakan Mamak kembali terdengar.
“Atri, kamu tidur?” Mamak mengetuk pintu kamarku tidak sabaran.
“Enggak!” Aku meninggalkan balkon kemudian menutup pintunya.
“Atri?”
Langkahku melebar ketika panggilan Mamak kembali terdengar. Aku menghela napas lalu menarik gagang pintu. Ujung bibir Mamak terangkat cepat begitu ia melihatku. Matanya yang semula lurus menatapku, kini turun perlahan hingga ujung kakiku.
“Anak Mamak cantik banget,” puji Mamak dengan senyum yang semakin melebar.
Sepertinya Mamak terlalu melebih-lebihkan. Ini bukan pertama kalinya aku mengenakan silver dress selutut ini.
“Ayo turun.” Mamak menarik tanganku lembut. Mau tidak mau aku harus turun dan bertemu orang yang sebelumnya aku lihat dari balkon kamar. Tanpa sadar aku menghela napas ketika kakiku mencapai tangga paling bawah. Berat sekali rasanya bertemu laki-laki itu.
Telingaku mendadak tuli saat Mamak menarikku untuk duduk di sampingnya. Entah apa yang mereka bicarakan, mataku sesaat terpaku pada laki-laki di hadapanku. Dia masih sama. Matanya yang dalam tanpa kelopak mata ganda dengan alis rendah. Bedanya hanya atas bibir yang meninggalkan jejak kumis tipis. Hingga akhirnya satu kalimat menyadarkanku sepenuhnya. Aku segera membuang muka.
“Maksud saya datang kemari, masih sama seperti tahun lalu. Saya berniat mengkhitbah Katrina Galuh Sanjaya untuk anak saya, Akbar Farabhi,” ucap Om Damar mantap.
Papa tertawa lepas membuatku menoleh cepat.
Apa-apaan!
Anaknya bingung setengah mati, Papa malah ketawa. Aku mendengus sebal kemudian melirik lagi Mas Abhi yang duduk di hadapanku bersama ayahnya, Om Damar. Lihat, lah! Dia malah tersenyum tanpa dosa! Mungkin dia pikir dengan melamarku untuk kedua kalinya, aku akan terima.
Cih! Tidak akan!
Tiba-tiba aku merasakan senggolan di lenganku. Aku menoleh malas dan langsung mendapat pelototan dari Mamak. Jangan-jangan Mamak mendengarku mendengus. Jangan salahkan aku. Itu spontan karena perasaanku tidak karuan sekarang ini.
Mengingat beberapa bulan yang lalu, Mamak meminta agar aku tidak lagi menolak lamaran yang datang. Aku tidak bisa mengatakan tidak waktu itu, bisa-bisa Mamak mengamuk, mengadu pada Papa dan selama beberapa hari ceramah demi ceramah akan terus masuk ke telingaku.
Tapi, siapa sangka lamaran selanjutnya justru datang dari Mas Abhi.
“Enggak usah formal gitu, lah. Kita sudah lama kenal,” kata Papa tersenyum cerah.
Om Damar dan Papa memang sudah lama saling mengenal. Jauh sebelum aku dan Mas Abhi terlahir ke dunia. Dari cerita yang sering Papa ulang-ulang, mereka berdua dulunya tinggal satu kosan.
“Lamaran itu sesuatu yang sakral, ya harus formal dong.” Om Damar tak mau kalah.
Papa melirikku sekilas, “Abhi, Om enggak nyangka kamu datang lagi ke sini.”
“Sesuka itu dia sama anakmu,” gurau Om Damar membuat Papa tertawa lepas. Lagi. Mamak juga sampai senyum-senyum sambil meremas tangan kananku.
Aku mau muntah boleh tidak, sih?
“Abhi, kamu tahu kan Katrina itu sifatnya kayak gimana? Om enggak habis pikir kamu kok bisa suka sama dia.”
Nah, makanya Pa! Aku juga bingung. Mas Abhi itu tipe pria yang bisa dengan mudah menggaet perempuan di luar sana. Yang jauh lebih cantik, mandiri, ramah, lemah lembut dan itu semua jelas berbanding terbalik denganku. Hmm, kecuali cantik.
Dia seperti tidak punya pilihan selain melamarku dua kali.
“Tau, Om. Dan itu semua enggak masalah buat saya,” jawab Mas Abhi mantap.
Papa mengangguk samar dengan tatapan penuh rasa kagum mendengar jawaban Mas Abhi. Detik berikutnya Papa menatapku serius, “Atri. Keputusan ada di tangan kamu, Nak.”
Aku menelan saliva dengan susah payah ketika Mamak berbisik di telingaku, “Ingat kata Mamak.”
Dari tatapan matanya, aku tahu Papa menaruh harapan besar pada jawabanku nanti. Sebesar itu keinginannya bisa membangun hubungan keluarga dengan Om Damar.
Aku menunduk sebentar lalu menatap lurus ke depan, “Aku boleh ngobrol dulu enggak sama Mas Abhi?”
“Atri….” desis Mamak.
“Boleh, mau ngobrol di mana?” sela Mas Abhi membuatku bisa terlepas dari amukan Mamak.
“Di teras aja, Mas,” usulku.
Mas Abhi mengangguk setuju.
Tanpa berlama-lama, aku bangkit dari dudukku setelah tersenyum singkat ke arah Om Damar. Aku melangkah cepat diikuti Mas Abhi, melewati teras dan berhenti ketika cukup jauh dari rumah. Ini jarak yang pas dan tidak akan ada yang dengar.
“Maksud Mas apa, sih?” serangku begitu Mas Abhi berdiri di hadapanku.
Alis Mas Abhi terangkat tinggi, “Aku enggak maksud apa-apa.”
Aku menghela napas kasar, “Kenapa harus aku sih, Mas?”
“Apa salahnya kalau aku milih kamu?”
Keningku mengernyit, “Mas enggak ada pilihan lain? Mau aku bantu cari?”
“Enggak perlu.”
“Oke,” aku mengedikkan bahu tak acuh. “Maaf Mas, jawaban aku tetap sama seperti tahun lalu.”
“Kalau cuma ini yang pengin kamu omongin, kenapa enggak di dalam aja? Inti dari pembicaraan ini, kan, kamu nolak aku,” katanya Mas Abhi tenang.
Enak saja! Aku masih mau hidup tenang, Mas! Aku bisa babak belur jika menolak Mas Abhi secara terang-terangan di depan Mamak. Mendadak telingaku seperti diterpa hawa panas membayangkan ceramah Mamak nantinya.
“Aku enggak mau Mas Abhi malu. Makanya aku ajak ngobrol di luar. Dengan begini, kan, Mas bisa langsung pamit pulang. Bilang aja ada urusan mendadak,” kataku diakhiri kendikan bahu.
Mas Abhi tersenyum sebentar, “Kamu bukan perempuan yang peduli sama perasaan orang lain.”
Sialan! Dia tahu aku bohong.
“Kalau kamu belum siap, aku kasih kamu waktu untuk pikir ini matang-matang. Dan dalam jangka waktu itu, aku bakal berusaha bikin kamu yakin terima lamaran aku.”
Aku mendengus dan melipat tanganku di depan dada, “Kamu masih sama kayak dulu, semaunya sendiri!”
Mas Abhi mundur selangkah lalu menjejalkan kedua tangannya ke dalam saku celana, “Dan kamu juga masih sama egoisnya seperti dulu.”
Dia menatapku teduh, sementara aku? Tentu saja tatapan sinis dan ingin menerkamnya sekarang juga. Aku masih belum mengerti kenapa harus aku dari sekian banyak perempuan di dunia ini!
“Ehmm.”
Aku langsung menoleh ke arah pintu ketika dehaman seseorang menginterupsi kami berdua.
“Belum selesai?” tanya Mamak.
“Belum.”
“Sudah, Tante.”
Aku melirik Mas Abhi. Lihat, kan? Kami tidak ada cocok-cocoknya sama sekali. Dari jawabannya saja sudah berbeda.
“Selesain dulu kalau gitu, jangan lama-lama. Atri ingat pesan Mamak.”
Entah ini ke berapa kalinya Mamak menyampaikan hal yang sama. Tanpa diingatkan pun, kalimat itu terus saja berputar di kepalaku.
“Masih ada yang mau kamu omongin?” tanya Mas Abhi ketika pintu kembali tertutup.
“Intinya aku enggak akan terima Mas Abhi,” ucapku mengalihkan pandangan.
“Alasannya?”
Aku menarik napas kasar bersiap menjawab namun Mas Abhi lebih dulu memotong. “Jangan bilang alasan kamu masih seperti tahun lalu?”
Aku mengangguk, “Kita enggak cocok, Mas. Dan enggak akan pernah cocok.”
“Oke.”
Kepalaku menoleh cepat. Secepat yang aku bisa. Apa katanya barusan? Telingaku masih berfungsi dengan baik. Kalau aku tidak salah dengar, Mas Abhi bilang oke, kan?
“Kamu bisa jelasin itu di dalam,” katanya kemudian berlalu begitu saja.
Aku berusaha menyusul langkahnya, “Eh? Tunggu! Mas, Mas!” lalu menarik ujung kemejanya.
Mas Abhi berhenti. Melirik tanganku lalu naik menatap kedua mataku.
“Jangan.”
Alis berantakannya saling bertaut, “Jangan apa?”
Aku membasahi bibirku yang mendadak kering, “Jangan masuk. Kita negosiasi dulu. Denger ya, Mas. Aku enggak mungkin nolak Mas Abhi secara terang-terangan di depan Papa sama Mamak.”
Air muka Mas Abhi sama sekali tidak terbaca. Aku tidak tahu dia setuju atau tidak. Setelah beberapa detik diam, Mas Abhi melepas tanganku yang menahan kemejanya dan menarikku ikut masuk rumah.
“Mas, tunggu! Kita belum selesai ngomong.”
Oh, tidak. Jangan sampai Mas Abhi menceritakan penolakanku barusan.
***
Aksi tarik-menarik antara aku dan Mas Abhi masih berlanjut bahkan hingga kami berdiri tak jauh dari kursi yang diduduki para orang tua. Dengan susah payah, aku memaksa ujung bibirku terangkat.
“Jadi?” Mamak menangkap tangan kami yang saling bertaut dengan mata berbinar.
Aku mengikuti arah pandang Mamak dan cepat-cepat menarik tanganku. Tanpa aku duga, Mas Abhi malah merangkul bahuku hingga sisi kanan tubuhku merapat ke arahnya. Papa dan Om Damar kompak memamerkan senyum merekah. Sementara aku? Jangan tanya. Aku mematung, tidak berani mendongak untuk melihat Mas Abhi.
“Sepertinya ada kabar baik,” ujar Om Damar yang segera disambut anggukan oleh Papa.
Mas Abhi tertawa singkat, “Sebenarnya bukan kabar baik, tapi bukan kabar buruk juga.”
Papa dan Om Damar saling melempar tatapan bertanya-tanya. Iya, jangankan mereka. Aku juga tidak tahu apa yang sebenarnya Mas Abhi rencanakan. Seandainya hanya ada kami berdua, perutnya sudah kusikut sekuat tenaga karena berani merangkulku dan memutuskan sesuatu secara sepihak.
“Jadi, kami sepakat jawaban lamaran hari bakal Atri jawab bulan depan.”
Aku menoleh cepat. Kapan aku dan dia menyepakati sesuatu?
"Maksudnya?" Suara Papa mengalihkan pandanganku.
“Aku mau kasih Atri waktu, Om. Dan dalam jangka waktu itu, aku akan buat Atri semakin yakin untuk terima lamaran aku.”
“Mas, kapan aku setuju?” bisikku tenang. Senyum tipis masih aku pertahankan di depan Mamak.
Mas Abhi sedikit menunduk, mendekatkan bibirnya ke telingaku, “Mau enggak mau, kamu akan setuju.”
Tidak aku sangka, Papa dan Om Damar mengangguk setuju. Dan Mamak menjadi orang yang paling semangat mendukung usul Mas Abhi.
Aku bagaimana?
Apa yang bisa aku lakukan jika Mamak sudah setuju?
Tidak ada selain pasrah.
***