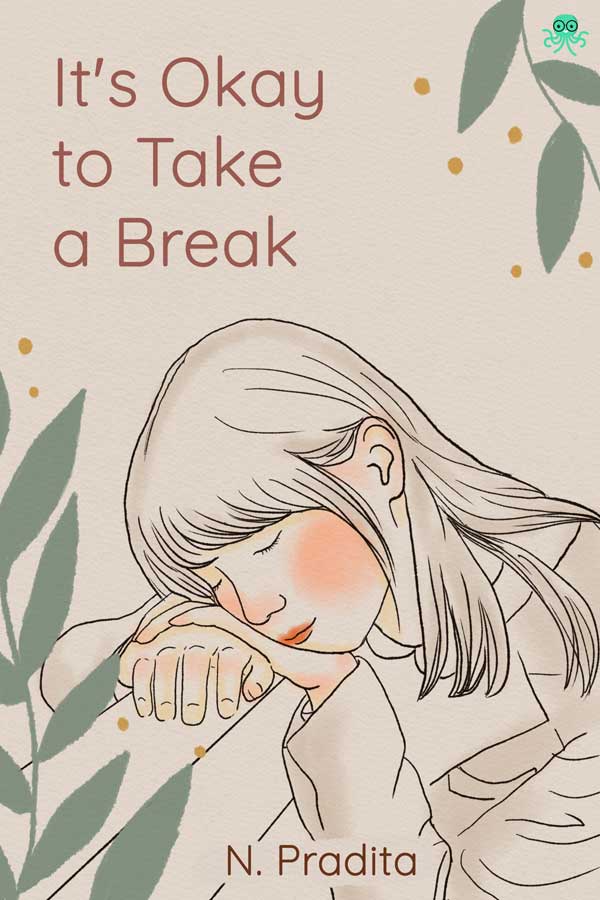
It's Okay to Take a Break
By N. Pradita
Semua akan baik-baik saja, selama orang-orang tidak tahu kebenarannya.
Gadis dengan rambut menjuntai sebahu itu melangkahkan kaki dengan mantap setelah turun dari bus. Hanya dengan satu tarikan napas, senyumnya mengembang hingga kedua manik mantanya nyaris tenggelam. Dia berjalan menyusuri trotoar menuju sekolah. Sepanjang jalan, orang-orang yang memakai seragam yang sama dengannya menyapa.
“Pagi, Ra!” Begitulah ucapan yang keluar setiap kali mereka melintas.
Yara, gadis yang tidak pernah lepas dari senyuman itu selalu membalas sapaan tersebut meski dia tidak mengenal setiap orang yang menyapanya. “Pagi!”
Satu kalimat yang kemudian orang-orang bisikan setiap kali Yara membalas ucapan mereka, “Gila, gue disapa balik!” Lagi pula, siapa yang tidak mengenal Yara di sekolah. Dia bagai malaikat yang selalu dipuja oleh orang-orang di lingkungannya. Orang-orang di sekitarnya ingin dekat dengannya. Bisa disapa oleh Yara saja mereka sudah kegirangan seperti mendapat undian miliaran rupiah.
Bukan hanya kalangan siswa saja, di antara guru-guru, Yara juga disenangi karena nilai-nilainya yang memuaskan. Gadis itu seakan menjadi idola tersendiri karena tidak banyak bertingkah seperti siswa lain. Satu kata yang dapat menggambarkan Yara: sempurna.
Maka begitulah, hari-hari Yara di sekolah begitu menyenangkan. Tidak ada gangguan dan begitu tentram. Iya, setidaknya seperti itulah harapan gadis itu.
***
“Yara!!” Sang pemilik nama terlonjak kaget saat seseorang melompat dan merangkulnya dari belakang.
Jantung Yara hampir saja melompat keluar jika tidak mengetahui siapa pemilik tingkah menyebalkan itu. “Leni?! Bisa nggak sih, biasa aja kalau nyapa?” Yara bersungut, melepas tanggan Leni yang menggantung di bahunya, meski akhirnya dia tetap tertawa juga.
“Itu juga udah biasa kali. Tiap pagi kan juga gitu, ya nggak, Mon?” Leni membela diri, meminta persetujuan dari Monica yang datang bersamanya.
“Iya, lo kayak nggak tahu tabiat Leni aja, Ra. Dia kalau nggak teriak-teriak kayak monyet emang nggak bisa.” Monica dan Yara cengengesan.
“Sial! Kampret emang lo pada!” Leni pura-pura marah. Dia mendesis kemudian berjalan menuju kelas mendahului kedua temannya.
“Ah nggak seru, gitu aja ngambek.” Yara menyusul bersama Monica di belakangnya. Satu-dua siswa mengamati mereka, atau lebih tepatnya mengamati Yara. Ingin rasanya menjadi Leni dan Monica yang dengan bebas bisa berbicara dengan Yara setiap hari.
“Emangnya, gue itu lo, Ra? Yang nggak bisa marah?” Leni berkata sambil lalu. Yara yang mendengar ucapan itu hanya tersenyum simpul.
Nggak bisa marah ya?
“Eh! Stop! Stop!” Tiba-tiba Leni menghentikan langkah. Kedua tangannya merentang ke samping. Mau tidak mau, Yara dan Monica yang mengekorinya ikut berhenti.
“Apaan sih, Len?” Monica celingukan, mengikuti arah pandang Leni yang tertuju ke lapangan.
“Itu, si Gavin, kan?” Leni menunjuk seorang siswa yang sedang menggiring bola di lapangan. Langkahnya gesit menghindari lawannya seraya menuju ring basket yang tinggal berjarak dua meter itu.
Penasaran, Yara mencoba mengikuti arah pandangan Leni. “Gavin?” Yara memang dikenal oleh orang-orang di sekolahnya tapi, gadis itu hanya mengenal beberapa orang saja dan itu tidak termasuk dengan cowok yang sedang menjadi bahan pembicaraan mereka.
“Iya, itu lho ... yang sering menang lomba karya ilmiah. Masa lo nggak tahu sih, Ra?” Leni menepuk jidatnya. Gavin sama terkenalnya di sekolah seperti Yara dan temannya itu tidak tahu? Yang benar saja.
“Ya wajar lah, Gavin kan jarang masuk sekolah, sukanya ke luar kota ikutan lomba ini itu. Piala yang dipajang sekolah aja mungkin separuhnya punya Gavin.” Monica menambahi.
“Gitu, ya?” adalah tanggapan Yara setelah mendengar penjelasan singkat kedua temannya. Leni dan Monica hanya saling pandang mendapat respon pasif dari temannya itu. “Yaudah yuk, masuk kelas. Bentar lagi bel. Kalau telat bisa diciduk Pak Wawan ke ruang BK.”
“Aer kali diciduk.” Leni menimpali dan seketika mereka bertiga tertawa, tidak sadar ada sepasang mata yang mengamati mereka.
***
Dengan santai, Yara meletakkan spidol ke tempatnya setelah berhasil menyelesaikan soal trigonometri yang diberikan oleh gurunya. Decak kagum teman sekelas mengiringi langkah Yara kembali ke bangkunya.
Pak Slamet, guru setengah baya itu pun memukul papan tulis dengan penghapus, membuyarkan kekaguman siswanya agar bisa fokus kembali ke pelajaran. “Harusnya kalian bisa seperti Yara yang dengan mudah mengerjakan soal-soal yang bapak berikan. Sebentar lagi kalian kelas tiga, kalian harus rajin belajar, tanya dengan Yara jika kesulitan kalau tidak mau bertanya dengan bapak.”
Pak Slamet menghela napas lelah, merasa frustrasi melihat siswa didiknya yang selalu ogah-ogahan saat menerima pelajaran matematika. “Yara, bantu teman-temanmu, ya?”
Menerima titah dari gurunya, Yara mengangguk mengiakan. Entah sudah berapa guru yang meminta bantuannya untuk mengajari teman-temannya dan gadis itu senang-senang saja melakukannya.
“Lo kayaknya cocok deh jadi guru, Ra,” bisik Leni yang duduk di sebelah Yara. “Lo lebih mumpuni sih ngajarinnya dibanding Pak Slamet.”
Yara tersenyum, lalu ikut berbisik, “Lebih mumpuni atau lo-nya aja yang sebenernya tinggal copas jawaban gue?”
“Ya ... lo udah tahu jawabannya ngapain pakai tanya, sih? Bikin malu aja.”
“Lo kan nggak punya malu, Len.” Monica yang duduk di belakang keduanya menimpali.
“Suka-suka kalian, deh!” ketus Leni, jika bukan karena jam pelajaran, dia pasti sudah menoyor kedua temannya itu.
Melihat Leni yang masih bersungut di sebelahnya, Yara tersenyum. Ini adalah hari yang selalu diimpikannya. Tenang dan damai. Rasanya, Yara tidak ingin kehilangan momen-momen seperti ini. Jangan sampai.
***
Yara merenggangkan otot tubuhnya, sesekali menghela napas panjang sebelum mengemasi buku-bukunya ke dalam tas. Bel pulang sekolah yang terdengar indah dan melegakan bagi teman-temannya, terasanya menyayat di telinga Yara. Dia tidak ingin cepat pulang seperti kebanyakan siswa lain. Yara ingin lebih lama di sekolah bersama teman-temannya. Sungguh, dia tidak ingin pulang.
“Ra!” tepukan Leni di bahu Yara menyadarkan gadis itu dari lamunannya. “Lo kenapa, sih? Kebiasaan deh, kalau mau pulang ngelamun dulu.”
“Anak pinter mah beda sama remah rengginang macem kita, Len. Penginnya belajar mulu tuh pasti.” Monica sudah bersiap menggendong tasnya. “Yuk, ah. Katanya mau ngerjain tugas bareng.”
“Aaaaah, gue males! Kenapa sih di sekolah udah belajar, pulang masih ngerjain tugas! Bisa botak gue!” Leni menggerutu, kemudian menggamit lengan Yara yang hendak bangkit dari tempat duduknya.
“Hari ini kita ngerjain tugasnya di rumah lo ya, Ra? Bosen gue kalau di rumah Monica atau di rumah gue,” pinta Leni dengan wajah yang dibuat sememelas mungkin.
“Hah?” kaget Yara, takut salah mendengar permintaan temannya itu.
“Hah, hah, hah, hah, emang gue kelomang apa pakai di-hah-hah-in?” Mendengar gurauan itu Monica dan Yara tertawa seraya membanyangkan kelomang yang sering mereka mainkan waktu kecil.
“Ehm ....” Yara berdeham menghilangkan serak di tenggrokannya akibat banyak tertawa. “Sorry, Len. Hari ini nggak bisa kalau di rumah gue,” ucapnya seraya menangkupkan kedua tangan, tidak lupa Yara menambahkan senyuman yang selalu menjadi andalannya itu.
“Heran deh, susah banget ke rumah lo, Ra. Nyokap-bokap lo segalak apa sih sampai kita nggak bisa main ke sana?” Monica merangkul bahu Yara. Entah sudah berapa kali mereka ditolak saat ingin berkunjung ke rumah temannya itu. Tidak pernah satu kali pun Leni dan Monica menyambangi rumah Yara. Bahkan hanya sekadar alamat saja, mereka berdua tidak tahu.
“Ya ... adalah pokoknya. Kalau bisa pasti gue undang, deh.” Yara mengacungkan jari kelingking kanannya sebagai bukti perjanjian. Leni dan Monica saling berpandangan. Mereka berdua sama-sama menghela napas panjang seraya mengedikkan bahu sebelum menyeret Yara keluar dari kelas.
“Yaudah, gantinya kita nyontek tugas lo aja!” tandas Leni dan Monica.
“Yeee ... biang aja mau nyontek dari awal! Pakai alesan ngerjain tugas bareng segala.” Gema tawa ketiganya menjadi pengiring langkah mereka keluar dari area sekolah.
***
Langkah kaki Yara berhenti tepat di depan pintu rumahnya. Lagi-lagi ada helaan napas panjang yang keluar dari mulutnya. Matanya melirik singkat jam tangan yang melingkar manis di pergelangan. Pukul enam sore. Bersama semilir angin yang menusuk kulit, tangannya mengusap kasar wajahnya yang lelah. Malas, Yara membuka pintu rumahnya dengan ragu-ragu dan hal pertama yang dia dengar adalah ....
“Kamu bisa ngertiin aku nggak, sih? Aku itu capek habis kerja!”
“Kamu pikir aku nggak kerja, hah?!”
“Kamu itu harusnya di rumah! Ngurus anak sama suami!!”
“Oh gitu, aku di rumah biar kamu bisa seenaknya keluyuran sama wanita lain sampai malam, iya?”
“Kamu apaan, sih?”
“Kamu itu yang apaan?! Cari duit nggak becus, masih aja mau selingkuh! Berapa banyak duit yang ka—”
PRAANG!!
Yara tersenyum getir bersamaan dengan suara vas bunga yang jatuh ke lantai. Perasaannya saat ini sehancur pecahan vas bunga yang berceceran tersebut. Manik matanya melirik siluet kedua orang tuanya yang sedang beradu di ruang tengah. Mereka bahkan tidak peduli apakah Yara sudah pulang atau tidak.
Sungguh, sambutan yang begitu luar biasa yang harus dia rasakan setiap hari. Jika seperti ini, bagaimana bisa Yara mengundang teman-temannya ke rumah? Bahkan bangunan itu tidak bisa Yara sebut sebagai rumah. Baginya, sudah tidak ada lagi tempat untuk pulang.
Siapa yang bakal nyangka kalau keluargaku sehancur ini?
***