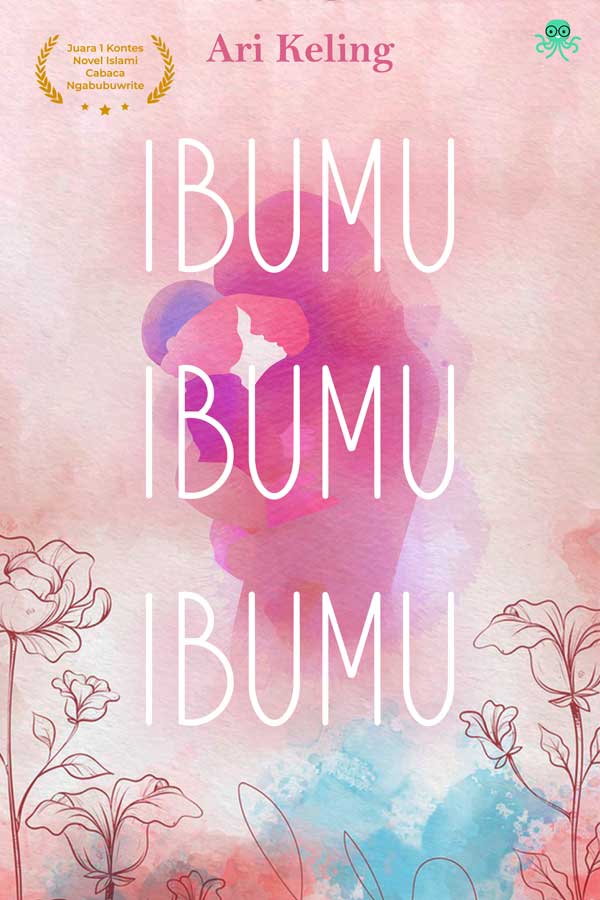
Ibumu, Ibumu, Ibumu
By Ari Keling
Sebuah mikrolet berhenti di depan Gang Melati. Seorang penumpang lelaki ke luar dari angkutan kota berwarna biru telur asin itu. Lalu, dia membayar ongkos kepada sang sopir. Lelaki berkulit sawo matang ini sempat terpaku sejenak saat angkot kembali melaju. Dia membalikkan badan dengan perlahan sambil mengusap rambut agak ikalnya yang gondrong sebahu. Kedua matanya yang sayu memandang lurus ke dalam gang yang hanya cukup dilalui dua sepeda motor secara berlawanan. Di siang yang cukup terik ini hidung bangirnya kembali mencium aroma masa lalu, yang serta-merta membuatnya menahan sedu. Dia mengembuskan napas perlahan sembari mengusap kumis dan janggutnya yang tumbuh tak rapi. Sementara dalam dadanya doa menggema tiada henti.
Lelaki berusia 28 tahun ini mulai melangkah. Terlihat berat dan sangat hati-hati. Di matanya, gang itu seolah banyak duri. Sehingga dia tampak ragu, namun tetap hati-hati berjalan maju. Hari ini memang sudah sangat lama dia tunggu. Namun ada ketakutan yang tak bisa ditutupi, bahwa penolakan tak lama lagi bisa saja dia dapati. Maka dari itu ayunan kedua kakinya begitu pelan, tetapi dia sadar betul jangan sampai kehilangan harapan.
Sementara itu. Beberapa orang yang melihatnya terheran-heran. Dari mereka ada yang membatin seperti mengenalnya. Ada yang benar-benar lupa. Ada pula yang saling berbisik satu sama lain; menebak-nebak siapakah lelaki yang seperti tengah memikul berkarung-karung dosa masa lalu itu? Lain lagi dengan seorang ibu yang sedang merapikan jemuran di teras depan rumahnya, dia langsung mengingat lelaki itu sambil bergumam, “Abang.”
Lelaki yang disebut Abang ini terus saja melangkah, masih tetap dengan ayunan kaki yang lemah. Dengan rasa malas dia sekilas memerhatikan orang-orang yang melihatnya. Dia cukup paham mengapa orang-orang itu menampilkan wajah seperti menelanjanginya. Dia tak dapat tersenyum untuk sekadar menyapa para tetangganya yang sudah agak dia lupakan, dan belum ada niat untuk mengingat-ingat. Kemudian dia menunduk dan terus menuju sebuah rumah bercat putih kusam bernomor 26.
Abang, si lelaki bertubuh tinggi dan kurus ini berdiri di depan rumah yang sangat sederhana itu. Dia menelan ludahnya yang mendadak terasa kelu. Kembali ada takut dan ragu yang membelenggu. Diaturnya napas agar bisa tenang. Dirapikannya kaus abu-abu yang dia pakai. Dia juga memeriksa celana jin krem kusam yang dikenakannya. Dilihatnya pula sandal jepit dengan lis berwarna biru yang menjadi alas kakinya. Sekali lagi dia memastikan bahwa sudah sangat siap untuk bertemu Emak, yang entah bagaimana tanggapan orang tuanya itu saat kembali melihatnya.
Abang menoleh ke kanan dan kiri. Lalu kembali memandang pintu di depannya yang berwarna cokelat tua. Dia tahu betul beberapa orang tengah memerhatikannya. Bukan karena merasa dia orang asing, tetapi kini semua mata seolah berbicara dengan tanya, apa yang kali ini akan terjadi pada dirinya. Dia tidak peduli, lantas perlahan menggerakkan kaki.
Detik ini Abang sudah berdiri di dekat pintu. Sekali lagi dia menghela napas panjang. Diembuskannya lagi dengan penuh beban. Sementara dalam hatinya doa terus dipanjatkan. Saat ini memang itu yang perlu dia perbuat, dan segera melakukan segala rencana yang sudah dirancang sekian lama.
Dengan gerakan perlahan tangan kanannya terangkat. Diketukannya daun pintu sebanyak tiga kali sambil mengucapkan salam. Lantas diam sejenak. Abang merasakan debaran jantungnya kian tak keruan. Sementara para tetangga yang menyaksikan itu juga cemas.
“Assalamu’alaikum ...,” kata Abang lagi sambil mengetuk daun pintu tiga kali untuk kali kedua.
“Wa’alaikumussalam ...,” jawab dari dalam rumah dengan suara agak serak dan berat.
Abang tahu betul itu suara siapa meski sudah tujuh tahun tak mendengarnya. Ah, dia rindu sekali suara itu. Suara yang kini malah membuatnya merasa sangat takut. Namun, dia harus bertemu dengan si pemilik suara tersebut.
Gagang pintu mulai bergerak.
Abang spontan mundur satu langkah. Dia begitu gelisah. Sementara doa dalam dadanya bersuara lebih keras. Sedangkan kedua matanya mulai memanas.
Pintu terbuka.
Abang mendapati seorang perempuan dengan wajah banyak kerutan memandangnya penuh heran. Meski begitu, perempuan berkulit sawo matang itu masih terlihat kuat dan segar di usia yang mulai menuju senja. Dia diam belum mampu berkata-kata. Diperhatikannya perempuan itu yang mulai melihatnya penuh curiga.
Abang menelan ludah dengan kegelisahan yang kian bertambah. Matanya yang tadi sudah memanas langsung berkaca-kaca. Bibirnya bergetar seraya terbuka.
“Kamu siapa?” tanya perempuan berusia 55 tahun itu. Rambut panjangnya sudah beruban dan dikucir menggunakan karet gelang berwarna merah.
Abang belum bisa menjawab. Mulutnya masih ternganga. Kini bukan hanya seisi dadanya bergetar, tetapi juga tubuhnya mulai terasa lemas. Rasanya dia ingin menubruk tubuh tua di depannya itu. Memeluk, memohon ampun, dan menangis sejadinya.
“Kamu siapa?” tanya perempuan yang mengenakan daster cokelat dengan motif bunga-bunga kecil itu.
“Ini—” Air mata Abang bergulir ke pipinya. “Ini—” Tenggorokannya seolah tersumpal sesuatu.
Perempuan itu mulai teringat. Kemudian berucap, “Kamu—”
“Ini Abang, Mak.” Tiba-tiba saja Abang berucap menyela perkataan Emak. “Ini Abang, Mak,” katanya lagi sambil menyentuh dadanya, sementara air matanya terus berjatuhan.
Dada Emak mendadak sesak, tetapi dia berusaha tenang. Dia pura-pura tak mengenal lelaki di depannya itu. Kedua alisnya bertaut, sedangkan kedua matanya memicing. Dia tampak berpikir, padahal tidak. Ada pergolakan batin yang hebat dalam dadanya, dan mati-matian dia tutupi.
“Ini Abang, anak Emak,” ucap Abang lagi dengan heran melihat Emak yang tampak tak mengenalnya.
Apakah benar Emak telah melupakan Abang? Ataukah memang itu faktor usia yang membuat Emak sudah pikun kepada salah satu anaknya itu?
“Saya cuma punya dua anak laki-laki,” sahut Emak kemudian. “Yang satu masih sekolah dan belum pulang, yang satu—”
Abang menyela perkataan Emak, “Mak, ini Adri Suseno, Mak,” terangnya menyebut nama aslinya. “Gak mungkin—”
“Saya cuma punya dua anak laki-laki!” kata Emak balas menyela sekaligus mengulang perkataannya yang tadi, tetapi kali ini suaranya lebih keras. Sehingga Abang terdiam dan mendengarkannya. “Yang satu lagi namanya Budi, orang-orang memanggilnya ‘Baba’. Semenjak Baba dibunuh orang, saya gak punya anak laki-laki lagi yang seumuran kamu! Jadi, kamu jangan ngaku-ngaku anak saya!” sambungnya dengan suara yang masih cukup keras.
Abang tak percaya mendengar ucapan Emak. Dia begitu syok menyimak penuturan Emak yang sungguh di luar prediksinya—bukan soal penolakan maaf, tetapi tidak diakui sebagai anak lagi. Dia mulai terisak. Sedangkan seisi dadanya terasa meledak. Sebab, detik ini dia paham. Emak bukan tidak mengingatnya. Emak bukan pikun. Emak memang sudah tidak mengakuinya sebagai anak setelah dia membunuh kakak lelakinya itu.
“Mak, ampuni saya ...,” ucap Abang dengan air mata yang terus jatuh membasahi kedua pipinya. Sementara dia terus berusaha agar tangisnya tidak meledak dan membuat keramaian yang pasti tidak diinginkan Emak.
“Pergi!” seru Emak.
Para tetangga hanya mampu melihat kejadian itu. Tak ada yang berani berkomentar atau mendekati untuk melerai atau menenangkan Emak.
“Mak, saya—”
“Pergi ...!!!” teriak Emak lagi dengan tangan kanan terangkat. Dia benar-benar mengusir Abang.
Abang kaget sekali. Dia tidak menyeka air matanya yang terus merembas dari sudut-sudut kedua matanya. Dia merasa sangat terpukul. Perkataan Emak umpama godam yang menghantam, dan menguburnya lebih dalam.
Beberapa orang ke luar dari rumah mereka karena teriakan Emak. Kini, lebih banyak tetangga menyaksikan seorang anak yang sudah tidak diakui orang tuanya lagi. Ada keharuan yang tak bisa dijelaskan pada batin masing-masing. Semuanya hanya bisa melihat tanpa tahu harus berbuat atau berucap apa. Dan tentu semuanya jadi teringat kejadian di masa lalu—kurang-lebih tujuh tahun silam.
Abang mundur sampai ke jalan. Napasnya keluar masuk tak keruan. Kedua matanya kian memerah. Hidungnya tersumbat. Akhirnya dia tak kuasa menahan lonjakan air dari kelenjar air matanya. Dia tak peduli banyak mata yang melihatnya menangis. Dia hanya tak tahu harus melakukan apa. Ya, tujuh tahun dia di penjara setelah membunuh Baba. Tujuh tahun dia merasa berdosa—bahkan seumur atau sisa hidupnya. Tujuh tahun dia memohon ampunan pada Tuhan. Tujuh tahun berharap setelah bebas Emak mau memaafkannya. Tujuh tahun berusaha membenahi diri. Tujuh tahun menunggu-nunggu bertemu Emak lagi. Rencana Tujuh tahun itu pun hancur hanya dengan kurang dari lima menit. Tujuh tahun dia merasa seluruh doanya tak pernah sampai ke langit.
Dengan berlinang air mata Abang melangkah meninggalkan tempat itu. Dia butuh maaf dari Emak. Sebab jika tidak, mungkin Tuhan pun enggan mengampuninya. Itu yang dia tahu. Sehingga dia ingin sekali diberi kesempatan kedua, tetapi rupanya Emak, bahkan mungkin dunia tak akan mudah memberikannya itu. Dia sudah dicap sebagai pembunuh!—orang yang tak bisa diampuni.
***