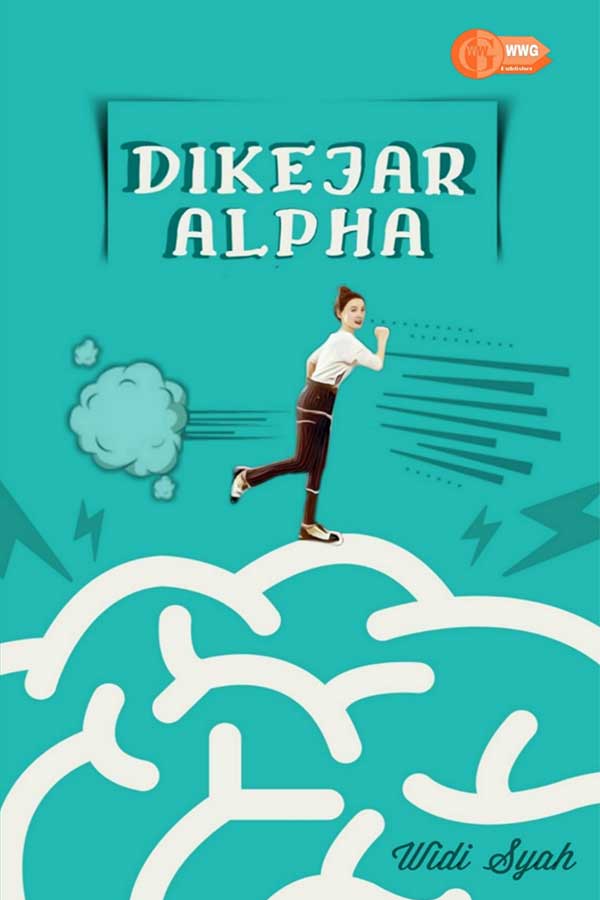
Dikejar Alpha
By wwgpublisher
PROLOG
Lelaki dengan dua atau tiga pacar mungkin saja sudah biasa. Banyak lelaki yang menduakan pacarnya tanpa ketahuan. Lelaki yang poligami pun mulai tak terhitung. Ibaratnya jamur di musim hujan.
Bisa jadi hal itu disebabkan karena populasi perempuan dua persen lebih tinggi dibandingkan lelaki. Itu dulu! Sekarang sebaliknya, populasi perempuan satu persen lebih tinggi dari lelaki.
Apakah karena itu yang menyebabkan perempuan menduakan pacarnya? Atau perempuan yang diam-diam dekat dengan tiga lelaki tanpa ketahuan? Meski pun status hanya teman dekat, saat ketahuan memberi harapan, apa yang akan dilakukan?
Sastra merasakan tubuhnya limbung, bukan mabuk karena kebanyakan minum jus buah naga kesukaannya tetapi karena sesuatu yang tak pernah ia harapkan ada di depan mata. Bahkan gelas yang sedari tadi di genggaman sampai jatuh berkeping-keping.
Tak ada lagi rasa nyaman yang ia rasakan melalui rangkulan tangan Arkana di pinggang mungilnya. Rooftop L'Avenue yang semula sejuk karena semilir angin malam perlahan terasa panas menyesakkan.
"Siapa kedua lelaki itu, Sas?" bisik Arkana di telinga Sastra. Pun pertanyaan senada terlontar dari bibir kedua lelaki di depan mereka, Ardia dan Aksara.
Sastra hanya bergeming tanpa kata. Seperti biasa berusaha tetap tegar, hanya mengerjap mencoba menghalau air mata yang sedikit lagi tumpah sehingga telaga bening bulat itu tampak berkaca-kaca.
"Kamu ngasih harapan juga sama mereka?" Kembali pertanyaan terlontar dari ketiga lelaki itu.
Arkana melepas rangkulan, menatap Sastra dengan pandangan terluka. Tampak lelaki itu mengepalkan tangan hingga buku jari memutih. Sastra masih terdiam, hanya bisa mengetatkan rangkulan di kedua lengan. Bahunya berguncang menahan suara tangis yang hendak pecah.
Sementara kedua sahabatnya—Kika dan Tiwi—yang semula berdiri dekat panggangan barbeku di sisi utara kolam mendekati Sastra dan merangkul punggung rapuh Sastra.
Kedua perempuan itu tak tahu harus melakukan apalagi. Merasa bersalah? Pasti! Karena mereka pun punya andil dan tahu segalanya.
"Dan kalian berdua tahu?" Tunjuk Arkana pada Kika dan Tiwi. Kedua perempuan itu mengangguk, pasrah.
"Shit!" Ardia mengumpat, lalu melempar bunga—yang dipegang sedari tadi—ke kolam renang. Lelaki berkacamata itu menghempaskan tubuhnya di kursi bulat berbahan rotan, menatap Sastra dengan tajam dan rahang mengetat.
"Gue kecewa, Sas," ujar Aksara, memijit pelipis lalu meletakkan kotak hadiah di meja. Lelaki itu memilih duduk di sofa tunggal, di seberang Ardia.
"Kenapa, Sas?" Arkana mendekati Sastra, alih-alih berhasil menangkup pipi perempuan itu, kedua tangan lelaki itu tiba-tiba dicekal.
"Jangan sentuh Sastra!" seru Ardia dan Aksara bersamaan.
"Kamu milih aku 'kan, Sas?" Arkana kembali mendekati Sastra, tetapi sekali lagi dihalangi oleh Ardia dan Aksara. Saling dorong seperti bocah yang memperebutkan mainan. Perdebatan, saling tarik, saling dorong mewarnai ketiga lelaki jangkung itu.
Kika dan Tiwi berjengit, terlonjak dengan kecepatan Ardia dan Aksara menghalau Arkana. Kedua perempuan itu nyaris terjengkang ke kolam. Tak mau bernasib seperti buket bunga yang dilempar Ardia, Kika dan Tiwi memilih berdiri menjauh dari Sastra.
Sayangnya, tingkah kekanakan ketiga lelaki itu justru membuat perasaan bersalah yang perlahan muncul dalam hati Sastra mendadak hilang. Ia yang semula tak tahu harus berbuat apalagi, lantas menyentakkan lengan ketiga lelaki itu.
"Gue enggak suka kalian seperti ini, apa lagi status kita saat ini masih proses untuk saling mengenal. Wajarlah kalau perempuan itu menginginkan yang terbaik sebagai pendampingnya. Kalau lo pada enggak terima, lo bertiga harusnya nonjok gue, bukan malah saling adu otot seperti tadi...."
Sastra berusaha menahan diri untuk tak meradang. Kerumunan di sekeliling juga semakin banyak dan tentu saja disertai bisikan-bisikan yang di telinga Sastra sudah seperti dengungan pasukan lebah yang benar-benar bising. Sastra sempat berdoa dalam hati, di antara kerumunan itu semoga tak ada yang mengenalinya.
Sastra lalu berjongkok, meremas rambutnya sendiri. Ia menunduk jengah oleh tatapan para pengunjung lain. Amarah bercampur malu sudah sampai di ubun-ubun. Belum lagi dengan tingkah ketiga lelaki itu sudah seperti berebut antrean BBM di SPBU.
"Oke! Sastra sama aku!"
"Gue anterin lo balik, Sas!"
"Saya duluan yang nganterin Sastra!"
"Diaaaaaammm!" Sastra berteriak dengan suara yang memekakkan telinga. Ketiga lelaki yang semula beradu mulut itu sontak terdiam. "Gue enggak milih siapa pun dari kalian. Lo bertiga puas?!"
Tanpa menghiraukan pandangan semua pengunjung L'Avenue pun arti dari semua bisik-bisik mereka, Sastra beranjak hendak berlalu. Ia pikir dengan memilih meninggalkan ketiganya, masalah selesai. Sayangnya Sastra salah, ia kembali berbalik dengan mata melebar dan mulut menganga saat mendengar ucapan Aksara dan diamini oleh Ardia dan Arkana.
"Gue enggak masalah! Meski lo punya orang lain...."
01
Udara sore ini hangat, matahari masih tampak gagah di ufuk barat. Jalan Panjang cukup lengang seperti biasanya. Dari kejauhan seorang perempuan melajukan Yamaha Jupiter Z dengan kecepatan sedang. Sesekali, ia melihat spion dan memerhatikan kendaraan yang lalu lalang di sekitarnya.
Ia Sastra Prameshwari, perempuan dua puluh lima tahun dengan wajah mungil yang selalu tampak ceria, bola mata bulat itu pun berbinar indah. Berpadu serasi dengan hidung dan bibir mungilnya membentuk senyuman tipis. Meski warm blonde dari surai sepunggung itu efek toning tetapi sangat serasi dengan kulit putih Sastra.
Perempuan itu selalu memilih Jalan Panjang sebagai alternatif untuk pulang ke Jagakarsa. Selain karena kendaraan yang melintas bisa dihitung jari hanya di perempatan Jalan Musyawarah dan beberapa titik saja yang cukup padat, Sastra tak perlu khawatir kena tilang karena melanggar rambu larangan berkendara roda dua. Sesekali kaki jenjangnya dibiarkan menjuntai menapak aspal demi menjaga keseimbangan saat jalanan di depan tiba-tiba saja macet.
Maklum, Sastra tak pernah tertarik dengar roda empat yang hanya akan membuatnya terjebak kemacetan Jakarta. Jalan tol saja padat merayap, bagaimana ia bisa tiba di rumah lebih cepat? Dengan roda dua, Sastra membutuhkan waktu tempuh sampai lima puluh menit. Bayangkan jika harus menggunakan roda empat, sebelum sampai tujuan yang ada malah kulit Sastra akan mengkerut karena terlalu lama terpapar AC.
Sastra mengembuskan napas lega saat kendaraan yang diberi nama 'Jupi' itu mencapai pintu pagar rumah. Pagar papan khas Betawi, tersusun dan terpaku rapi.
Setelah memarkirkan si Jupi, Sastra bergegas masuk ke rumah. Ia sudah tak sabar untuk bertemu dengan Ayah, Ibu dan abangnya. Sastra itu bucin keluarganya. Tak bertemu seharian saja sudah membuat ia rindu. Bagaimana nanti kalau ia sudah bersuami? Sastra mungkin akan meminta suami yang ikut dengannya.
"Assalamu'—" Sapaan salam dari Sastra terpotong oleh suara pecahan barang pecah belah dari arah ruang tengah. Entah apa yang terjadi. Dengan berjingkat, Sastra melangkah pelan melewati ruang tamu yang berantakan.
Sofa 321 warna hijau yang sudah tidak pada tempatnya, ada asbak yang menelungkup di lantai dan puntung rokok yang berhamburan. Langkah Sastra terhenti pada tirai kain panjang pembatas ruang tamu dan ruang tengah, tepat di samping lemari kayu ukir asli Jepara yang isinya pun tak kalah berantakan.
"Siapa dia, Yah?" Suara Laely terdengar lirih, sampai Sastra harus benar-benar menajamkan telinga agar bisa mendengar ucapan ibunya.
"Siapa apanya?" Kali ini suara gusar milik Sjamsul membahana, sang Ayah terdengar balik bertanya pada Laely.
"Dia yang telah merubahmu seperti ini. Katakan siapa dia?!" Suara Laely semakin meninggi, Sastra berjengit
"Kamu jangan asal tuduh, Bu! Bukannya kamu yang terlalu sibuk dengan teman-teman arisanmu yang enggak jelas itu?"
"Yah, saat seorang suami tak lagi memberi nafkah lahir batin ke istri, apalagi masalahnya kalau bukan karena ada orang ketiga, hah?" Laely pun menangis sesegukan.
Sastra yang berada di balik tirai, mendengar semuanya dengan penuh tanya. Tak biasanya Sjamsul dan Laely berdebat dengan nada tinggi. Kaki Sastra sebenarnya sudah gatal ingin menghampiri jika saja ia tidak mendadak ingat pada Warta, abangnya. Sastra merasa ada yang tidak beres, ia bermaksud menengahi tetapi tak mau dianggap mengganggu privacy.
Di mana Bang Warta? Kenapa enggak berusaha menengahi, sih? Gue harus gimana ini? Sastra membatin sembari meremas ujung kemejanya. Ia kembali mencoba menajamkan pendengaran.
"Kamu harusnya prihatin dengan kondisi stasiun televisi tempatku bekerja. Bukan hanya menuduh semaumu!"
Sastra mematung, kembali terdengar percakapan Sjamsul dan Laely. Dalam hati, ia mulai menebak-nebak penyebab keduanya sampai bertengkar.
"Ini mungkin karma, Yah, karena lebih memilihmu dibandingkan orang tuaku. Ini balasan untuk aku yang enggak berbak—" Suara tamparan terdengar menginterupsi ocehan Laely disusul suara piring pecah ke lantai. Suara langkah tergesa yang dihasilkan oleh sepatu Sjamsul membuat Sastra menahan napas.
Sjamsul menyibakkan tirai dengan kasar, menoleh ke kiri sekilas karena menyadari kehadiran Sastra yang berdiri mematung, bergeming, menyapa dengan suara sedikit tercekat.
"Ayah...."
Sastra memaksakan untuk tersenyum, seakan tak mendengar pertengkaran beberapa saat lalu. Namun hanya dibalas dengan dengkusan oleh Sjamsul. Rahang lelaki 49 tahun itu mengeras. Tak ada sapaan untuk Sastra. Ia lalu melangkah lebar, berderap meninggalkan ruang tamu dan menutup pintu dengan keras hingga menimbulkan bunyi berdebam.
Sjamsul pergi, Sastra dapat mendengar deru mobil dari arah garasi yang bergerak semakin menjauh.
Sastra mengintip dari balik tirai, memandangi Laely yang duduk membelakangi. Bahunya tampak bergetar naik turun pertanda isakan yang tertahan. Ruang tengah yang terhubung dengan dapur dan ruang makan pun berantakan. Remote TV yang tergeletak mengenaskan, bantal duduk yang teronggok di depan TV berpindah ke samping meja makan pun karpet oval yang tersibak tak lagi menggelar sempurna.
Sastra mengendap-endap menuju tangga yang berada di sebelah kanan ruangan. Sastra berharap jika Laely tak mengetahui keberadaannya. Ia tak ingin dicap mencuri dengar pertengkaran perempuan itu. Sastra pikir, itu adalah ranah privacy sang Ibu. Ada hal penting dan harus ia lakukan sebelum menyapa Laely.
Sastra harus menemui Warta, bisa-bisanya sang Abang hanya diam mendekam di kamar sementara keadaan di lantai bawah nyaris menyamai situasi perang dunia kedua.
Derit pintu pertanda butuh pelumas mengagetkan Sastra, mungkin saja suaranya sampai ke telinga ibunya yang tepat berada di lantai bawah. Sastra mengumpat dalam hati lalu membuka pintu dengan pelan, teramat khawatir kalau bunyi yang membuat gigi terasa ngilu itu muncul kembali. Sastra bergidik, meremang karena mendapati ruangan kamar yang gelap gulita.
"Bang...," panggil Sastra sepelan mungkin. Tak ada sahutan. Sastra beringsut ke kanan mencari sakelar lampu. Bola mata bulatnya semakin melebar, terkesiap mendapati kamar mini malis ukuran 4x3 milik Warta kosong tak berpenghuni.
Perasaan was-was mendatangi. Ada apa lagi ini? Sejak kapan Bang Warta seapik ini?
Sastra membuka lemari dua pintu Olimpic yang jaraknya selangkah dari tempatnya berdiri. Ada beberapa lembar pakaian yang menghilang. Berapa banyak 'sih, pakaian Warta? Sastra yang selalu mencucinya setiap akhir pekan, ia tahu setiap detail dan jumlahnya.
Sastra menarik ponsel dari tas yang ia sampirkan di bahu. Mencoba menghubungi Warta tapi yang menjawab malah Mbak Vero. Berkali-kali diulang pun, hasilnya tetap sama.
Beruntunglah Mbak Vero hanya bisa menjawab 'nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif, silakan coba beberapa saat lagi' tanpa bisa balas mencaci dan memaki jika ia sudah bosan mendengar suara Sastra.
Dengan langkah gontai, Sastra masuk ke kamar yang berada tepat di samping kamar Warta.
Jika Warta lebih senang dengan tema vintage yang mendominasi, Sastra lebih suka shabby chic. Terasa menenangkan dan nampak manis. Yang membedakan kamar keduanya hanyalah warna, selebihnya sama.
Saat meletakkan tas di atas meja nakas samping ranjang, Sastra kembali memekik. 'Si Piggy' celengan babinya ikut raib bersama dengan Warta, hilang digondol sang Abang.
Hoi, Motor ASTRA ....
Si Piggy Lo buat gue, ya.
Gedung ARTA lagi butuh duit buat renovasi, segera!
Sastra meremas kertas yang ditinggalkan Warta tepat di tempat Sastra menyimpan si Piggy, lalu melemparnya ke sembarang arah.
Bang Warta tahu banget kalau si Piggy udah hampir brojol! Mengambil alih tanpa permisi seolah milik sendiri!
Rasanya Sastra ingin meraung saja kalau saat ini ia sendiri di rumah. Tetapi saat ini ada Laely, ia bahkan belum menemui ibunya sejak tiba di rumah. Ia lalu bergegas turun ke lantai bawah tapi tak lagi menemukan perempuan itu di stool depan kitchenisland. Samar, Sastra mendengar suara tawa berderai milik Laely dari arah ruang tamu. Sepertinya sedang menerima telepon.
"Gampanglah, Jeng. Hajar Jahanam Mesir-nya akan restock lagi besok. Hihihi...."
"…."
"Huum, Jeng ... besok aku anterin ke rumah, ya."
Kaki Sastra yang hampir sampai di undak tangga terakhir perlahan berhenti. Ia termangu, mendengar suara tawa
Laely yang sangat riang padahal beberapa saat yang lalu, perempuan itu masih menangis sesenggukan.
Apakah orang dewasa selalu seperti itu?
Hurt easily, easily recovery ....
Sastra batal menemui Laely, lebih memilih kembali ke kamar, mengunci pintu lalu berbaring meringkuk di ranjang, tangan dan kedua kakinya tertekuk memeluk guling hingga lututnya nyaris mencapai dagu. Suara cacing dalam perut meminta diisi tak lagi Sastra hiraukan. Ia hanya butuh tidur saat ini.