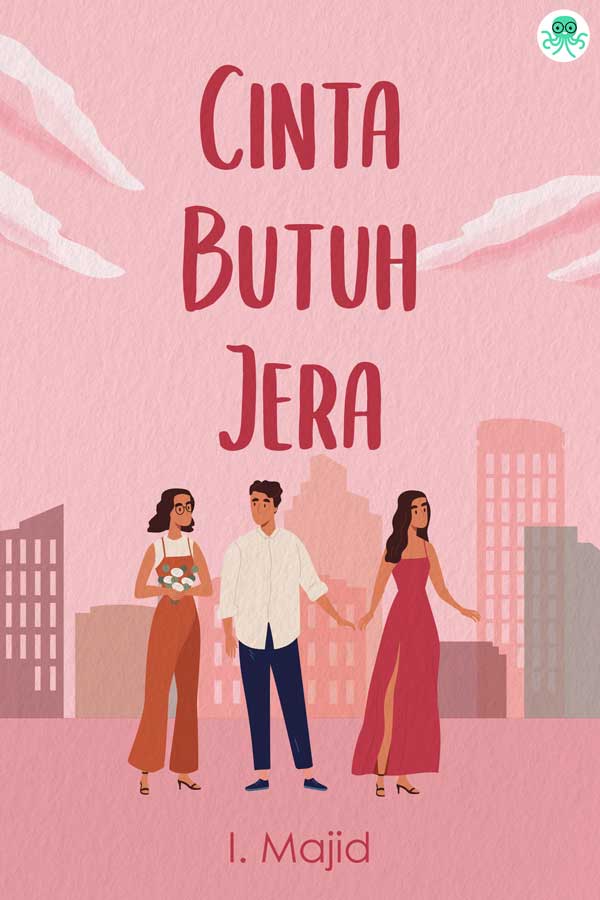
Cinta Butuh Jera
By I.Majid
Sore itu, Galih merasa bahwa pekerjaannya di kantor terlalu banyak menyita waktu. Seharusnya ia bisa pulang sebelum jam empat sore kalau saja rekan kerja samanya yang merupakan kontraktor swasta itu tidak minta meeting dadakan. Padahal pembahasan soal proyek pembangunan dermaga masih bisa dilanjutkan esok hari.
Tangan Galih sibuk memasukkan barang-barang pribadi ke dalam ransel ketika ia menjepit ponselnya di antara bahu dan telinga sembari menjawab telepon dari Anis. “Iya, Sayang … kamu tunggu dua puluh menit, ya? Ini aku lagi OTW jemput kamu, kok.”
Terkadang, orang yang sedang kasmaran memang tampak tidak waras. Galih tersenyum sendiri pasca menutup telepon dari sang calon istri. Ya, Galih memang secinta itu pada Anissa hingga raut wajah euforianya menjadi bahan olok-olok teman satu ruangannya di kantor. Itu sudah menjadi hal biasa bagi Galih. Semua orang yang ada di ruangan itu tahu kalau Galih adalah tipe pria lupa diri kalau sudah berurusan dengan yang namanya cinta dan Anis.
Pria dengan rambut potongan undercut itu melengos dengan senyum sekadar ketika teman-temannya mencibir menggunakan kata-kata candaan. Tentu saja ia tidak sempat menanggapi omongan mereka. Galih menggantung tas ranselnya di bahu kanan seperti prajurit yang membawa senjata saat langkahnya terburu keluar dari kantor menuju parkiran mobil. Begitu ia duduk di atas jok kemudi, Galih menyalakan mesin lantas melajukan mobil Mercy tiger merahnya lantas dengan cermat membelah jalanan Jakarta yang dirundung kemacetan.
***
Anis melangkahkan kaki keluar dari toko bakery tempat ia bekerja. Ada kelegaan napas tatkala sinar matahari sore menyambutnya hangat. Ia menyempatkan diri menengok ke belakang. Lantas tersenyum sendiri, menyadari bahwa beberapa minggu lagi ia akan meninggalkan tempat ini.
Kini, gadis berambut lurus panjang sepungggung itu memusatkan perhatian pada trotoar, tempat di mana biasa ia menunggu angkutan umum. Dan tentu saja, tempat di mana biasa ia menunggu lelaki pujaannya datang menjemput.
Dari jarak tiga puluh meter, Anis sudah bisa melihat mobil berwarna merah benderang milik Galih tengah berupaya melewati kemacetan yang tak terlalu parah. Ia tersenyum saat Galih berhasil menghentikan mobil tepat di hadapannya.
Tanpa perlu berpikir keras, Anis langsung masuk, memerosotkan diri di jok kesukaannya sementara tangan kiri Galih memasukkan persneling sembari menyapanya hangat bak mentari sore.
Mobil Galih adalah Mercy tiger klasik produksi tahun 1980. Waktu Galih masih duduk di semester dua perkuliahannya, ayahnya memberikan mobil itu sebagai hadiah ulang tahunnya yang ke sembilan belas. Ia menabungkan uangnya sedikit demi sedikit untuk membuat mobil tua itu tampak lebih bersih, keren, dan sempurna. Ia mengganti semua joknya dengan warna hitam mengkilap berbahan kulit, memasang layar sentuh di dasbornya, ia juga memasang speaker di setiap pintu bagian dalam. Sehingga setiap ia menyalakan musik, telinga akan dicekoki suara menggema dari bass speaker yang bergetar-getar.
Anis memasukkan tangannya ke dalam tas, lalu dengan cepat mengeluarkan contoh-contoh undangan, menyusunnya seperti jajaran kartu. "Coba lihat! Aku punya beberapa contoh undangan dari Hikmal, kamu lebih suka yang mana?" Ia mendekatkan undangan itu hampir ke wajah Galih.
"Kalau kamu suka yang mana?" tanya Galih kembali.
"Mmmm ... kayaknya ungu cantik. Lihat lamit mengkilapnya, aku juga suka font-nya."
Galih memusatkan perhatian beberapa detik, masih tetap fokus pada jalanan di sekitarnya. "Ungu bagus."
Di saat itu juga Anis tersenyum, merasa menang bahwa tebakan Hikmal kali ini sangatlah meleset. Detik ini juga ia bisa merangkai kata-kata yang pantas untuk menyela temannya itu sepuas hati esok harinya.
"Eh sepertinya hitam lebih keren, hitam aja deh."
Anis langsung memasang ekspresi lunglai mendengar pernyataan yang baru saja dikeluarkan dari bibir manis lelaki itu.
"Hitam?" serunya, "Kamu yakin? Apa kerennya, sih, hitam? Bukannya tadi kamu pilih warna ungu?" Sedikit paksaan barangkali perlu.
"Sayang, hitam itu netral, kamu perhatikan baik-baik, desainnya kelihatan beda dari undangan lain. Lagi pula jarang kan orang pakai undangan warna hitam?"
Ya, bagian yang terakhir barang kali benar, bukan berarti Anis juga tak suka dengan pilihan Galih, hanya saja ia memang lebih suka yang ungu. Apakah ia perlu menghipnotis agar calon suaminya itu menurut?
"Galih, hitam memang―"
"Keren! Ya, kan?" Galih dengan sengaja menyambungnya. "Aku tahu kamu juga suka hitam. Bilang sama Hikmal, kita minta dibuatkan yang warna hitam. Oke?”
"Tapi—"
"Udah ... ngapain dipersulit, sih? Aku yakin hitam adalah pilihan yang tepat." Galih tersenyum. Matanya menyipit hampir tak kelihatan.
Anis tak boleh egois. Lelaki di sampingnya itu telah ada bersamanya selama enam tahun. Sejak mereka bertemu di rumahnya saat Levin―teman semasa SMA-nya yang masih punya hubungan saudara dengan Galih—membawa Galih ke rumahnya untuk diperkenalkan.
Wajah tampan serta perangai yang dimiliki pria itu telah membuatnya jatuh cinta mulai dari pandangan pertama. Meskipun awalnya ia cukup ragu dengan perasaan itu, merasa tak pantas bila gadis biasa seperti dia, yang hanya berakhir di pendidikan SMA dan tidak sarjana, yang tak memiliki rupa secantik wanita kelas atas, harus mengharapkan perasaan yang sama dari seorang pria berpendidikan tinggi.
Hanya saja Anis tak tahu harus mengucapkan rasa terima kasihnya dengan cara seperti apa karena Galih telah bersedia setulus hati mencintainya, memberikan segala hal yang terbaik selama ini juga menjaganya dengan sepenuh hati bahkan tak pernah menuntut apa pun darinya kecuali setia.
Dan yang terpenting, Anis pun semakin mencintainya, tepatnya saat dua bulan yang lalu ketika Galih melamarnya, memintanya untuk menjadi seorang istri yang bersedia mendampingi setiap langkah kehidupannya ke depan. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke dua puluh empat tahun, Galih membawanya ke sebuah padang rumput luas (ia tak tahu apa nama tempat itu), memohon dengan penuh cinta dan ketulusan: bahwa ia dengan sungguh-sungguh menawarkan diri untuk menjadikan Anis sebagai istrinya.
***
Ada suara erangan motor yang sangat deras menyenggol telinga mereka ketika mobil Galih sudah tiba di depan rumah Anis. Galih tahu persis siapa orang yang suka memainkan gas motor seperti pembalap liar begitu. Ia pun keluar dari dalam mobil dan mendapati Levin dengan motor besarnya―membonceng seorang gadis bercelana pendek―berhenti di depan mobil Mercy Galih.
Gadis itu membuka kacamata hitamnya hingga terlihat warna kebiruan lensa kontak di matanya.
"Hei! Baru pulang?" sapa gadis itu pada Anis. Kedua lengannya merangkul erat pinggang Levin.
"Iya nih baru pulang, pada mau ke mana?" balas Anis. Galih dengan cepat berdiri di samping kekasihnya, seolah menunjukkan pada kedua orang itu bahwa dialah orang yang mengantar Anis sampai rumah.
"Biasa, cuma mau nongkrong sama teman-teman Levin di track." Senyuman Sita sesungguhnya sangatlah ramah, tapi sayangnya harus tercemar dengan asap serta suara berisik motor Levin. Seolah ia sengaja melakukan itu.
Levin tidak mengenakan helm. Dan dari sana Galih bisa melihat bagaimana air muka sepupunya itu tak menunjukkan keramahan saat melihat kedekatan jarak tubuhnya dengan Anis saat ini.
Apakah benar firasatnya? Bahwasannya Levin masih memendam rasa cemburunya pada Anis yang dulunya hampir ia jadikan kekasih. Atau rasa penyesalannya karena pernah mengenalkan Anis pada Galih enam tahun yang lalu. Dan mengetahui, bahwa ternyata Anis tak punya perasaan apa-apa padanya selain pertemanan. Malahan lebih menyukai Galih ketimbang dirinya.
Bila benar seperti itu, seharusnya Levin tak pantas lagi bersikap apatis. Karena saat ini, kesendiriannya telah terbayarkan dengan kehadiran seorang gadis dalam hidupnya. Seorang kekasih yang kelihatannya lebih dari sekadar istimewa dibandingkan gadis mana pun yang pernah Levin kenal.
Masita Raina, gadis cantik pemilik tubuh tinggi semampai itulah yang selama delapan bulan belakangan ini menjadi kekasih Levin.
"Nis!" panggil Sita. "Nanti malam aku tidur rumah kamu, oke?"
Gadis di samping Galih langsung setuju, bahkan kelihatannya sangat senang mendengar kalimat pemberitahuan Sita. "Oya? Oke, aku tunggu."
"Yup! Kalau gitu, kita cabut dulu. Bye ...."
"Bye …."
Lagi-lagi motor Levin mengerang deras kemudian melaju cepat tanpa meninggalkan senyuman ataupun sapaan pada mereka.
Anis melihat ke mata Galih, seolah bertanya apa yang sedang terjadi pada sepupumu? Galih mengangkat bahunya sembari menggelengkan kepala seolah menjawab entahlah!
***
Sita datang sesuai janji. Namun kali ini, Sita sedang ingin mengajak sahabatnya itu keluar malam sekadar makan di kafe pinggiran kota Jakarta. Setelah selesai makan, mereka pun berbaur dengan ramainya pejalan kaki, lampu-lampu kota yang terlihat gemerlap, begitu juga dengan kendaraan-kendaraan yang terlihat benderang dengan cahaya lampu mereka. Udara malam tak tampak secara kasatmata, entah itu polusi atau sekadar karbondioksida. Namun, ia suka angin malam yang menerpa dan membelai lembut kulit mereka. Agaknya rumah Anis tak begitu jauh dari tempat semula.
Sita sadar, tidak lama lagi mungkin ia akan kehilangan Anis. Gadis yang sudah ia jadikan sahabat sejak kecil. Bukan hanya karena rumah mereka bertetangga, atau sekolah mereka sama sampai SMP, tapi karena mereka telah terikat. Tak ada orang lain yang bisa mengerti dirinya kecuali Anis. Meskipun ia lahir dari keluarga yang lebih kaya daripada Anis, meskipun pergaulannya lebih liar dan bebas, pendidikannya lebih tinggi, tetapi hanya sahabatnya itulah yang tak pernah mengeluhkan sifat buruknya. Dari sekian banyak teman yang ia miliki, Sita akan tetap suka dengan pribadi Anis yang sangat sederhana.
Anis tahu tentang Sita yang sudah kehilangan keperawanannya akibat pergaulan bebas. Bahkan ia melakukan seks hampir dengan semua pria yang pernah menjadi pacarnya. Bagi Sita itu adalah suatu kepuasan yang tak tiada banding. Maka ketidakwajaran yang mungkin dirasakannya itu hanyalah sebatas kepuasan sesaat. Sebiadab apa pun dirinya, ia tentu tak ingin kalau sampai sahabatnya itu sampai terjerumus sama seperti dirinya.
Daratan agaknya sedikit basah lantaran hujan yang baru mereda. Kedua tangannya ia masukkan ke dalam saku jaket, berjalan dengan langkah tak lurus karena harus bersusah payah menghindari genangan air. Sekaligus memperhatikan wajah semu memerah Anis yang kelihatannya senang setelah mendengar pujiannya.
"Aku serius. Galih adalah laki-laki paling beruntung karena bisa memiliki kamu."
"Sita, aku pikir kamu bakal bilang kalau aku dan Galih adalah pasangan yang sama-sama beruntung."
Sita tertawa, menghentikan langkah di perempatan jalan tak jauh dari rumah Anis. "Ya, Galih pria yang baik, aku nggak pernah melihat seorang pria yang begitu peduli dengan pacarnya sampai segitunya. Dia punya kharisma yang nggak dimiliki oleh pria lain yang pernah kukenal. Aku percaya kalau dia pasti bakal menjadi ayah yang luar biasa nantinya."
"Aamiin," ucapnya, berharap agar itu bisa menjadi kenyataan. "Kamu tahu? Semakin dekat harinya, semakin membuatku takut."
"Takut kenapa?" tanya Sita sambil membenarkan posisi kacamata tebalnya yang nyaris kabur karena berembun. Seharusnya ia memakai lensa kontak saja tadi.
Anis berdeham, menyelipkan rambutnya ke belakang telinga lalu melanjutkan perjalanan pulang. "Entahlah, aku takut jika kami sudah menikah nanti, aku nggak bisa menjadi istri yang baik untuk Galih. Kamu kan tahu, aku tipe perempuan yang gampang cemburuan."
Suara tawa Sita melerai udara dingin sesaat. Tangannya menyentuh pundak Anis. "Ya ampun, Anis, nggak ada istri yang sempurna di dunia ini. Kalian saling mencintai, bukan? Aku rasa itu bisa jadi jaminan utama untuk bisa membuat rumah tangga kalian bahagia nantinya."
Bukan maksud Sita membuat ekspresi Anis menjadi kikuk, ia hanya ingin memberi sedikit pencerahan pada gadis yang terbilang masih sedikit lugu.
"Artinya ketakutanku nggak beralasan?" Sita menganggukkan kepala membenarkan. "Aku benar-benar bodoh, seharusnya aku berpikir seperti itu sebelumnya."
"Ya, dasar polos."
Mereka telah tiba di depan rumah Anis. Masih enggan untuk berpisah dengan suasana gelap malam, mereka pun menyempatkan waktu lagi untuk duduk di undakan tangga serambi depan. "Kalau aku jadi kamu, yang kupikirkan menjelang hari pernikahanku adalah bagaimana reaksi para mantan pacarku yang terkejut ketika melihat kartu undangan sampai ke tangan mereka."
Tawa Anis menggelak sampai tangannya refleks memukul paha Sita. "Satu per satu dari mereka mungkin akan memberimu kado berupa surat kaleng berisi sumpah serapah."
Tentu saja Sita masih ingat berbagai macam alasan yang ia gunakan ketika memutuskan hubungan dengan pria-pria pecundang yang pernah ia pacari. Bahkan Sita hampir tak percaya ia pernah mengaku mengidap penyakit HIV agar bisa putus dari Jacob—cowok tak berambut yang tingkah lakunya lebih manja daripada anak tetangganya yang berumur lima tahun.
Sita melihat tawa Anis yang melebar lambat laun menenang. "Ceritakan tentang Levin. Apa dia salah satu cowok yang bakal bernasib sama seperti pacar-pacarmu yang sebelumnya?" tanya Anis.
"Levin?" Sita tersenyum kecil lalu menggeleng. "Enggak, aku nggak akan memperlakukan Levin seperti itu."
"Oya? Serius?" tanyanya tak percaya. Hawa napasnya terlihat mengepul di udara.
Kali ini Sita mengangguk tegas. "Anis, aku capek harus seperti ini terus. Aku ingin berhenti mempermainkan laki-laki. Selama ini aku menganggap semua laki-laki adalah manusia tak bermoral, yang hanya bisa memanfaatkan perempuan sebagai pemuas keinginannya. Mereka bahkan nggak akan pernah peduli bagaimana perasaanmu yang sebenarnya." Sita membuang napas, sedangkan Anis hampir tak ingin mengalihkan perhatian dari kalimat-kalimat Sita. "Tapi Levin berbeda. Dari semula aku mengenalnya, aku melihat sesuatu dari dirinya yang membuatku nggak bisa lupa dengan segala tentangnya. Meskipun kebanyakan temannya berasal dari kalangan anak-anak nakal, tapi Levin nggak seperti itu.
"Dia selalu mengerti bagaimana perasaanku, Levin bahkan nggak pernah berani menyentuh tubuhku tanpa meminta izin padaku. Apalagi menggerayangiku. Ia selalu melindungiku seperti seorang putri raja, membuatku tampak lebih berharga di matanya. Meskipun ia tahu semua tentang kehidupanku di masa lalu."
Sita mengenal banyak cewek-cewek yang menyimpan catatan seks mereka di dalam note book, atau yang merekamnya dengan kamera amatir lalu disimpan di dalam flash disk. Sebagian dari mereka adalah cewek-cewek yang menderita kelainan karena terlalu sering melakukan seks. Itu sebabnya Sita tak ingin hal seperti itu menimpanya.
"Levin adalah yang terakhir. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk bisa bahagia hanya dengan laki-laki pilihan terakhirku."
"Kamu mencintainya?" tanya Anis.
Sita menggenggam jemarinya. "Sangat ... aku sangat mencintainya."
Anis menunduk sesaat. Raut wajahnya sedikit berubah tak sesemangat tadinya. Sedangkan Sita tersenyum-senyum sendiri, sedikit lagi tenggelam dengan gambaran wajah Levin yang seolah tersenyum memandangnya.
"Kalau begitu jagalah hubungan kalian baik-baik." Sita menoleh ke arah Anis. "Kalau memang kamu sudah yakin dengan pilihanmu kali ini, aku hanya berharap Levin adalah yang terbaik buat kamu, Ta."
"Tentu! Aku nggak akan membiarkan Levin jatuh ke tangan cewek lain, karena dia adalah laki-laki yang harus menjadi suamiku kelak."
Anis mengangkat bahu. "Jodoh siapa yang tahu?" Lalu mereka tertawa hampir berbarengan.