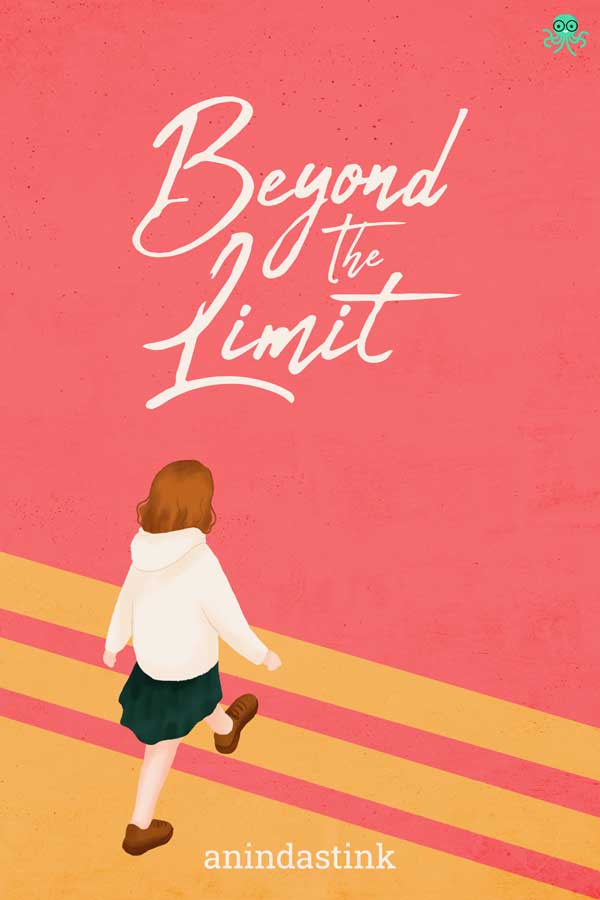
Beyond The Limit
By anindastink
MARSI
Do you know, what is in my mind when holiday is getting near? Everybody must have their own way enjoying their holiday. Dan daripada memilih liburan ke Singapore seperti temanku Maya, atau pergi ke pusat perbelanjaan untuk mengecek diskon makeup keluaran terbaru. Aku memutuskan duduk manis di atas sofa apartemen Syahdan seraya menyaksikan tayangan televisi, of course after we spent the night full of fatigue.
Eits, jangan berpikir liar. This is not sex, melainkan pulang kerja, lantas memutuskan menonton film action terbaru, selepas itu makan di Japanese restaurant, dan berakhir tidur di apartemen ini dengan kamar yang terpisah. Bukankah itu termasuk kegiatan yang melelahkan besides working on the bed? And most importantly, this apartment is very comfortable and I can get delicious food, of course from Chef Syahdan terhormat, yang sekarang terlihat berjalan dari dapur dengan membawa sepiring salad buah.
“Apa bagusnya menonton acara begituan?” Suaranya terdengar kesal.
Syahdan meletakkan saladnya di atas meja, lantas mengempaskan tubuhnya di sampingku yang masih betah menguasai televisi yang menayangkan program berjudul the project, sebuah program renovasi.
“This is about life style, Syah.”
“Gaya hidup apaan? Nggak jelas,” sambungnya.
Syahdan menusuk potongan melon berlumur yogurt dengan garpu lalu mengunyahnya.
Aku tidak ikut menusuk, namun saat tangan Syahdan kembali mengambil buah, aku menarik tangannya ke arahku lalu memakan buah dari garpu yang ia pakai. Melihat apa yang aku lakukan, Syahdan hanya berdecak, tidak berkomentar apa pun.
“Nah, begini kalau bicara dengan orang yang nggak searah. Lagipula gue nonton acara ini buat cari inspirasi rumah,” kataku akhirnya.
“Oh gitu, wow sekali, Nona,” komentar Syahdan dengan nada yang dibuat terkejut.
Aku menatapnya sebal. “Oh. Makasih, lho,” cibirku.
Mendengar cibiranku, kontan saja Syahdan tertawa. Bodoh amat. Aku tidak menggubrisnya. Memilih untuk menyamankan posisi duduk dengan mengangkat kedua kaki ke atas sofa lalu kutekuk bersila dan menyandarkan kepalaku pada bahu Syahdan.
Dari jarak sedekat ini aroma tubuh Syahdan seenaknya menembus penciumanku. What’s it called? Masculine? Or gentle? I don't know, yang aku tahu, aku menyukainya lantaran baunya tidak norak. Tidak tahu dari mana dia mendapatkan aroma seenak ini. Barangkali karena durasi mandinya yang lama atau boleh jadi ia memang bisa menjaga tubuhnya supaya tetap wangi.
“Memangnya lo ada rencana bikin rumah, Mar?”
Pertanyaan Syahdan mengalihkan lamunanku.
“Belum tahu. Eh, tapi itu kan acara renovasi ruangan kali, bukan renovasi rumah.”
“Sama nggak, sih, Mar?”
Aku sedikit berpikir. “Ya sama sih, tapi nggak sama-sama banget. Nggak ngerti juga, bukan anak desain interior.”
Syahdah hanya mengangguk sambil menikmati salad, maybe he understand.
“Kalau mbangun sama gue, mau?”
Aku melirik Syahdan. “Bangun rumah? Idih niat banget bangun sama lo. Gue mau pakai jasa pembangunan. Itu pun kalau gue ada rencana mau bangun rumah, sih.”
“Kalau rumah tangga, bukan bangunan rumah, mau?”
Aku sontak mengangkat kepala dari bahu Syahdah. Menoleh padanya yang tengah menatapku. Sempat tercengang, namun detik berikutnya kuteriaki dia.
“Iyuh! Tambah ogah! Lo, kan berniat punya bini empat. Say goodbye aja, ya,” cibirku.
Tidak habis pikir dengan pria yang duduk di sampingku ini. Ada-ada saja pria ini. Akan tetapi aku sedikit merasa janggal begitu mendapatkan tatapan Syahdan yang amat serius menatapku. Kok merinding, ya?
“Bukan empat, Girl,” katanya.
Alisku menukik. “Terus?”
“Dua,” sambungnya lalu nyengir.
Tai! Gue kena tipu.
“Bangsat! Apalagi itu. Nggak!” Aku menggeleng sebagai bentuk penegasan atas penolakanku.
“Jadi gue ditolak, nih?” godanya sambil menyenggol bahuku.
“Iya, tapi kalau gue jadi satu-satunya, bolehlah dipertimbangkan,” ujarku lalu memasukkan potongan melon ke dalam mulut. Kunyah... kunyah... telan.
Aku melirik Syahdan, seringai dari bibirnya bukannya membuatku bergidik justru membuatku geregetan ingin menabok bibirnya.
“Kalau lo satu-satunya?” Tidak habis akal ternyata dia. Satu alisnya menukik.
Sebentar, keranjingan apa pria ini sampai bicaranya terdengar begitu serius begini? Tapi okay, aku ikuti permainannya.
“Tapi maskawinnya harus berlian, ya.”
Aku menatap Syahdan dengan pandangan penuh kemenangan, tahu kali ini aku berada satu poin di atasnya. Syahdan mencondongkan badannya ke arahku sehingga kepala kami bisa berhadapan lebih dekat. “Jangankan berlian, batu asteroidpun gue ambil buat lo. Gimana?” sahutnya terdengar mantap.
Aku menyeringai. Gombalanannya benar-benar tidak masuk akal. “Lho, berarti lo milih mati dong daripada gue?” tukasku.
Dari jarak sedekat ini aku bisa melihat perubahan raut wajah Syahdan yang melesu. “Ya kan perumpamaan, Mar,” protesnya lalu menjauhkan tubuhnya dariku dan bersandar pada sofa.
“Tolong ya, itu bukan perumpamaan kali. Itu gombalan. Belum apa-apa masa udah gombal. Artinya lo nggak serius.”
“Gue serius, ya,” kilahnya. Matanya yang tajam menatapku seolah merasa tidak terima.
Aku ikut menyandarkan tubuhku dan menoleh padanya. “Gue juga serius. Asal berlian, besokpun gue jabanin.”
“Ya sudah, tunggu.”
“Gue nunggunya sampai besok jam tujuh, kalau nggak ada berlian. Bye bye deh.”
Syahdan mengacak rambutnya. “Ya kan usaha dulu, Mar,” katanya terdengar frustrasi.
Aku terkejut dengan respons Syahdan barusan, terlebih dengan tatapannya yang tidak bisa aku artikan. Tatapan macam apa coba itu?
“Syah, apaan sih. Frustrasi banget lo ini. Dah ah,” tukasku.
Jika tidak segera disudahi, obrolan ini tidak akan ada ujungnya.
“Dah ah apa?”
“Ya udah, terserah lo,” kataku lalu berdiri, perut keronconganku tiba-tiba menyuruhku untuk mengecek dapur. Mengabaikan Syahdan yang terlihat hendak menanggapi perkataanku.
Honestly, this is not the first time we talked about marriage. Walaupun aku merasa obrolan kali ini terasa lebih serius. Too bad we’re not a couple, so tawaran pernikahan darinya bukan hal penting bagiku. Lebih dari itu, aku belum tertarik dengan pernikahan. Masih banyak yang harus aku lakukan sebelum menikah. Terlebih hidupku sudah terasa sempurna, aku punya mama yang pengertian, saudara yang perduli, dan teman dekat yang menemani tawaku. Itu lebih dari cukup.
“Mau ngapain, Mar?” teriak Syahdan dari ruang televisi. Telat banget dia tanyanya.
“Ambil nasi, laper!”
***
Perkenalan pertamaku dengan Syahdan mungkin sembilan tahun yang lalu. Saat kami berada di kelompok KKN yang sama. Sedangkan pertama kali mengetahui Syahdan bernapas di bumi ini saat semester satu kuliah. Aku masih ingat tubuh kurusnya yang mengenakan jaket jin dan celana balel, serta sepatu converse melangkah melewati lorong yang menghubungkan setiap kelas. Dan jangan lupakan rambut gondrong yang berhasil menodai mataku.
One thing that occurred to me, “Iyuh, dia serius gondrong macam Mbah Surip begitu?”
Tentu dengan rasa geli berlipat-lipat. Pilihan selanjutnya aku lupa kalau dia hidup di bumi ini.
Seperti kataku, kami baru saling mengenal di masa KKN. Tentu dengan penampilannya yang sudah rapi. Di perkenalan kami, aku sama sekali tidak tahu kalau Syahdan adalah mahasiswa gondrong yang membuatku geli setengah mati. Aku baru tahu setelah dia menunjukkan satu video masa awal kuliahnya yang di warnai dengan rambut panjang mencapai pantatnya.
Kubilang padanya. “Sumpah? Ini serius elo? Gila, dulu gue jijik banget sama nih orang. Nggak tahunya itu elo! Beda banget, sih!”
Dan itulah Syahdan. Ia tidak marah. Mendengar perkataanku, ia justru ikut tertawa sambil bertanya. “Sekarang ganteng, kan?”
Penyesalan begitu saja menghantamku melihat bagaimana dia justru besar kepala.
“Tapi gue pengen panjangin lagi, nih,” sambungnya.
“Mau saingan sama pacar lo?”
Ia menggeleng. “Mau nemenin rambut panjang lo, dong,” jawabnya lalu nyengir.
“Tai, Syah!” Yang disambut tawa penuh kepuasan Syahdan.
Masa KKN bisa dibilang masa kedekatan kami. Bisa jadi karna kami satu prodi di hubungan internasional. Prodi yang terdengar keren, namun artinya kami harus bekerja keras mempelajari segala literatur asing yang membuat perut melilit.
Sampai kupikir, I don't have “urat malu” when I’m in front of him dan begitupun dia. Pernah satu hari, kami mandi di bilik kamar mandi yang bersebelahan. Dia dengan percaya diri berteriak. “Mar! Lempar pasta gigilah.”
“Ha? Serius, nih?” teriakku balik.
“Serius! Pasta gigi gue habis!”
“Okeh. Wait!” Lantas dengan tenaga ekstra aku melempar pasta gigi melewati dinding yang membatasi kami.
“Adoh!”
Mataku membeliak. Rasa panik seketika menerjangku. “Syah. Kena apa?”
Serius, aku khawatir, pasalnya aku tidak ingin pasta gigi yang aku lempar berhasil mencederai organ vitalnya.
“Sialan! Ngomong dong kalau mau lempar!”
Aku langsung terbahak. “Aman, kan?”
“Aman!”
Tidak menyangka ternyata kedekatan kami berlangsung sampai detik ini. And I think, I'm still willing to be by his side. Mungkin karna sejauh ini dia yang bisa mengimbangiku, atau aku merasa selalu diuntungkan. Begitulah. Seperti pagi ini. Aku baru saja selesai mandi. Saat suara berisik di dapur kudengar, aku buru-buru ke dapur. Bukan karna lapar, lebih karna penasaran.
“Bikin apa?” tanyaku mendekat pada Syahdan. Mataku langsung berbinar melihat apa yang Syahdan buat.
“Smoothie,” jawabnya sambil tersenyum.
Tebakanku benar. “For me?” tanyaku tanpa bisa mengendalikan gemuruh senang.
“Yes.”
“Yeah, gue suka smoothie,” kataku girang.
“Okay, now, sit on your stool.”
Tanpa pikir panjang, aku langsung duduk di atas stool. Tidak butuh waktu lama Syahdan sudah menaruh semangkuk smoothie di atas meja makan.
“Semangkuk smoothie sudah siap,” katanya.
Warna smoothie yang cerah membuat mulutku langsung gatal ingin menyantapnya.
“Thanks, Chef Syahdan,” ucapku tanpa lupa mengerling padanya. Syahdan hanya merespons dengan tawa.
Syahdan tahu aku tidak terbiasa sarapan, tapi dia selalu punya cara supaya aku bersedia mengisi perutku di pagi hari, termasuk dengan cara satu ini. Membuatkanku smoothie. Aku mengambil sendok kemudian mulai menyuapkan smoothie ke dalam mulut. Rasa manis, asam dan lembut langsung memenuhi mulutku. Ini enak.
Syahdan kembali ke meja makan dengan sepiring Herb omolette with fried tomatoes dan semangkuk nasi. Tidak memang tidak perna lupa menambahkan nasi di setiap acara makannya.
“Ini khas orang Indonesia, Mar.” Jawabannya saat kutanya kenapa setiap makan selalu harus ada nasi.
“Habiskan smoothie-nya, jangan sampai gue tahu lo harus berakhir di rumah sakit karna asam lambung,” katanya penuh peringatan.
Aku nyengir. “Kalau sarapan dari Chef Syahdan pasti gue habisin dong.”
Dan bukannya tersanjung, Syahdan justru mendengus.
“Nanti perlu di jemput nggak?” tanyanya lagi.
Aku menggeleng. “Nggak usah, lo lupa mobil gue nngetem di kantor gara-gara sabtu kemarin kita ke bioskop dan makan seenaknya?”
Tawa Syahdan yang renyah langsung kudengar. “Oke, Nyonya.”
Sepuluh menit kemudian kami sudah bersiap berangkat. Aku mengambil tasku kemudian menyusul Syahdan yang lebih dulu keluar apartemen. Begitu sampai di depan kantor, aku langsung melepas seatbelt.
“Nanti kayaknya gue mau ke Hakey,” kataku.
Syahdan mengangguk. “Kabar-kabar aja pengen makan apa.”
“Gampang. Ya udah. Gue turun dulu. See you,” sambungku.
Begitu turun dan menutup pintu mobil, aku bergegas meninggalkan mobil Syahdan yang deru mesinnya masih bisa kudengar. Aku bersyukur karna pagi ini bisa sampai kantor lebih awal.
“Mar!” Seruan barusan membuatku menoleh. Senyumku langsung terukir begitu melihat siapa yang menghampiriku. Maya, gadis yang bisa aku bilang teman kantor paling dekat denganku. Certainly not a matter of vacation abroad or buy branded goods, melainkan soal kebiasaan kami yang senang bergosip.
“Morning!” sapapku.
“Morning. Well, diantar Syahdan?”
Aku mengangguk.
“Wih enaknya. By the way makin ganteng aja si Syahdan, makin hot juga,” bisik Maya.
Kami berjalan melewati lobi lalu berhenti tepat di depan pintu lift.
“Tahu dari mana lo?” Aku menekan angka lima pada tombol lift. Menuju lantai kerja kami.
“Kan gue follow instagram dia.”
“Sinting. Biasa aja dia. Namanya juga rumput tetangga,” kataku.
Maya tertawa. “Gue mau lho sama dia, itupun kalau lo nggak mau, sih.”
“Ingat pacar woi! Tapi terserah sih, itupun kalau Syahdan mau,” ejekku. Aku benar lho.
“Pacar kan bisa ganti. Okay! Nanti gue ke restoran dia. Sama lo, ya,” serunya begitu bersemangat.
Aku tidak bisa menahan tawaku. Sumpah, Maya niat banget, sih.
“Boleh. Kebetulan nanti sore gue mau ke sana,” sambungku.
Dan begitu pintu lift terbuka, kami segera masuk. Beruntungnya lift hanya berisi kami berdua saja. Maya merapat padaku dengan mata memincingnya. Aku memandang Maya penuh kewaspadaan.
“Tapi gue penasaran, pertemanan macam apa antara cowok sama cewek yang kadang tidur satu apartemen?”
Aku takjub dengan Maya dan mengutuk segala fantasi liarnya kali ini.
“For your information, May. I'm still virgin, kalau itu yang sebenarnya mau lo tanyain.”
Maya terbahak. “Gila si Syahdan. Pinter nahan, ya?”
“Itu bukan soal Syahdan yang pinter menahan diri, tapi soal bagaimana gue yang bisa membentengi diri,” ujarku bangga.
“Udah ah, bosen gue ngobrolin ini, ganti topiklah,” sambungku.
Sialnya Maya makin terbahak lantas merangkulku setelah pintu lift terbuka.
“Duh, jangan marah, dong. Habis kalian aneh banget, sih. Udah tua juga, daripada temenan mending nikah.”
“Ini pasti gara-gara nonton film teman tapi menikah. Bahaya emang kalau woman macem lo nonton yang baper-baper kayak gitu. Imajinasi bukannya berkembang, tapi justru meliar,” tudingku.
Maya berdecak. “Yang namanya imajinasi itu emang liar kale,” balasnya sewot.
Aku hanya geleng-geleng saja. Tidak mau lagi membuka mulut, tahu jika membuka mulut topik ini tidak akan selesai.
Oh ya, this is my fifth year working here. An insurance company. Dan Perkara pekerjaan, beberapa orang yang mengenalku, sering mempertanyakan karierku yang berakhir di perusahaan asuransi, sedangkan sebagai sarjana ilmu politik, aku bisa mengajukan lamaran ke multinational corporation, Kemenlu atau bahkan ke embassy office. Walau pada akhirnya berakhir di perusahaan asuransi dengan jabatan financial advisor.
Pekerjaan yang enak-enak susah. Enak kalau sudah menerima gaji. And I think Financial Advisor is more bona fide and comfortable, tentu jika dibandingkan dengan seorang agen. Dan sisi susahnya adalah seperti pertanyaan Maya saat ini. “Kemarin jadi ngurusin komplainnya pengusaha batu bara?”
Aku meletakkan tasku di atas meja kubikel lalu menjatuhkan pantatku di kursi.
“Jadi. Alot banget, tapi ya lumayanlah, terselesaikan. Kalau sampai enggak, di penggal gue sama Bos.”
Maya tertawa. Ia membungkuk lalu menyalakan CPU. Aku ikut menyalakan CPU.
“Namanya juga nasabah,” kata Maya.
Aku setuju. Bekerja di asuransi memang tidak jauh-jauh dari marketing dan keluhan nasabah.
Aku hendak mengajak Maya bicara, namun telepon di meja Maya berdering. Ia segera mengangkatnya dan aku memutuskan mendata beberapa orang yang sudah di follow up pihak marketing untuk menjadi nasabah tetap.
“Mar,” panggil Maya tiba-tiba.
“Gimana?” tanyaku tanpa mengalihkan pandangan dari layar PC.
“Temuin nasabah klaim ya, ortunya habis kecelakaan.”
Oh shit!
***
Pada akhirnya sore ini Maya tidak ikut dengan ke Hakey. Katanya dia harus menemui pacarnya di bandara. Sedangkan aku, sehabis menyelesaikan pekerjaan kantor, langsung meluncur ke Hakey. Selepas memarkirkan mobil, aku lekas masuk. Restoran Hakey adalah milik Syahdan, yang sudah berdiri sejak enam tahun yang lalu. Satu tahun setelah kelulusan kami. Dan jatuh bangun restoran ini tentu sudah kuhapal di luar kepala.
“Sore, Mar!”
Aku menoleh. Menemukan Anna–salah satu pegawai Hakey yang sedang sibuk membereskan meja pelanggan.
“Sore Ann!”
“Sendiri aja?” tanyanya.
Aku cemberut. “Emang gue pernah sama doi?”
“Jan sewot dong, biasanya kan sama Bos,” godanya.
“Bos lo kan di sini kali. Btw, dia di mana?”
“Biasa, kitchen.”
Aku mengangguk. “Oke. Gue ke kitchen dulu, Ann.”
“Siap!”
Aku segera menarik langkah kakiku ke dapur, begitu membuka pintu, apa yang pertama aku lihat langsung membuatku berdecak. Syahdan sedang sibuk dengan salah satu pegawainya yang kuingat namanya Raisa. Tolong, wajahnya tidak seperti Raisa istri Hamish Daud.
Kabar buruknya, seragam kerja yang hanya berupa kaos polos berwarna biru muda itu terlihat begitu menjerit di lekuk tubuhnya. Mereka memunggungiku dengan tubuh sintal Raisa yang terus merapat pada Syahdan. Aku pura-pura terbatuk dan berhasil membuat mereka menoleh. Ekspresi terkejutan Syahdan dengan cepat berubah cerah.
“Oh! Hai,” sapanya.
Seringaiku terbit. “Hai,” sapaku balik lalu mengibaskan rambutku.
Sejujurnya, daripada dengan pegawai junior yang menatapku dengan pandangan yang kuartikan tidak suka itu, Syadan akan lebih cocok dengan model yang melenggok di atas cat walk. Aku jamin.
***