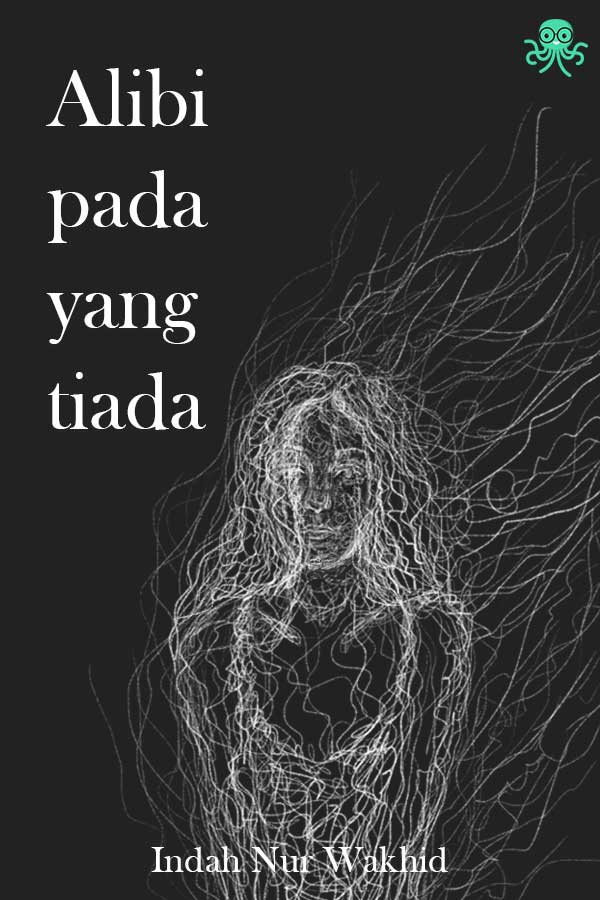
Alibi pada yang Tiada
By Indah Nur Wakhid
SENIN, Minggu Pertama Mei | 06.30 AM
Ini bukan hari impiannya, pagi-pagi buta mendapat kabar meninggalnya seseorang. Perlahan jemarinya meraba-raba pinggiran nakas, menuju ke tengah lalu ke sudut nakas yang merapat pada dinding. Ujung telunjuknya menyentuh jam tangan digital Hello Kitty yang sudah bersamanya selama 5 tahun terakhir. Ia mendengar suara berderit memilukan saat menarik benda itu kedekatnya. Matanya menyipit menatap jarum pendek. Pukul 6 lebih 40 menit. Ya ampun, dia baru kelar mengerjakan laporannya jam 2 pagi, dia pasti ketiduran menjelang jam 3 pagi. Buku, map, catatan, coretan, laptop, bungkus kacang kulit. Semuanya berserakan di atas tempat tidur ukuran single miliknya. Dengan pikiran kosong ia berusaha menggerakkan tubuh untuk berguling turun. Kakinya mengambang sebentar di tepi tempat tidur sebelum benar-benar menyentuh lantai. Diseretnya sandal kelinci besar menuju kamar mandi.
“Nggak mau pergi tapi harus... nggak mau pergi tapi harus...” gumamnya berulang-ulang di depan wastafel, berharap mendapat suntikan semangat dari kalimat itu. Ia mengembuskan napas kuat-kuat. Wajahnya kusut masai. Matanya merah kurang tidur. Ia melotot ngeri. Kantong matanya sudah punya kantong, jumbo size!
“Aaaaarrrggghhh! Disaster!” jeritnya, menyalakan shower dengan kekuatan penuh.
Selesai berurusan di kamar mandi ia menuju ke lemari pakaian. Seluruh tubuhnya segar, matanya terbuka lebar dengan kesadaran terkumpul penuh. Disempatkannya melirik kaca, memastikan tampangnya sudah mendingan. Meski begitu, ia masih enggan berkonsentrasi pada kabar mendadak yang diterimanya pagi ini. Ia mulai memilih pakaian yang pantas dikenakan dalam suasana duka.
Sebagian besar pakaiannya berwarna kalem dan polos tetapi tiba-tiba saja semua terlalu ceria untuk dipakai. Pink, ungu pastel, tosca, magenta, mana warna hitam? Pikirannya mulai nggak sabar. Come on, Jakarta adalah macet, macet pasti Jakarta, semua orang harus menyiapkan an extra time untuk ke mana pun. Tangannya memilah semakin cepat, memangnya dia nggak punya warna hitam?
Got it, ketemu warna hitam! Gadis itu melenguh panjang ketika menarik keluar selembar tanktop.
“Done?” Tiba-tiba suara cempreng Vika mengambang mengejutkan. Lupa kalau dia menghubungi sahabatnya itu – antara sadar dan tidak beberapa menit setelah menatap si Hello Kitty – agar menemaninya menghadiri acara pemakaman ini. “Atau kita mampir ke toko baju dulu untuk beli gaun hitam?”
“Acaranya jam 9, macet, bolak-balik, kayaknya nggak bakal sempet.”
“Good, kalau nyadar sebaiknya buruan ganti baju deh.”
Stevia menggigit bibir, berjalan tersaruk-saruk ke arah kamar mandi lalu keluar lagi dalam waktu kurang dari 5 menit. “Ready,” katanya seraya meringis memamerkan deretan giginya yang rapi.
Terusan cokelat tua yang ia kenakan tepat mencapai lutut. Cukup pantas kalau saja bagian pinggang ke bawah tidak diberi kerut dan ruffle jadi mengembang, seolah ada gas ditiupkan ke dalamnya sampai menggembung. Sedikit udara lagi akan mengubah roknya menjadi balon helium yang bisa terbang ke mana-mana. Tapi daripada mengenakan warna-warna yang membuatnya dikenali dari jarak satu kilometer, gaun ini lebih masuk akal.
“Lu yakin pake gaun itu?” Vika memasang wajah sangsi sambil berdiri, menyambar kunci mobil yang ia letakkan secara sembarangan di atas kasur Stevia, melirik jam tangannya sejenak.
“Memangnya kenapa?” Sedikit terburu ia mengikuti langkah cepat Vika menuju keluar. Mobil sahabatnya parkir melintang secara sembarangan di depan pagar tetapi memang hanya sekitar 5 menit mobil itu perlu parkir.
Dia sedang memikirkan jalur paling cepat. Sesuatu yang sia-sia saja. Diperkirakan sekitar 12 juta orang memadati Jakarta per kilometer persegi! Lebih dari separuhnya berada di jalan pada jam berangkat kerja seperti ini. Vika mendengus. “Kayak gaun anak-anak. Ngomong-ngomong, siapa yang meninggal ini?”
Ya, selama bermenit-menit ia juga menanyakan hal yang sama, siapa yang meninggal? Otaknya dilanda kebingungan dan rasa tak percaya membaca sebaris nama yang di sms-kan ke ponselnya. “Namanya Alma Margareth, pasien, hampir teman.”
Vika menoleh sedetik, buru-buru menginjak rem ketika dua orang anak laki-laki berseragam putih abu-abu mendadak melesat menyeberang di antara kemacetan. Ia yakin anak-anak itu nekat menyeberang sembrono karena takut terlambat sampai di sekolah sementara jembatan penyeberangan terlalu jauh dan plang di atas zebra cross bertuliskan ‘Anda dilindungi undang-undang apabila menyeberang di sini’ sudah lama tidak ada, jadi menyeberang di mana aja sama. Ia mengumpat pelan, mengembalikan konsentrasi kepada Stevia. “Hampir? Emangnya lu nggak mau temenan sama pasien?”
“Aku harus objektif, selama pertemanan nggak mempengaruhi kinerja, aku mau.”
“Jadi... hampir teman itu seperti apa?”
“Saling say hello lewat text, menanyakan hal-hal remeh yang manis seperti udah makan belum?” Ia menghela napas, Alma sering melakukan itu, ia hanya sesekali membalas. Itu pun dengan kalimat pendek yang dingin. Setitik penyesalan menelusup. Mungkin, kalau dia lebih care sedikit aja, dia akan tahu kenapa mendadak gadis itu tiada.
“Oh, memang seperti apa biasanya lu sama pasien lu yang lain?”
Ia menghela napas lagi. “Seperti kamu dan dokter umum. Datang, ketemu, bicara, dapat resep kalau si pasien memang perlu obat, terus pulang.”
“Gue dan dokter umum.” Vika membeo. “Nggak ada yang namanya ‘hubungan’ antara gue dan dokter umum. Gue bisa ke dokter umum yang berbeda tiap kali gue sakit sedangkan lu, mereka selalu kembali ke elu kan?” Vika menginjak rem untuk kesekian kali dalam 10 menit terakhir. Mobil itu tak berdaya melawan kemacetan. Sambil menahan sabar dan berharap mereka tidak terlalu terlambat tiba di acara pemakaman, keduanya diam menatap jalan.
Stevia mengangguk pelan, amat pelan. “Ya, beberapa,” sahutnya lirih.
“Mereka merasa terhubung sama lu tapi lu enggak.” Vika mengetukkan jari ke setir, menandakan ia mulai diserang rasa tak sabar sementara kendaraan di sebelah mobil mereka menurunkan kaca menampakkan lelaki setengah baya yang asyik mengangguk-angguk mengenakan headset, menikmati macet!
“Kenapa nadamu menyudutkan begitu?” Pikirannya melayang. Alma Margareth, 27 tahun, sukses, setidaknya orangtuanya sangat sukses hingga mampu mendanai usaha fashion yang digeluti Alma. Dia penjual yang selalu nampak ceria di depan customer. Kecuali psikisnya, Alma sehat. Gadis itu menegakkan tubuh agar oksigen bisa terpompa dengan lebih baik ke paru-parunya.
Kepergian Alma terlalu mendadak. Kemarin sore mereka masih bertemu untuk membahas sumber depresi gadis itu. Alma mengatakan kalau ia tidak bisa tidur selama empat hari lantas gadis itu terburu-buru pamit karena ditelepon salah satu kliennya yang datang ke butik. Mereka janjian ketemu lagi sore ini di tempat praktik. Sekarang baru pukul delapan kurang sekian menit. Status Alma sudah berubah dari hidup menjadi mati. Alma takkan muncul. Hari ini, besok, selamanya. Ia tak berani membayangkan seperti apa pemandangan yang akan dilihatnya nanti.
Hpnya bergetar tepat ketika ia kelar mengganti profilnya dari umum menjadi getar karena takut ketika semua orang sedang khusyuk berdoa benda itu mendenging-denging menggila mengganggu semua pelayat, entah mengapa belum apa-apa ia sudah merasa tegang.
Deretan angka tanpa nama muncul di layar. Ia tidak pernah mengangkat telepon tak dikenal. Tetapi ketegangan di otaknya sedang memegang kendali, tanpa diperintah telunjuk kanannya menekan tombol terima. Suara berat seorang laki-laki yang kebanyakan merokok dan jarang ketawa terdengar kaku menyapa telinganya.
“Dokter Stevia Santoso?”
Alisnya mengkerut hingga nyaris berkumpul di pangkal hidung. “Benar, siapa?”
“Kami dari pihak kepolisian ingin menyampaikan surat pemanggilan, di mana posisi Anda sekarang?”
Dengan gugup Stevia menyebutkan alamat Alma Margareth. Sedetik berikutnya ia langsung merasa super bodoh. Mau apa mereka? Apakah mereka akan ikut datang ke acara pemakaman itu, mengawasinya seolah-olah dia residivis yang berencana kabur? Memangnya apa yang sudah dilakukannya? Kenapa secara otomatis ia memberitahukan posisinya? Gugup pula! Seharusnya ia memancing informasi dulu sebelum membocorkan keberadaannya!
Tenang Stev, nggak ada yang perlu ditakutkan kalau kamu nggak melakukan apa-apa. Dan kamu memang nggak melakukan apa-apa! Kata hatinya menenangkan. Selanjutnya ia menyimpan hp itu ke dalam tas, mengancingkan tas lalu menelungkupkan kedua tangannya di atas tas. Semua itu dilakukannya slow motion.
Vika meliriknya. “Telepon dari siapa?”
“Nobody,” sahutnya dengan napas tersengal. ia tak ingin Vika berpikir yang aneh-aneh atau jadi ketakutan padanya. “Polisi, Vik, aku baru aja ditelepon polisi!” pekiknya dalam hati. Kenapa aku ditelepon polisi? Mereka nggak berpikir bahwa aku penyebab kematian Alma kan? Tengkuknya bergelenyar, obat-obat itu, gumamnya dalam diam.
Mobil bergerak semakin pelan. Kepala Vika menjulur-julur mencari celah di mana ia bisa menyelipkan mobilnya sedekat mungkin dengan tempat acara, sementara Stevia menerawang setengah melamun memandang deretan mobil dan karangan bunga yang tak terhitung. Rumah duka masih sekitar 40 meter lagi tetapi mereka tak mungkin mendekat. Vika mematikan mesin.
“Kita turun di sini,” katanya menyerah seraya membuka pintu. Udara dingin berembus menerbangkan partikel tak terlihat di jalanan yang meskipun penuh orang, terasa lengang. Manusia yang hilir mudik datang dan pergi tanpa suara. Kepala mereka tertunduk menyesalkan usia belia yang berakhir pagi ini. Keduanya beriringan mendekat ke arah tenda putih di mana beberapa anak muda berdiri menyambut pelayat dengan wajah datar. Setiap orang digiring melewati deretan kursi plastik bertutup kain putih berenda menuju ke pintu berbentuk kupu-kupu yang membuka lebar.
Dada gadis itu berdebar tak terkendali sewaktu kakinya berada di ambang pintu, berusaha tidak gugup ketika mendekati peti kaca. Alma berbaring seperti putri salju yang tersihir menunggu pangeran berkuda putih menemukannya, terpesona dan memberi true love kissuntuk membangunkannya. Cantik tanpa cela seolah dia berada di dalam peti itu demi pemotretan krim pelembap muka yang bekerja saat pemakainya tertidur pulas.
Ia bengong di situ lebih dari 5 menit.
Lelaki muda yang baru datang membuatnya tersadar, pria itu berdiri tepat di hadapannya, memandangnya sambil lalu, menatap serius pada wajah Alma. Semuanya serba sebentar. Ekspresi menganalisa, mencari sesuatu, heran, ngeri, bahkan seperti… puas! Berganti-ganti dalam hitungan detik. Dengan cepat pria itu menunduk memberi penghormatan terakhir kemudian keluar.
Stevia ikut melangkah keluar. Apakah Alma sempat dibawa ke rumah sakit? Apa jenazah Alma divisum? Apa hasil visumnya? Ia melihat lelaki tadi memilih duduk di deretan kursi paling belakang. Di sebelahnya duduk lelaki lain, mengenakan kaca mata hitam trendy yang membuatnya tampak gagah sekali. Semoga saja ia tetap mengenakan kacamata sampai akhir acara. Beberapa lelaki justru jadi kurang menarik ketika melepas kacamata hitam mereka, ah, mikir apa sih?
Sejenak ia celingukan mencari Vika. Ketika ia melangkah ke dalam tadi, Vika tak ikut masuk. Temannya itu memilih mencari tempat duduk dan menunggu di luar. Akhirnya ia menemukannya, dilihatnya Vika duduk di deretan paling belakang, 8 kursi dari dua pria yang menarik perhatiannya tadi. Tangannya menahan rok yang mengembang terkena angin ketika melewati deretan tempat duduk menuju ke arah Vika sambil menggumamkan permisi beberapa kali.
Perlahan ia duduk, memindahkan tas cangklong ke pangkuan dan melirik jam tangan. 10 menit lagi kebaktiannya dimulai. Tubuhnya miring ke arah Vika agar bisa berbisik. “Aku belum pernah ikut kebaktian, apa sebaiknya kita tetap di sini atau pergi?”
Vika menatap lurus ke depan. “Pergi sebelum kita terjebak dalam prosesi panjang yang nggak kita mengerti.”
Benar, toh ia tak bisa berkonsentrasi maupun khusyuk berdoa. Ada polisi yang ingin datang ke kantor. Apakah para polisi itu sudah punya data dirinya? Memegang fotonya? Astaga, dia membayangkan bagaimana polisi mengunduh fotonya dari semua akun jejaring sosial miliknya, mengeprintnya besar-besar lalu membagikannya ke anggota polisi se-Jakarta. Jakarta yang overpopulated, Jakarta yang menghasilkan satu ton sampah setiap hari, Jakarta yang takkan pernah kelar menyelesaikan masalah macet dan banjir siapa pun gubernurnya. Ia menelan ludahnya susah payah, mengangguk siap berdiri. “Oke, kita pergi sekarang.”
“Sebentar.” Vika menutupkan telapak tangannya ke punggung tangan Stevia, memaksa Stevia duduk kembali dengan heran. “Aku nggak tahu kalau kamu ternyata kenal Ezra Adiputra,” bisiknya.
“Siapa?”
“Come on, cowok paling hot selama 5 tahun terakhir.”
“Please Vik, ini acara pemakaman.” Ia mendengar lonceng berdenting merana dari dalam rumah. Orang-orang yang sibuk mendengung rendah. Anggota keluarga dan aktivis gereja berlalu lalang sambil berkoordinasi. Tetamu menunggu dalam diam, penuh kesedihan. Benar-benar dosa rasanya kalau membicarakan cowok hot.
Namun beberapa lelaki memang tampak hot. Seorang model, seorang aktor FTV, eksekutif muda (sangat muda) yang terlalu sukses sebelum waktunya dan segerombolan pria super rapi yang meskipun hot harus dipertanyakan orientasi seksualnya. Stevia mengenal salah satunya, lelaki dengan foundation, bedak tipis dan maskara itu, pernah mengantar Alma ketika berkonsultasi. Suatu malam saat Jakarta diguyur gerimis, konsultasi ketiga mereka. Siapa ya namanya? Udin, Ujang, Cecep? Bukan, namanya terdengar sedikit lebih nyentrik. Mark, ya, itu namanya.
Pastor berpakaian putih memasuki rumah. Ia pasti melamun karena tak menyadari ketika pastor itu lewat. Padahal ia duduk tepat di pinggir jalan masuk. “Sekarang atau di sini sampai selesai,” bisik Stevia resah. Ia ingin cepat-cepat pergi sementara orang-orang bergerak mendekat untuk mengikuti misa.
Vika berdiri.
Stevia mengikuti ke mana arah pandangan Vika. Lelaki yang tadi berdiri di hadapannya juga sedang bangkit dari tempat duduknya, memasang kacamata hitam lalu berjalan tergesa ke arah mereka berdua. “That’s him?” bisik Stevia, merasa gila karena sempat-sempatnya melirik cowok ganteng di saat seperti ini.
“Ya, mapan, matang, seksi.”
Blodyhell! Laki-laki itu tepat seperti yang dikatakan Vika, meski namanya tak terdengar sangar, dibandingkan para model yang berseliweran, dia jauh lebih maskulin dan menantang. Oke stop! Otaknya mungkin sudah lumer akibat panas dan terlalu tegang di acara duka ini. Stevia meninggalkan kursi, menjauh dari kerumunan kemudian berjalan berlawanan arah dengan semua orang. Hanya dirinya, Vika, dan dua lelaki itu yang meninggalkan rumah duka. Seharusnya dia tadi membawa kacamata hitam. Mendadak benda itu sepertinya bisa melindunginya saat ini. Beberapa orang menatap ke arah mereka berempat.
Oh wow, ia baru sadar kalau mereka terlihat seperti dua pasang lelaki dan perempuan yang tidak punya hati karena meninggalkan acara justru saat pastor mulai berdoa.
40 meter kemudian, setelah berjalan beriringan selama entah beberapa menit tanpa saling melirik satu kali pun, kedua pria itu menyelinap ke sebuah wrangler. Mesinnya nyaris tak bersuara sewaktu mundur kemudian melesat entah ke mana. Sungguh ajaib bahwa mobil mereka ternyata bersebelahan. Grandis Vika segera mengekor kendaraan itu.
“Apa yang harus kukatakan?” pikir Stevia, melirik sahabatnya sedetik, berpindah menatap wrangler di depannya. Mana mungkin dia minta di drop di kantor polisi. Vika sahabat yang baik tapi ia agak ember pada orang-orang yang sudah akrab dan Vika akrab dengan mamanya! Tanpa diminta saluran pernapasannya menarik oksigen dan menyingkirkan karbondioksida dengan buru-buru. Embusannya terdengar keras.
“Gimana caranya membuat Ezra menyadari kehadiranku?” kata Vika tiba-tiba. “Kita nggak mungkin menyelip terus berhenti di depan mobilnya kan?”
Butuh beberapa detik sebelum Stevia menangkap perkataan Vika lantas menyahut. “Klaksonin aja sampai mereka berhenti karena heran. Kalau sudah jengkel, salah satunya pasti keluar.”
“Hmm... agak aneh tapi nggak ada salahnya dicoba. Kalau mereka turun dari mobil terus gimana?” Vika terdengar bingung dan penasaran.
“Pura-pura salah orang.”
“Garing.” Nada bingungnya berubah menjadi sedikit sebal. Kalau saja Stevia tak melihat wajahnya, ia pasti membayangkan seraut wajah ketus yang kesal dengan alis mencuat. Kenyataannya Vika hanya menatap kosong ke depan.
“Bilang aja seumur idup kamu selalu mimpi suatu hari bisa mengemudikan sebuah wrangler.”
“Norak.”
Stevia tertawa kering. “That’s it, kamu garing dan norak. Sekarang drop aku di perempatan itu, ada klien yang harus kukunjungi.” Dia harus turun, menyetop taksi dan ke kantor polisi sebelum polisi mengira dia melarikan diri betulan lalu melacaknya ke kos dan ke rumah orangtuanya. Mama papanya bisa pingsan sambil berdiri tegak kalau sampai itu terjadi.
“Apakah sehat menemui klien sedangkan lu baru aja menyaksikan kematian salah satu klienmu?”
“Awalnya aku ngerasa sehat but thanks God, berkat kata-katamu aku nggak ngerasa sehat lagi.”
“Sorry.”
Wrangler itu ke kiri, mereka seharusnya ke kanan tetapi Vika membelokan mobil ke kiri.
“Kenapa kita ngekor mereka?” seru Stevia berusaha tak kehilangan kendali. Kebutuhannya untuk berhenti sudah seperti pecandu mariyuana yang membutuhkan suntikan untuk meredakan rasa sakit yang bisa membuatnya kejang-kejang tak keruan.
“Gue ingin tahu ke mana Ezra. Ini kesempatan langka.”
“Tapi aku harus turun sekarang,” desis Stevia menahan diri. Kalau satu kali lagi niat turunnya gagal dia pasti menjerit.
“Tunggu sampai mereka berhenti baru gue bakal berhenti.”
“Kamu stalk dia, i can’t believe it!” bentaknya.
“Shhh... gue kudu nginget nomor polisi mobil keren ini.” Vika sama sekali tak menyadari bahwa Stevia serius dengan kemarahannya sekaligus gemetar mendengar Vika menyebut kata ‘polisi’.
“Bisa aja ini mobil lelaki yang satu lagi.” Gadis itu berdecak.
“I really hate you kalau lu benar!”
Wrangler berisi Ezra dan rekannya berbelok ke pelataran kafe. Pemandangan yang semakin menjengkelkan Stevia. Seharusnya tadi ia membawa kendaraan sendiri, meminta Vika mengekorinya agar bisa bersama ke pemakaman itu lalu pulang sendiri-sendiri. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Sebenarnya bubur juga enak kalau diberi kuah sup ayam tapi dia benci bubur apa pun lauknnya! Matanya menyala-nyala manakala grandis Vika berhenti tepat di samping wrangler kedua pria itu.
Percuma saja ia memasang wajah cemberut paling seram yang dia bisa. Vika langsung melompat turun, tergesa berjalan di belakang kedua pria itu. Stevia terpaksa ikut turun tetapi ia memilih berdiri di pinggir jalan untuk menunggu taksi.
“Ezra!” seru Vika.
Great, dia menyerang. Stevia mempercepat langkah menjauh sambil menelepon layanan taksi yang sibuk melulu sejak tadi.
Lelaki jangkung itu menoleh. “Maaf?” Suaranya tenang, ekspresinya datar.
Seharusnya lelaki ini bernama Jagad, Bumi, Bimasakti, Gagah atau sesuatu yang lain yang mengesankan kekuatan. Nama Ezra terlalu imut bagi sepasang mata elang yang somehow bisa kelihatan teduh dan tengah menyorot heran itu.
“Nggak inget ya, kita pernah ketemu beberapa kali di acara keluarga, gue ingat lu juga datang di acara pernikahan kakak gue.”
“Oh...” Pria itu tersenyum seadanya. Kentara sekali kalau dia tidak ingat namun berusaha tidak mempermalukan orang lain. “Apa kabar?”
“Baik, boleh gabung ya? Kebetulan gue juga mau sarapan.”
Ezra menoleh ke sebelahnya.
“Sure, temanmu nggak diajak?” Pria disebelah Ezra melirik ke arah Stevia yang berdiri di dekat pohon palem sekitar 4 meter dari situ. “Siapa namanya?”
“I’ll do it.” Ezra tiba-tiba menepuk perut temannya, berjalan mantap ke arah Stevia meninggalkan Vika yang menganga dan temannya yang melongo.
Mata Stevia membesar. Hell no! Dirinya nggak akan mau berkomunikasi dengan lelaki itu se-seksi apa pun dia. Ia menjerit dalam hati. Please, Vik, selain tindakanmu itu sangat memalukan, lelaki itu sempat kelihatan puas melihat sosok Alma terbujur kaku!