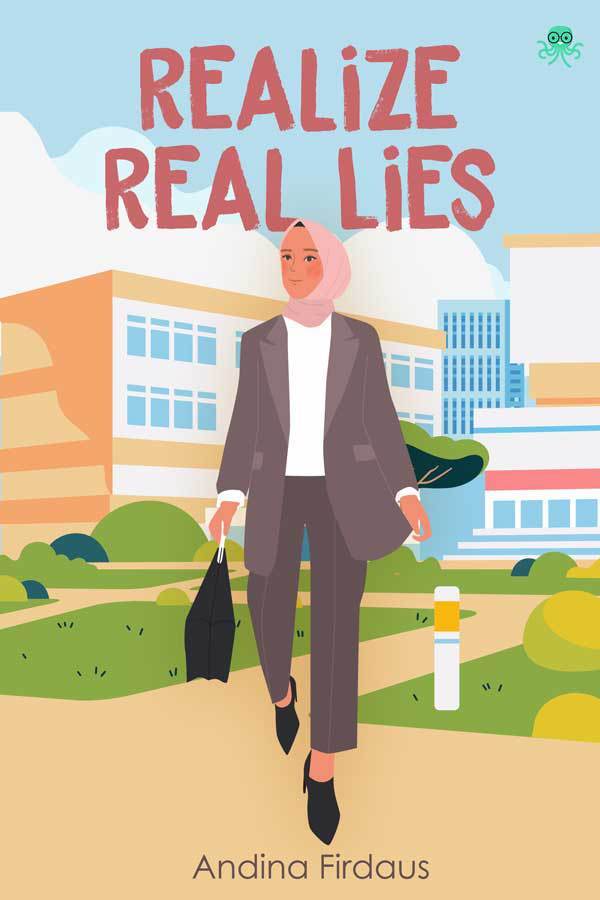
Realize Real Lies
By Andina Firdaus
Langit tampak gelap, tak sabar untuk menumpahkan airnya. Membasahi tanah, mengguyur pepohonan, serta membuat orang-orang yang berlalu-lalang menepi. Dari pendopo kampus yang semakin ramai, Senja mengalihkan perhatian ke jam tangannya. Sudah pukul empat. Detik demi detik dilaluinya. Kembali ditengoknya draf tesisnya yang sudah dibubuhi banyak coretan. Pikirannya sudah ingin langsung menyelesaikannya, tapi apa daya badannya benar-benar lelah. Ia ingin segera tiba di rumah lalu tidur. Tak perlu ditambah dengan hujan-hujanan. Ia harus segera pulang. Jangan sampai nikmat sehat tak dirasakannya di waktu liburnya besok.
Tak melihat tanda-tanda kehadiran orang yang ditunggunya, Senja menyandarkan punggungnya nyaman. Dengan santai kakinya berselonjor. Pandangannya jatuh ke sepatu berhak yang sengaja dibelinya lima tahun lalu. Benda yang menemaninya, menjadi saksi atas perjuangannya. Dari yang mulanya pekerja paruh waktu di restoran cepat saji dengan sepatu kets, jadi bersepatu tinggi untuk membagikan selebaran informasi sebuah properti, kemudian naik ke manajemen kantor untuk Praktik Kerja Lapangan, sampai akhirnya training hingga kemudian jadi karyawan tetap. Refleks ia tersenyum. Sudah sejauh ini, pikirnya.
Langkah kaki yang mendekat ke arahnya membuatnya menegakkan kepala. Senja langsung berdiri. Ia tersenyum, sedikit menunduk pada pria tambun berkacamata yang tersenyum lebih dulu padanya.
“Di sini saja, ya?” Prof. Lingga, pembimbingnya itu duduk di sebelahnya. “Tadi saya ketemu mahasiswa saya di S1, mau sidang juga,” lanjutnya seraya mempersilakan Senja duduk kembali.
Tak berlama-lama, Senja mengeluarkan map berlogo kampus yang langsung diberikannya pada Prof. Lingga. Pria berbatik cokelat itu membuka map berisi draf tesis anak bimbingannya. Lengkap dengan lembar catatan revisi, lembaran persetujuan untuk draf akhir, dan lain sebagainya. Tak banyak bertanya, Prof. Lingga menandatangani berkas pada tiap bagian bertuliskan ‘Pembimbing I’.
“Untuk tawaran saya kemarin, bagaimana?”
Senja menggigit bagian dalam bibirnya. Prof. Lingga membuatnya kembali berpikir soal penawaran yang sudah mereka bicarakan sejak Senja mengajukan judul tesis.
“Memang, kampusnya belum lama berdiri. Tapi sudah terdaftar dan sudah terakreditasi juga. Satu yayasan dengan Universitas Buana Jaya di Bandung. Ya ... lumayan untuk pemula. Kampusnya tidak sebesar kampus ini. Fasilitasnya pun belum begitu lengkap. Tapi sejauh ini menurut saya cukup potensial.”
Senja sudah memikirkannya. Segala hal sudah dipertimbangkannya untuk menerima tawaran menjadi dosen di universitas yang dikembangkan Prof. Lingga bersama kawan-kawannya yang tergabung dalam organisasi perkumpulan alumni sebuah universitas negeri.
“Kalau siap, ada jeda satu semester untuk kamu berkenalan dengan kampusnya, mengurus apa yang perlu diselesaikan di sini. Tidak masalah.” Prof. Lingga terus menjelaskan sementara Senja hanya bisa mengukir senyum, menyembunyikan segala hal yang terbesit di benak.
Di sela-sela pikiran Senja, Prof. Lingga merogoh tas kemudian menyerahkan sebuah brosur bergambar kampus, lengkap dengan label akreditasi yang biasanya jadi andalan kampus swasta dalam mengenalkan diri.
“Silakan kamu pelajari dulu,” tutup Prof. Lingga sambil mengembalikan berkas Senja.
Pergi jauh dari kedua orang tua, meninggalkan adik-adik, Senja masih perlu memikirkannya matang-matang. Terlebih belakangan ini Senja masih belum pulih berdamai dengan Banyu—adik bungsunya—yang ‘dipaksa’ masuk pesantren. Sesekali Senja berpikir kalau dirinya sudah keterlaluan. Tapi mengingat hal yang jadi sebab dari langkah yang diambilnya itu, Senja sama sekali tak menyesal.
Berbeda dengan dua adik pertamanya, usia Banyu terpaut jauh dengannya. Dengan Fajar dan Taufan, Senja masih bisa berlagak menjadi kawan mereka. Menjadi serba ingin tahu, mengakrabkan diri walau menyebalkan, tak peduli gerutuan mereka. Tapi dengan Banyu, Senja tak bisa menjangkaunya. Umur mereka terpaut sepuluh tahun. Senja tak tahu apa yang dilakukan adiknya di warung internet sampai mengabaikan sekolah bahkan tak jarang sampai tidak pulang ke rumah. Senja terlambat tahu akan kenyataan itu. Mungkin karena kesibukannya yang membuatnya tiba di rumah tinggal tidur atau kedua orangtuanya yang memang sengaja menyembunyikannya karena mereka tahu bagaimana Senja akan bereaksi.
“Kalau gini terus gue masukin pesantren lo, ya!”
“Kak—”
“Mau jadi apa nongkrong di warnet terus-terusan kayak gitu?!” Senja mengabaikan interupsi ibunya. “Lihat rapot lo! Sekolah mana yang mau nerima nilai rata-rata segitu?”
Tiap kali Senja memarahi adik-adiknya, seperti biasa tak akan ada yang menengahi. Pun kedua orangtuanya sudah tak punya tenaga lebih untuk mengomeli Banyu yang masih senang main-main. Wajar lagi umurnya, wajar laki-laki. Basi! Selalu itu yang jadi pembelaan mereka untuk Banyu. Sementara adiknya yang lain, mereka memilih mundur ketimbang kena semprot Senja.
“Bu, Adek tuh nggak bisa kalau cuma sekolah umum. Main terus kerjaannya. Sampai nggak pulang. PR-nya nggak tahu dikerjain nggak tahu enggak. Mau jadi apa Adek kalau gitu terus?” ucap Senja saat mendapati Banyu yang lagi-lagi melakukan kesalahan yang sama.
Orang tuanya angkat tangan, tak lagi mengomentari ide Senja. Hingga akhirnya Banyu benar masuk pesantren.
Ada masanya Senja merasa sudah terlalu jauh melangkahi kedua orangtuanya dalam mengurus adik-adiknya, mengarahkannya, mengaturnya. Tapi tetap saja ada pikiran bahwa ia memang harus melakukannya sekalipun perasaan tidak enak pada kedua orangtuanya setia melingkupinya.
Perasaan bersalah pada Banyu mengiringi langkahnya hingga kini. Ditambah dengan kenyataan kalau hubungan mereka tidak baik. Hanya Senja yang berusaha untuk kembali dekat dengan sang adik. Menanyakan kabarnya lewat kedua orangtua mereka, Fajar, Taufan ataupun Iman paman mereka.
Senja anak pertama dengan tiga adik laki-laki. Cukup Senja yang merasakan bagaimana ia tumbuh besar dengan segala ketidaktahuan dan kekurangan dalam keluarganya. Jangan adik-adiknya. Mereka tidak boleh begitu. Segalanya Senja berikan untuk mereka. Tapi kadang Senja lupa, kalau hal tersebut tidak sepenuhnya tanggung jawabnya. Yang ia lewatkan juga, kalau segala perlakuannya pada adik-adiknya adalah untuk membantu orangtuanya, bukan untuk menjadi orangtua.
“Saya pamit duluan, ya, Senja.” Prof. Lingga membuyarkan lamunan sang anak didik. “Nanti langsung kabari saya bagaimana-bagaimananya. Masih banyak waktu.”
Tanpa berkata-kata, Senja terangguk, ikut berdiri melepas kepergian sang dosen.
Sebenarnya Senja sudah tahu jawabannya. Tapi, entah kenapa ia merasa perlu untuk memikirkannya lagi.
“Waaah! Pradhina Senja, S.E., M.M! Gila, gila ....”
Seruan Raina menyambut Senja di parkiran kampus. Senja tersenyum melihat Raina yang masih mengenakan setelan kerja. Perempuan semampai itu sedikit menunduk, memeluknya erat. Senja tersenyum penuh. Tangannya terangkat membalas pelukan Raina. Harum body lotion susu bercampur parfum vanila menguar di penciumannya.
Raina juga masuk dalam pertimbangannya untuk pergi. Orang yang sekali-kali membuat Senja berpikir, bagaimana hidupnya kalau tidak ada perempuan itu? Raina terlalu memberi banyak pengaruh. Senja payah dalam urusan beradaptasi, mengenal lingkungan baru, orang-orang baru. Di kantor saja, kalau tidak ada Raina—temannya sedari kecil yang kebetulan bekerja di perusahaan yang satu gedung kantor dengannya—Senja mungkin tak akan pernah makan di luar atau setidaknya di kantin karyawan yang letaknya di rooftop, juga kantin lain di belakang gedung.
Raina kecil adalah si tetangga yang selalu tiba-tiba datang ke rumahnya, mengajaknya bermain. Sampai semakin besar, Raina adalah sosok teman yang akan meneleponnya untuk sekadar bercerita sepanjang malam. Bahkan cukup sering baik Raina maupun Senja menginap. Kalau tidak mengenal Raina, mungkin Senja tak akan mengalami hal-hal itu. Sedikit demi sedikit Senja pun terbiasa, juga melakukan timbal balik. Rumah Raina adalah tempat pelariannya saat segala hal sulit dalam keluarganya semakin dimengertinya.
Senja dan Raina amat berbeda. Raina yang mudah dekat dengan orang dan Senja yang selalu enggan. Senja yang pendiam dan seperlunya, sementara Raina si penyemarak suasana. Senja si anak sulung dengan tiga orang adik sementara Raina si anak tunggal. Senja yang tak pernah mau tahu akan hal yang bukan urusannya sementara Raina yang serba tahu. Ada kalanya Senja berpikir kenapa mereka bisa berkawan akrab dalam jangka waktu lama.
Sekali-kali dihinggapi masalah adalah lumrah bagi setiap hubungan. Berbeda sekolah menjadikan Senja dan Raina menemukan teman baru. Kesibukan juga berbeda. Tapi selalu ada waktu untuk bersama. Semakin dewasa, sesekali Senja merasa kehilangan tiap kali Raina memiliki kekasih. Tak ada Raina yang memaksa Senja keluar untuk sekadar ngopi di kafe atau nonton film di bioskop. Yang ada hanya Raina yang tiba-tiba meneleponnya, bercerita panjang lebar soal hubungannya dengan sang kekasih walaupun Senja hanya mendengarkannya, tak bisa merespons dengan baik.
Siklusnya selalu sama. Tiap kali Raina memiliki kekasih, maka intensitas Raina merecokinya pun akan semakin sedikit. Meski begitu, Raina tetap sama. Tiap kali bertemu, ia akan selalu heboh, mencecar Senja dengan banyak tanya dan cerita. Sering kali Raina gemas pada Senja yang hidupnya begitu serius dan tak pernah punya urusan dengan laki-laki.
Dari beberapa pria yang dekat dengan Raina, baru saat bersama Bian Senja merasa lega. Entah karena lelaki itu adalah kawannya atau karena Senja sangat mengenal sosok pria yang kenal dan tumbuh bersama dengannya sejak zaman training untuk di kantor pusat tempatnya bekerja. Bersama Bian, Raina tak pernah curhat seperti saat dengan kekasih yang sebelum-sebelumnya. Berkeluh-kesah soal hubungannya pun tidak.
Dilihatnya kembali Raina yang sudah mengurai pelukannya. Lagi, Senja berpikir, bagaimana hidupnya kalau ia tak mengenal Raina?
“Yuk, makan-makan!” seru Raina semangat lengkap dengan senyuman lebar.
Senja berpikir sejenak, mengangguk, kemudian berkata, “Lo sendirian?”
Kemunculan pria gondrong berkacamata yang dari mobil hitam langsung menjawab pertanyaan Senja. Iman, adik bungsu ibunya yang tinggal serumah dengannya itu melangkah ke arahnya, mengambil tas yang Senja jinjing. “Lama lo!” katanya kesal.
Senja berdecak. “Gue nggak minta lo jemput, ya!” ucapnya tak kalah sebal, mendelik pada pamannya yang sudah seperti kucing dan anjing dengannya itu.
“Ayo, Sen!” seru Raina, menggamit lengan Senja, menyusul Iman yang sudah masuk kembali ke mobil.
“Gue kira lo sama Bian,” kata Senja pelan. Entah tak mendengar atau pura-pura, Raina tak merespons apa-apa. Perempuan itu langsung duduk di depan bersama Iman sambil melihat-lihat draf tesis Senja.
Dari kursi belakang, Senja yang tadinya ingin tidur malah melihat dua manusia di kursi depan.
Setelah hari itu Senja tidak bisa lagi santai melihat keduanya. Dulu Senja mengira kalau Iman hanya biasa saja menyukai Raina yang periang. Tapi semakin lama Senja perhatikan, Iman cukup sering mengantar-jemput Raina. Iman juga selalu jadi tempat cerita Raina. Bahkan ketika Senja tak ada di rumah, Raina akan tetap datang ke rumah selagi ada Iman di sana.
Senja tahu bagaimana perasaan Iman pada Raina. Tentu ia tak mau kalau pamannya itu diberi harapan palsu. Terlebih Raina sedang menjalin hubungan dengan Bian. Senja tak akan berpihak pada siapa pun. Bahkan Senja ingin tidak peduli dan tutup mata saja. Tapi lama-kelamaan, berbicara pada Raina memang harus dilakukannya.
“Rain, lo kalau serius sama Bian, udahlah, jalanin aja. Dia baik, nggak aneh-aneh. Gue kenal dia udah lumayan lama.” Senja buka suara saat menemukan Raina di rumahnya usai lari pagi.
“Lo naksir Bian?” tembak Raina santai.
Senja mencebik. “Lawak lo! Tahu sendiri gue sama Bian gimana.”
Raina memanyunkan bibir. “Iya gue tahu. Lagian, kok lo ngomong gitu?” tanyanya, tak menangkap maksud Senja.
“Lo masa nggak ngerti?” Senja menggeleng takzim. “Lo sama Iman—”
Mendengar nama Iman, Raina ber-oh ria, terkekeh. “Kita cuma ngobrol.”
“Elonya ngobrol doang. Imannya enggak gitu,” kata Senja terang-terangan. Ia tak peduli kalau Iman akan protes nantinya. Lagi pula tidak mungkin kalau Raina tidak mengerti bagaimana Iman padanya.
“Enggak gitu, Sen. Gue—”
“Bukan gue mau ngatur elo. Cuma ya ... Iman om gue, Bian juga teman gue.”
“Ngerti apa lo urusan ginian?” ledek Raina masih dengan kekehannya, berhasil membuat Senja gondok. “Gue ngerti maksud lo. Enggak, gue nggak aneh-aneh kok sama Iman. Sumpah! Gue cuma ngobrol-ngobrol. Curhat.”
Senja tahu apa saja yang jadi curhatan Raina soal Bian. Sesekali Iman menyinggungnya tiap kali Senja berkata untuk tidak terus-terusan meladeni Raina.
“Sibuk dikit, nggak bisa main sama lo, nggak bisa nurutin kemauan lo, itu tuh wajar. Hidupnya nggak melulu soal lo.”
Raina mengatupkan mulutnya mendengar itu. Melihat reaksi kawannya, Senja berdecak. “Ah iya, gue nggak ngerti urusan ginian. Bukan urusan gue juga,” kata Senja pada akhirnya sebelum pergi dari hadapan Raina.