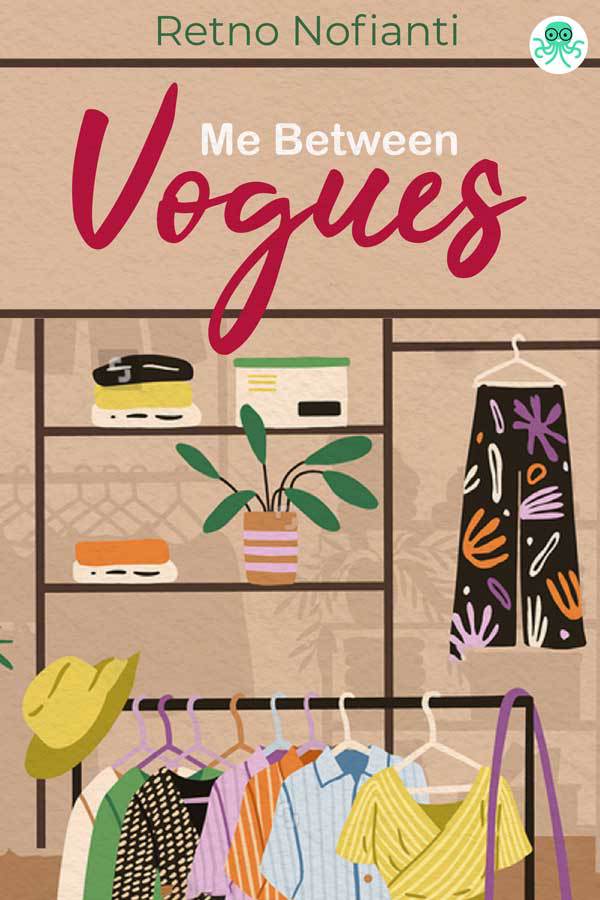
Me Between Vogues
By RetnoNofianti
Satu, dua, tiga. Oke, cukup. Aku bisa mati. Dadaku berdegup kencang. Jemariku gemetaran, mencengkeram erat kemeja flanel yang begitu pas membalut tubuhnya. Susah payah aku maraup oksigen sebanyak mungkin. Menatapnya lurus tepat di manik mata. Kami sama-sama terpaku.
“Maaf,” katanya kemudian. Dia berusaha mundur.
Aku masih bisa merasakan manis dari bibirnya yang sedikit tebal. Pun bau mint yang menguasai rongga mulut. Jujur saja, aku belum ingin semua ini berakhir. Selama ini aku tidak pernah berpikir akan menyerang seorang pria sebrutal itu. Hanya saja, momentumnya sangat pas. Hujan, mati lampu, sebotol whisky, dan hanya berdua di kamar.
“La,” suaranya terdengar serak. Aku tidak peduli. Dia mundur maka aku maju, membabat habis jarak yang tercipta beberapa detik lalu. Mungkin nanti aku akan menyesal. Itu urusan nanti.
Sekali lagi aku menyodorkan diri. Melumat bibirnya yang tegang. Hanya sementara. Karena selanjutnya dia melakukan apa yang telah aku lakukan. Kami berpagutan cukup lama. Entah tangan siapa yang berulah, hingga kemejanya sudah tergeletak begitu saja di sebelah kaki, pun kausku yang kebesaran.
Kami berpandangan lagi. Seperti meminta izin tanpa kata-kata. Aku menyukai bentuk tubuhnya. Dengan warna cokelat mengilap oleh keringat, bisa kurasakan otot-ototnya yang liat. Aku tidak menyangka Nanda menyembunyikan aset sebagus ini di balik kemeja lengan panjang yang selalu dia kenakan.
“La.” Dia mengerang lagi. Tanganku terus menyusuri setiap inci dadanya. Mengabaikan degup jantung yang memburu. Aku takjub. Rupanya seperti ini tubuh seorang laki-laki dewasa.
“Please!” Dia mendesis. Entah, memohon untuk apa? Berhenti atau mempercepat semua ini.
Aku memilih opsi kedua. Aku bangun dari posisi duduk di atas pahanya. Tanpa berpikir lagi, aku menarik celana jeans belelku yang sedikit basah karena hujan tanpa permisi tadi. Aku memang tidak punya otak sekarang. Kami lebih tepatnya. Karena dia melakukan hal yang sama.
“La ....” Dia tertegun.
Aku tidak bisa membedakan, rautnya yang terlihat menyesal atau mendamba? Bagiku sama saja. Aku menginginkannya. Biarkan aku bodoh sekali ini saja. Maka, aku merapat padanya tepat saat suara petir menggelegar memekakkan telinga.
“Mbak, sudah sampai.” Sebuah tangan mengusap lenganku.
“Mbak,” ulangnya lagi.
Mbak?
Butuh beberapa detik untukku mengerjap dan membuka mata.
Membuka mata?
Aku sedang bermimpi?
Aku membuang napas kasar dan menggaruk kepala yang tidak gatal. Memalukan sekali harus memimpikan momen itu setelah aku yakin telah melupakannya. Seorang pramugari berdiri di sebelah bangku yang sedang aku duduki. Dia tersenyum.
“Sudah sampai, Mbak.” Dia berkata lagi.
“Ya,” jawabku sekenanya.
Mataku memindai area kabin yang sepi. Tidak banyak penumpang yang mengisi gerbong ini. Hanya tinggal beberapa dan mereka pun tertidur lelap. Kereta sudah benar-benar berhenti saat aku meraih trolley bag di atas kepala. Dengan cekatan pramugari yang tampak segar tersebut membantuku untuk menurunkannya.
“Terima kasih,” ujarku sambil memandang wajahnya yang tidak berhenti tersenyum.
“Sama-sama. Selamat jalan, Mbak.”
Selamat jalan. Selamat tinggal. Dua kata yang tidak pernah ingin kudengar beberapa tahun terakhir. Selalu meninggalkan sesak yang tidak bisa kujelaskan mengapa. Aku hanya mengulas senyum sambil berjalan mendekati pintu.
Bunyi desisan angin terdengar kuat saat pintu terbuka. Udara dingin langsung merangsek masuk. Suasana hening di peron membuatku merapatkan kardigan. Bukan karena dinginnya, tapi kesenyapan yang mencekam terkadang lebih mengintimidasi.
Seorang petugas meniup peluit saat aku sudah benar-benar menjejak lantai stasiun. Pukul setengah tiga pagi. Petugas tersebut langsung masuk ke dalam tanpa menoleh padaku setelah kereta kembali berjalan. Mungkin dia hendak melanjutkan tidur. Terlalu merepotkan memang, menerima satu penumpang turun di stasiunnya tengah malam buta seperti sekarang.
Aku mengedarkan pandangan. Ini pertama kalinya aku berada di stasiun ini. Tujuh belas tahun lalu, ya, ternyata sudah selama itu, aku pernah berada di kota ini untuk kurun waktu yang tidak sebentar. Bukan berarti aku mengenal setiap sudut kota, karena nyatanya satu-satunya tempat yang kuketahui hanyalah rumah kakakku, yang akan aku tuju sekarang.
Aku mengusap sudut mata yang tetiba basah. Aku benci menangis. Tadinya aku mengira semua sesak serta rasa bersalah tersebut akan terkubur waktu. Nyatanya tidak ada yang berubah. Tanah ini mengingatkanku akan momen-momen itu. Satu momen yang kuharap bisa dihapus secara permanen dari memori otakku.
Susah payah aku mengusap pipi. Rembesan air dari kelopak mata tidak jua berhenti. Rasanya sia-sia apa yang kulakukan selama ini. Mengobati luka? Bullshit, aku hanya menyingkirkannya sejenak. Saat aku berani bersinggungan dengan masa itu, semuanya kembali seperti semula. Tidak ada yang benar-benar sembuh. Siapa pun yang mengatakan bahwa waktu bisa menyembuhkan luka, itu hanya omong kosong belaka.
“Welcome, Aunty.” Suara Rama membuatku segera mengusap pipi dengan lengan kardigan. Aku tidak mau melihatnya merasa bersalah. Pasalnya, dia yang meyakinkanku untuk kembali ke tempat ini saat mendengar Mami berusaha membuka perjodohan kembali.
Bisa dibilang aku gila. Iya, memang. Aku bertukar pikiran dengan seorang kemenakan yang agak eror isi kepalanya. Bocah tujuh belas tahun ini langsung menyuruhku segera mengepak koper untuk meninggalkan Bandung setelah mendengar rencana Mami. Berbeda dengan ayahnya yang justru memintaku pulang ke Surabaya sesuai permohonan Papi.
“Oma takkan pernah mengejar Tante ke Blitar. Percayalah.” Itu yang dia katakan saat aku menolak. Rencana perjodohan yang digagas Mami juga aku dengar dari mulutnya. Untuk ukuran anak laki-laki, dia memang menjengkelkan. Mulutnya tidak bisa diajak untuk merahasiakan sesuatu.
“Kabur dan ketahuan lalu diseret Oma pulang, atau kabur, ketahuan, tapi dibiarkan?” tanyanya kemudian. Tentu saja aku memilih yang kedua.
Seharusnya aku berterima kasih untuk rencana gilanya yang langsung ditolak mentah-mentah oleh ayahnya. Kakakku percaya, aku belum siap. Memang belum dan akan terus seperti itu jika aku tidak berani mencoba.
“Tante semakin mungil.” Rama menenggelamkanku dalam pelukan. Dia saja yang terlalu tinggi. Sama sekali tidak pantas untuk duduk di bangku SMA.
“Lama nungguinnya?” Aku melepaskan diri. Dipeluk seorang kemenakan yang otaknya sering gesrek membuatku waswas. Ada apa dia semanis ini? Pasti ada sesuatu yang dia inginkan, atau sembunyikan. Mataku menyipit. Dia hanya tertawa dan meraih koperku lalu diseretnya keluar.
“Tante jangan berisik, ya.” Rama menoleh. Langkah kakinya lebar. Aku agak kewalahan untuk mengimbanginya.
“Sejak kapan tante banyak omong?” Aku menggerutu. Mataku mengawasi halaman stasiun yang terang benderang. Beberapa bajaj berjejer rapi dengan pemiliknya tidur di dalam. Kendaraan roda tiga tersebut masih terlihat baru. Warna catnya cukup terang, berbeda dengan yang pernah kutemui puluhan tahun lalu saat berkunjung ke Jakarta. Apa mungkin ini bagian dari pembaruan? Setahuku, kota ini sangat identik dengan becak. Sama-sama beroda tiga. Yang membedakannya hanya kecepatan kendaraan tersebut untuk sampai tujuan.
“Please!” Rama berhenti. Dari sorot matanya yang memelas, aku semakin yakin, dia sedang menyembunyikan sesuatu.
“Hem,” jawabku malas. Aku mengikuti langkahnya tanpa bersuara. Bukan karena hendak menuruti apa yang dia minta. Hanya saja, aku masih terlalu mengantuk, tapi takut mimpi itu akan terulang. Apa karena aku kembali ke tempat ini sekarang? Sesuatu yang kuanggap sudah mengerak di dasar ingatan, kini berlomba untuk muncul satu per satu. Mamaksaku untuk mengakui, sebuah kenangan takkan semudah itu dimusnahkan.
“Tante duduk di belakang, ya.” Rama berkata kalem saat aku memegang pintu penumpang. Dia baru saja menyimpan koperku di bagasi.
Keningku berkerut. Dia langsung nyengir.
“Ada yang lagi tidur,” ucapnya sekali lagi, dengan nada bicara yang sama. Anak ini kalau sedang sopan begini sangat mencurigakan.
Detik berikutnya pintu penumpang didorong dari dalam. Aku segera menyingkir. Seorang gadis yang kelihatan baru bangun dari tidur berdiri terpaku. Dia mengucek matanya yang sembap. Aku yakin sekali dia habis menangis. Hidungnya memerah. Aku segera menatap Rama dengan mata memicing.
“Ini pacar aku, Tante.” Dia nyengir.
“What?” Suaraku melengking tanpa bisa ditahan. Rama buru-buru mendekat dan membekap mulutku.
“Tante bisa membangunkan semua orang.” Rama berbisik. Matanya nyalang mengawasi deretan bajaj yang baru saja kami lewati.
Aku segera melepaskan tangannya. “Kamu pacaran hingga jam berapa ini? Ya ampun, Rama. Ayahmu tahu?” Aku turut berbisik. Seolah gadis itu takkan mendengar. Jarak kami sangat dekat untuk ukuran menyembunyikan sesuatu. Meskipun mulutku sekarang aku tutup dengan tangan, tetap saja, gadis itu akan mendengar. Dia terlihat salah tingkah sekarang.
“Kami dari rumah.”
“Kami?” Aku membeo.
“Nala tidur di rumah.”
Na-la? Aku segera menatap gadis yang lumayan cantik dengan posisi berantakan tersebut. Rambutnya kusut, matanya sembap, hidungnya merah, dan dia terlihat sangat kikuk. Postur tubuhnya lumayan tinggi. Warna kulitnya putih susu. Aku seperti sedang bercermin. Setidaknya saat usiaku tujuh belas, aku juga seimut itu. Bedanya, aku memang benar-benar imut untuk ukuran tubuh.
“Syanala Nandini, cakep, kan, Tante namanya? Sama seperti orangnya.” Rama cengengesan.
Syanala? Aku tercekat. Dadaku seperti dihantam godam yang begitu berat dengan sangat keras. Syanala. Kenapa nama itu yang harus kudengar di hari pertama menginjakkan kaki di kota ini? Tanpa permisi air mataku luruh. Aku langsung mengusapnya dengan punggung tangan. Jangan. Kumohon. Aku sudah berlari tunggang langgang. Kenapa seperti baru kemarin semua ini terjadi?