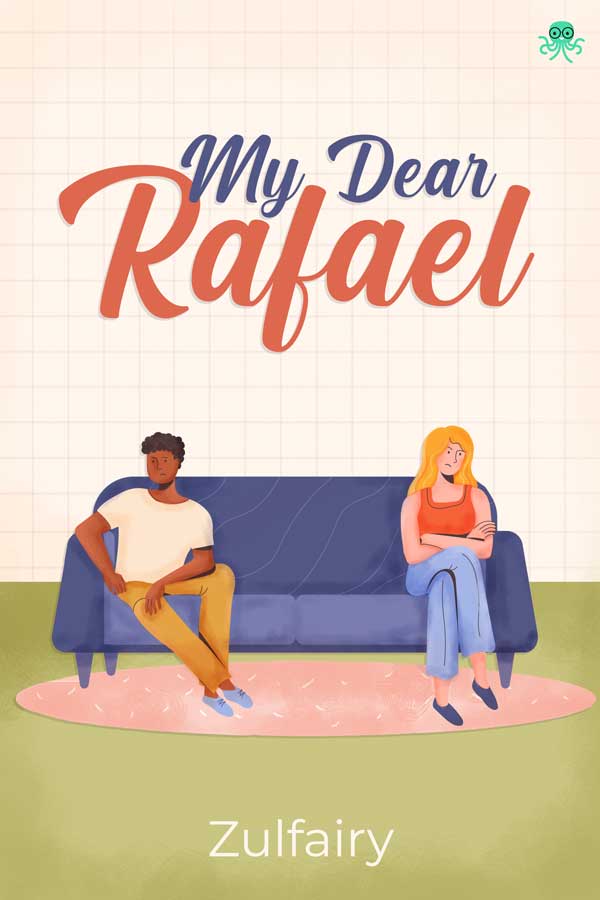
My Dear Rafael
By zulfairyy
Setelah mandi, Alice mengikat rambut pirangnya yang sehalus beludru dengan sebuah tali kulit panjang yang sudah lusuh. Bagian ujungnya terdapat beberapa manik berwarna merah dan kuning, juga sebuah batu lonjong seperti kapak kecil, hijau hitam berbintik.
"Tomako batu," kata Rafael.
"Tapi ini hanya tiruannya. Ini bukan asli. Ini untuk mempermanis rambut Nona."
"Saya rangkai sendiri sambil duduk di tepian danau Sentani. Air mendebur-debur dan saya menjalin-jalin serat kayu, memikirkan kontras warna manik-manik dan mata Nona yang biru." Matanya hitam keabuan dan berbinar-binar bangga.
Alice menerimanya, berterima kasih. Bibir tipisnya yang pucat menggumam beberapa kata lagi.
"Tidak, saya tidak repot," balas Rafael.
"Saya tidak pernah merasa repot membuat sesuatu untuk wanita cantik."
Tapi Alice sudah biasa menerima kata-kata manis. Sudah biasa dipuja-puji. Seorang laki-laki tinggi atletis berambut ikal dari bumi Papua dengan kulit sewarna mata tombak berkilau dan mulut pandai merayu tidak akan menggoyahkannya. Tidak meski ia merangkai sejuta manik-manik pada tali kulit.
"Benar, pertemuan kita ini adalah takdir," kata Rafael.
"Pada suatu tempat di langit sana, ketika worai(matahari) dan sembai(bulan) tak melihat, di antara bintang-bintang yang sudah tua, yang mulai kehilangan kerlipnya, sebut saja namanya Tetua Yotefa, ia iseng menuliskan cerita."
“Pada bulan ini dan tahun ini ketika bunga-bunga ungu jacaranda mekar serentak, Alice Blanchet dan Rafael Dondi Korwa akan bertemu. Di ruang satu-kosong-sembilan.”
Rafael membentangkan lengan. "Kemudian mereka berdua akan jatuh cinta. Cinta yang berkobar meletup-letup seperti kebakaran."
Alice menatap Rafael. Tak percaya mendengar gombalnya cowok itu. Ia kira tidak mungkin ada cewek yang akan terpesona oleh semua kemuluk-mulukan Rafael. Kecuali kalau cewek itu udah gila. Semua kemulukan yang berawal dari suatu siang yang menurut Alice penuh kesialan. Suatu siang di kampusnya, di ruang kuliah satu-kosong-sembilan.
***
"Kamu mau masuk?"
Alice menekan kenop pintu ruangan 109 dan seisi ruangan kecil itu menatapnya. Ada empat belas pasang mata, semuanya melirik ke arah Alice. Membuat gadis itu membeku sejenak. Ini tidak Alice harapkan. Kalau jam tangannya benar, seharusnya saat ini ia datang sepuluh menit lebih awal sebelum kelas dimulai. Bukan malah terlambat.
"Kamu masuk masuk atau tetap di situ?" Sorot mata dan nada suara Profesor Garreth terdengar menuntut. Alice menyiapkan pembelaan.
"Profesor, jadwal kelas ini seharusnya jam sepuluh kan?" kata Alice.
"Minggu lalu aku memindahkan kelas ini satu jam lebih cepat. Kamu akan tahu kalau kamu sudah mengecek message board di laman mahasiswamu."
Alice menutup pintu di belakangnya, tidak ada gunanya membantah. Namun, bagaimanapun juga ia perlu menyelamatkan muka, "Baiklah, Prof. Mungkin lain kali kirimkan kami email juga."
Ruangan 109 terlalu sempit untuk dijejali 10 sampai 15 kursi. Sebenarnya ruangan itu memang hanya diperuntukkan sebagai ruang diskusi grup mahasiswa, tapi dosen-dosen yang merubah jadwal kelas secara mendadak biasanya terpaksa mengambil ruang ini karena tidak ada kelas kosong lainnya.
Hanya tersisa satu kursi di sudut belakang ruangan. Pas di sebelah seorang cowok berkulit putih berambut merah. Ada banyak bekas tindikan di telinganya. Pipinya dihiasi bekas-bekas eksim yang mengering. Bajunya hitam dengan bercak debu dan sesuatu yang sepertinya gumpalan kecil bulu hewan. Tanpa sadar Alice sudah mengernyit.
Gadis itu terus berjalan ke salah satu meja terdepan. Mengarah pada cowok berkulit gelap yang sedang menekuri diktat tebal dari Profesor Garreth yang mungkin dibagikan di awal kelas tadi. Alice meletakkan bukunya di sudut meja dan membungkuk ke dekat telinga cowok itu, berbisik.
"Hai, maaf, kacamataku ketinggalan." Alice memaniskan suaranya sebelum sedikit berbohong. "Kalau tidak duduk di depan, aku sulit melihat."
Cowok yang ia ajak bicara mendongak menatapnya. Mulutnya seketika sedikit membuka. Menampilkan ekspresi yang sangat familiar bagi Alice.
"Namaku Alice. Boleh kita tukar kursi?" Alice sengaja mengulum bibir.
"... yes, tentu saja." Cowok itu menatapnya amat lekat, “Nona punya mata warna biru?”
Alice terhenyak. Ya, ia memiliki warna mata biru muda. Tidak istimewa sebenarnya di Australia yang penuh ras Kaukasia ini. Kenapa cowok ini menjadi begitu terpaku hingga tak sadar mengomentari warna matanya saat baru berkenalan? Itu bukan respons yang biasanya Alice terima.
Sorot mata laki-laki lainnya yang pertama melihat Alice biasanya tak jauh terpaut dari lokasi bibirnya yang merekah sempurna atau leher jenjangnya, atau tulang belikatnya, dan terus menyusur turun hingga ujung kakinya.
"Sori, maksud saya, ya, ya, tentu saya bisa, Alice." Cowok itu berdiri. Suaranya dalam tapi renyah. Tingginya di atas Alice. Rambutnya ikal dan dipangkas dengan rapi. Matanya bulat abu-abu gelap dinaungi alis lebat hitam. Hidungnya besar dan kukuh. Dagu persegi dan sedikit membelah. Bahu yang tinggi dan punggung yang lebar. Senyum yang manis.
"Kalau butuh kursi terdepan, kamu bisa duduk di kursiku." Professor Garreth bicara tanpa melepaskan pandangan dari lembaran diktatnya. Kursinya tepat di sisi whiteboard, menghadap seisi kelas.
"That young gentleman came here half an hour before class started, to get the front seat. Aku harus menghargai usaha anak ini." Professor Garreth beralasan.
"Apakah Anda serius, Prof?" tanyan Alice sambil tersenyum.
"Memang terdengar seperti candaan?" Professor Garreth bertanya balik.
Kelas menunggu dengan agak tegang. Beberapa berdeham. Alice paham apa maksudnya. Professor Garreth terkenal kaku dan tegas. Ia tidak suka ada mahasiswa yang terlambat tanpa pemberitahuan ke kelasnya.
Jadi maksud dehaman itu adalah: Hei, duduk. Udah telat, bikin heboh, jangan rese.
Sampai cowok yang tadi diminta Alice bertukar kursi meminta izin berbicara dengan mengangkat tangannya,"Saya saja yang duduk di kursi Professor."
"Kamu tidak terlambat masuk kelas."
"Betul... tapi....kalau Professor biarkan saya duduk di depan situ—" Cowok itu bersikeras. Senyumnya terpentang lebar tak ditahan-tahan. Matanya berbinar-binar. "—saya gantikan duduk di situ, saya akan terlihat seperti pahlawan di mata gadis cantik ini. Siapa tahu besok dia akan langsung duduk di sebelah saya."
Sedetik setelah ia menyelesaikan kalimatnya, seisi kelas sontak pecah dalam tawa geli. Bahkan Professor Garreth tak bisa menahan tersenyum.
"Well, kalau begitu aku tidak bisa melarangmu." Bahu profesor ahli hukum kelautan itu terangkat. "Sana, Tuan Putri, duduklah."
Alice menahan rasa malunya dalam hati. Ia segera duduk untuk menghentikan drama itu. Lagi-lagi bukan reaksi semacam ini yang Alice harapkan ketika ia tadi berusaha menarik perhatian cowok itu. Dengan bibir rapat terkatup Alice mendesiskan 'terima kasih' tak rela pada cowok itu.
"Sama-sama. Eh, nama saya Rafael."
Oh-peduli-amat.
***
Tepat seminggu setelah kejadian memalukan di ruang satu-kosong-sembilan itu Alice mengunjungi terapisnya, Miss Jones. Sesuai jadwal yang diberikan kepadanya, Alice turun dari bus di halte terdekat dengan tempat praktik Miss Jones. Ia menunggu tak lama, hanya sepuluh menit lalu masuk ke dalam ruang Miss Jones dengan mata memerah.
Bukan karena Alice habis menangis, tapi karena Miss Jones mengganti pewangi ruangan di gedung praktiknya dengan produk pewangi lain yang sepertinya memicu alergi Alice. Pewangi sialan itu berhasil membuat gadis berambut pirang itu menderita di ruang tunggu sambil menunggu giliran sesi konselingnya.
“Air freshner? Aku akan mengeceknya. Maaf membuatmu tidak nyaman, Alice,” kata Miss Jones ketika Alice bersin untuk kesepuluh kalinya dan mengeluh kelopak matanya terasa gatal.
“Jadi kamu punya cerita apa untukku hari ini, Alice? Apakah kamu sudah mencoba bicara dengan seseorang di kampusmu seperti yang kusarankan minggu lalu?” Miss Jones memulai sesinya dengan Alice.
Miss Jones sudah berusia empat puluhan. Kacamatanya tebal dan menggantung di pangkal hidungnya. Ia mengenakan blouse kembang biru dan semacam blazer kebesaran warna hitam. Sorot matanya ramah dan ia bicara dengan nada lembut yang membujuk–kalau bukan meninabobokan.
Alice adalah pasien ketiganya hari ini. Jadwal hari Rabu Miss Jones entah mengapa dipenuhi pasien dengan berbagai varian depresi, Alice salah satunya.
“Aku berbicara dengan beberapa orang. Agak lama. Tapi mereka adalah petugas dan karyawan kampus. Apakah itu masuk hitungan?” tanya Alice balik. Miss Jones mengangguk dan berkata semacam ‘tidak apa-apa itu sebuah permulaan yang baik’.
Tunggu.
Alice teringat bahwa seminggu lalu ia juga bicara dengan cowok berkulit gelap itu. Cowok yang mempermalukannya di kelas Professor Garreth. Cowok tegap dan atletis dengan lengan panjang dan tatapan mata cemerlang. Cowok itu memanggilnya ‘Nona Mata Biru’. Alice menimbang-nimbang apakah itu penting untuk diceritakan kepada Miss Jones.
“Apa yang kamu rasakan pagi ini?” tanya Miss Jones.
“Pertama-tama aku merasa haus. Jadi aku membuka kulkas dan meminum jus jeruk. Kemudian aku duduk menonton televisi dan kembali berpikir rencanaku hari ini biasa banget. Kenapa aku harus capek-capek bangun dan keluar rumah bila semuanya terasa sangat biasa dan tidak istimewa? Apa pun yang kulakukan tidak ada gunanya.”
“Kemudian, kamu memikirkan itu lagi?” Miss Jones bertanya.
Alice menjilat bibir bawahnya. “Ya, aku memikirkan untuk mengakhiri hidupku.”
“Acara apa yang kamu tonton semalam, Alice?”
“Semacam acara kriminal tentang … hakim dan tersangka yang didakwa menggunakan racun serangga sebagai alat pembunuhan.”
Miss Jones menggeleng. “Lain kali ganti dengan kartun atau acara komedi.”
“Kurasa itu malah membuatku semakin murung. Aku melihat diriku ini sangat aneh ketika semua orang dalam tayangan sitkom tertawa tapi aku tidak bisa.” Alice menunduk.
"Baiklah, coba tonton drama kehidupan pengacara atau pengadilan, mungkin mood-mu bisa sedikit terangkat," saran Miss Jones.
Ketika Alice menyelesaikan sesi terapi rutin mingguannya dan keluar dari gedung jam sudah menunjukkan pukul lima sore. Ia berjalan menekuri trotoar menuju halte bus langganannya di ujung jalan. Kedua tangan Alice masuk ke dalam jaketnya. Ia melewati sebuah minimarket kecil dan melihat seorang laki-laki tengah menggotong peti kayu berisi produk segar ke dalam minimarket. Sepertinya laki-laki itu bekerja sebagai kurir untuk toko itu.
“Alice!” Gadis itu mendengar namanya dipanggil. Laki-laki yang tadi ia lihat bekerja sebagai kurir produk segar itu ternyata cowok yang mempermalukannya di kelas Professor Garreth.
Siapa namanya kemarin? Raul? Raffle? Rafael!
Rafael melambai lalu mendekatinya dengan langkah-langkah lebar. Alice meliriknya sekilas, lalu perlahan mengalihkan pandangannya ke arah lain pada bentangan jalan raya sepi yang hanya dilalui satu-dua mobil saja. Ia berusaha pura-pura tak mengenal Rafael.
“Alice, ya kan? Nona Alice?” Rafael tiba-tiba sudah sampai di sisinya. Senyum merekah memperlihatkan seluruh barisan gigi. Seperti anak kecil yang berseri-seri melihat stoples penuh berisi permen.
“Ah…ya? Maaf aku lupa nam….” Alice mendesah.
“Rafael, nama saya Rafael,” kata Rafael sambil antusias menunjuk dirinya.
“Sori, Rafael, aku sedang buru-buru.” Alice berusaha menghindar. Ia celingukan mencari bus yang tak kunjung tiba. Rafael melangkah ke sisi depan halte hingga ia menghalangi pandangan Alice. Senyumnya terpentang.
“Saya juga buru-buru. Saya buru-buru ke sini untuk bicara dengan Nona,” katanya. “Saya bisa membantu Nona.”
***