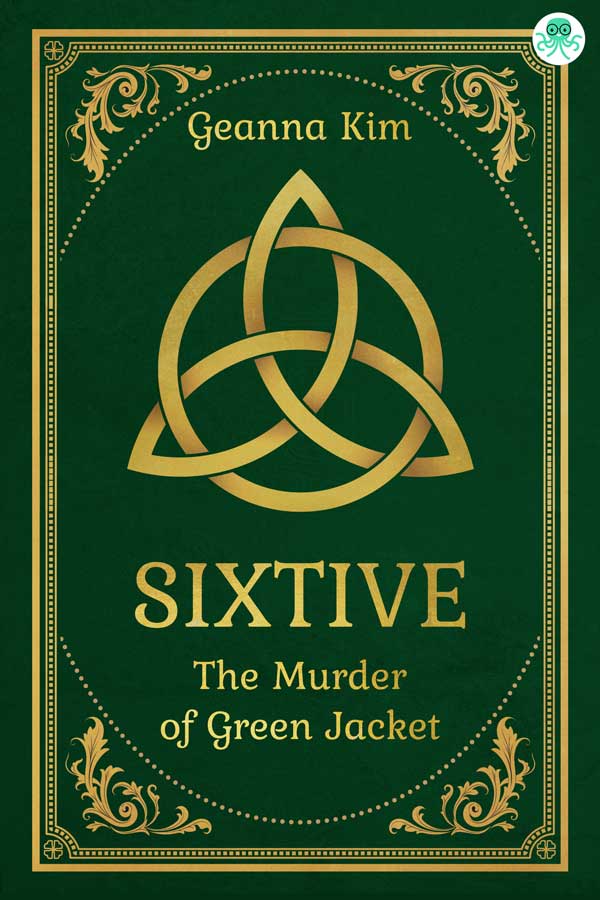
Sixtive
By Geanna Kim
Prolog
Danau Kenanga, 14 Maret 2014
Pukul 10.00 WIB
Orang dewasa selalu melarang anak kecil main di danau, katanya akan ada monster yang merangkak naik dari dasarnya dan menangkap kakimu. Kak Hara juga akan langsung berubah menjadi monster jika aku mencoba bermain-main di tepi Danau Kenanga yang cantik itu. Entahlah, sepertinya orang dewasa menganggap danau itu menyimpan raksasa atau hewan jahat dalam cerita dongeng yang biasa dibacakan Kak Hara setiap malam. Bagiku sendiri, danau itu menyenangkan dan luas. Aku bisa berlari seharian menyusuri tepiannya.
Tapi hari ini, kucabut pujianku itu setelah menyaksikan Kak Hara melanggar peraturannya sendiri dengan cara yang tak bisa kupahami.
“Hara Naomi Anatasya. Usia 24 tahun. Alumni mahasiswa Prodi Psikologi Fakultas Psikologi salah satu universitas ternama di Indonesia. Ditemukan tewas tenggelam di Danau Kenanga dalam kondisi leher tersayat pukul 08.30 WIB. Perkiraan kematian pukul 02.00 dini hari. Tim forensik menduga korban bunuh diri setelah ditemukan surat wasiat dalam kantong jaket almamater yang dipakainya. Saat ini tengah dilakukan pencarian untuk menemukan senjata yang digunakan korban.”
Danau Kenanga tempat Kak Hara biasa duduk sembari membaca buku kini terlihat mengerikan. Belasan mobil dengan lampu merah yang berputar di atapnya mengeluarkan suara menyakitkan. Pria-pria dewasa berseragam memadati tepian danau, mereka bertubuh besar dengan sepasang mata tajam tak menyenangkan. Semuanya terlihat cekatan memainkan jari yang berkelahi di atas permukaan secarik kertas, sebagian dari mereka kesulitan membentangkan stiker kuning panjang sembari menghalau kepungan warga. Orang-orang bersarung tangan karet yang membawa kamera hitam besar sibuk membidik ke segala arah, mereka asyik membingkai Kak Hara yang berenang di danau dalam keadaan mengambang.
Aku tak mengerti. Abang di sampingku hanya meremas tangannya kuat-kuat sembari menahan tangis. Tidak ada orang dewasa yang mau menjelaskan situasi membingungkan ini kepada anak kecil seperti kami. Mereka hanya memerintah dan menuding sudut taman perpustakaan dengan galak, menyerahkan dua orang anak kecil dimakan kegelisahan.
“Mengapa Kak Hara berenang sepagi ini?” tanyaku pada Abang.
Abang menghamburkan napas panjang, dari nada suaranya yang berat dia terdengar marah. “Itu bukan kolam renang. Itu danau. Seharusnya tak boleh ada orang yang berenang di sana karena dalam.”
Aku bingung. “La-lalu, Kak Hara?”
“Para orang tua selalu melarang kita main ke danau karena berbahaya, Gwen.” Abang menimpali dengan air mata yang merembes ke seluruh wajahnya.
“Jadi, Kak Hara dalam bahaya?” Aku mulai mengerti, sekaligus merasa sesak.
“Sepertinya ... ” Tubuh Abang bergetar di sampingku. “Tidak! Jangan pergi!”
Ada yang tak beres dari sekumpulan pria berseragam itu. Aku yakin betul. Kalau tidak, Abang tak mungkin menjerit sembari menutup telinganya lalu jatuh bersimpuh. Jadi, aku memutuskan untuk meninggalkan Abang yang meringkuk penuh penderitaan di sana. Aku harus memaksa salah satu pria berseragam itu untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan Kak Hara.
Tapi seseorang mencegatku. Ia memeluk tubuh kecilku saat aku mulai memberontak dari genggamannya yang kaku. Aku berteriak histeris dan nyaris membuat hidung mancungnya berdarah terkena tinjuku.
“Kamu mau ke mana? Di sana berbahaya, tidak untuk anak kecil!”
“Aku bukan anak kecil! Aku sudah 13 tahun!”
Anak laki-laki bertopi baret itu menggeram. Tubuhnya sedikit lebih tinggi dari Abang dan sepertinya usia mereka juga sebaya. Tapi genggaman tangannya sangat kuat seperti orang dewasa. Ia juga memiliki sepasang mata dingin seperti pria-pria berseragam di sana. Bahkan lebih dingin, matanya sangat dingin dan mengancam.
“Iya, baiklah. Kamu bukan anak kecil. Siapa namamu?”
Nada suaranya ketus sekali. Satu tangannya berkacak pinggang, menyibak juntaian jaket kulit hitam dan tertempel di pinggangnya yang terbalut kaus putih. Gayanya sok sekali untuk anak seumuran Abang, terlebih ia bicara sembari memainkan tusuk gigi yang digigit.
“Gwen Zefanya.” Aku mencoba terdengar ketus juga.
“Polisi-polisi berseragam di sana menakutkan. Jangan macam-macam.”
“Jangan sok tahu!” Aku menyanggah keras.
Begitu mendengar bentakanku, garis matanya menajam. Keningnya yang bersih dari juntaian rambut terlipat. Aku jadi merasa dia bukan anak yang ramah.
“Aku tahu. Aku calon detektif. Jangan remehkan aku.”
“Detektif? Apa itu?” tanyaku penasaran.
“Itu pekerjaan yang menyenangkan.” Anak itu berhenti bicara lalu memegang dadanya dengan raut dramatis. “Sekaligus mendebarkan, hehe.”
Aku tercengang saat tahu-tahu anak laki-laki itu tersenyum jahil dengan seringai nakal yang samar terpancar dari wajah putihnya. Aneh melihat sikapnya yang semula sok itu berubah menjadi ramah dalam sekejap.
“Biarpun mendebarkan tapi sangat dibutuhkan orang-orang. Detektif adalah pahlawan seperti yang kamu lihat di film dan komik. Mereka juga sahabat untuk anak-anak.” Anak itu melanjutkan sembari sesekali menyeringai lucu.
Senyumku mengembang. Tanpa sadar aku telah melupakan kegelisahanku dan hujan pertanyaan di dalam kepala tentang Kak Hara yang sejak semalam belum pulang.
“Kamu mau jadi detektif kalau sudah besar nanti, ya?”
Anak itu mengulum tusuk giginya, memandang ke langit biru yang cerah lalu tersenyum. “Ya, seperti Ayahku. Dia itu detektif paling hebat di dunia, meskipun sekarang dia sudah berada di Taman Bunga Langit yang indah.”
“Taman Bunga Langit?”
“Ya, kakakmu ju-juga sudah berada di sana,” tuturnya agak terbata.
Sekarang raut wajahnya yang kasar itu tak terbaca olehku. Matanya kosong menatapku seperti berusaha menyembunyikan sesuatu. Ia bahkan melonggarkan genggamannya di lenganku, persis yang dilakukan kepala panti asuhan dulu saat memberitahuku kalau ayah dan ibu sudah berpisah. Ia menunjukkan iba padaku, semua orang juga seperti itu saat mencoba menghiburku karena telah ditelantarkan orang tua. Gerakan kasar yang tercermin dari sifat seseorang akan melunak saat orang itu merasa kasihan, orang-orang tak akan tega mengasari anak kecil yang tengah bersedih karena kehilangan.
“Kak Hara tidak baik-baik saja, kan?” Aku bertanya dengan napas tertahan.
Helaan udara menguar dari mulutnya. “Ada orang mengambang di danau. Tubuhnya belum membusuk, tapi wajahnya sangat pucat dan tak ada napas yang keluar dari hidungnya. Menurutmu dia kenapa?”
Lidahku terasa pahit, menjalar ke dada dan memanaskan segala sesak yang ada di sana. Untuk sejenak paru-paruku lupa cara bernapas, sehingga harus menerima pukulan hampa dari kepalan tanganku yang bergetar.
“Bunuh diri atau dibunuh. Dua kemungkinan itu.” Ia melanjutkan dengan parau. “Tapi kuyakin keduanya benar. Memangnya air danau itu setajam pisau sehingga bisa menyayat leher seseorang?”
Tatapanku berguncang, terpaku pada wajahnya yang sekilas memancarkan aura sedih. Kendati begitu salju di sepasang matanya tetap tak mencair, ia masih begitu dingin.
“Dia dibunuh saat mencoba bunuh diri. Kepalanya mungkin saja disayat di dalam air, hendak dipotong oleh pelaku yang memanfaatkan aksi bunuh dirinya dengan cara yang keji.”
“Kak Hara ... tidak meninggal, kan?” tanyaku lirih.
Setelah itu aku tak dapat mengingat apa-apa lagi. Hanya sentuhan jemarinya yang menghancurkan lelehan air mataku di pipi. Juga teriakan melengking dari seseorang yang kukenal dan umpatan yang menghilangkan jari-jarinya. Itu orang tua adopsiku, ia seratus kali lipat lebih kasar dari si anak laki-laki saat sedang marah.
“Bocah kurang ajar! Tahu apa kau? Jangan asal bicara tentang putriku!”
Ayah pasti sangat berang, urat di pelipisnya menonjol dan menyulapnya menjadi monster mengerikan. Namun, anak itu tetap tenang meski dirajam umpatan Ayah.
“Di ranselnya ditemukan batu seberat 14 kilogram. Ditemukan juga botol minuman teh di TKP yang di dalamnya masih ada bongkahan utuh berbagai jenis pil obat. Itu jelas bisa beracun dan menguatkan dugaan bunuh diri. Terlebih ketika surat wasiat dimasukkan dalam daftar barang bukti. Tapi, mengapa lehernya tersayat?”
Semua orang terperangah. Aku juga sama, menatapnya dengan kengerian antara ada dan tiada. Dan tiba-tiba dia tersenyum, sengaja meninggikannya seolah-olah menantang.
“Aku yakin ini pembunuhan.” Anak itu melanjutkan, memasang senyum angkuh. “Titik penemuan mayatnya hanya sedalam 1,5 meter. Sedangkan tinggi korban yang tercatat di perlombaan terakhirnya bulan lalu adalah 1,6 meter. Berdasarkan profilnya, dia pernah menjuarai perlombaan renang tingkat nasional. Lantas, mengapa ia harus bunuh diri tempat sedangkal itu?”
Anak itu tersenyum mengejek. “Sebaiknya polisi jangan langsung menyimpulkan bahwa kasus ini bunuh diri. Pelaku memanfaatkan percobaan bunuh dirinya untuk membunuh. Memangnya air danau itu pisau yang bisa memotong saraf leher seseorang?”
Kami yang berada di sana dan menyaksikan semua ucapan anak laki-laki itu hanya bisa terdiam. Ayah membeku dengan wajahnya yang mengeras. Sementara dadaku berdegup keras saat kepala anak itu tiba-tiba menoleh dan melampirkan seutas senyum datar. Dua pria berseragam yang datang bersama Ayah tertawa samar. Mereka yang anak itu sebut sebagai polisi. Salah satunya menggaruk kening, seringai tawanya masih belum lepas dari bibir.
“Kamu suka nonton film detektif, ya?” tanya polisi itu sambil tertawa pongah.
Alis anak laki-laki itu mengerut, rautnya meluapkan rasa tidak suka. “Semua orang yang melihat TKP dan terlibat di dalamnya berhak mengajukan analisis untuk membantu pihak kepolisian memecahkan kasus.”
Polisi itu menoleh kepada Ayah dan rekannya, lalu mereka bertiga tertawa sangat geli seperti habis mendengar sebuah lelucon.
“Siapa yang menghitung kamu termasuk ke dalam orang yang terlibat di TKP? Kamu cuma penonton iseng, bukan saksi, petugas forensik, apalagi detektif.”
“Namamu siapa, Nak? Umur berapa?” Rekan polisi itu bertanya dengan lebih ramah.
“Ben. Lima belas tahun. Putra tunggal Detektif Rick Nalen.”
Dua polisi itu terkejut, mata mereka tak berkedip menatap anak laki-laki itu yang ternyata bernama Ben.
“Oh, Rick Nalen? Detektif yang dipecat karena kasus salah tangkap itu?”
Ayah yang menyadari lelucon dua polisi jahat itu ikut tertawa bersama mereka. Sementara aku yang tak mengerti apa-apa tentang dunia detektif dan polisi hanya bisa membaca kemarahan yang besar di wajah Ben.
“Ya, sebaiknya omonganmu memang tak perlu didengar.” Polisi berkumis tipis berkata ketus. “Karena seperti kata pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya.”
Kemudian terdengar panggilan nyaring dari seseorang agar semua polisi segera berkumpul. Dua polisi yang masih menyeringai jahat itu pun pergi ke tepi danau. Ayah memicingkan mata padaku dan menyuruhku kembali ke tempat Abang. Mereka bertiga pergi, menyisakan aku yang masih syok berat dan Ben yang berdiri kaku tak bersuara.
“Ben?” panggilku. “Benar yang kamu bilang itu?”
Ben masih berdiri seperti patung hidup, hanya hidungnya yang berkali-kali mengembuskan napas seperti deru.
“Akan kucari bukti yang lebih kuat. Mereka menginjak analisisku hanya karena persoalan umur dan catatan karier Ayahku yang buruk.”
Aku diam, berusaha mencerna perkataannya yang begitu dewasa. Ben tidak terlihat seperti anak berumur 15 tahun, dia bijaksana dan mempunyai gaya yang khas.
“Aku turut sedih untuk kakakmu.”
Aku mengangguk dengan kantung mata yang siap meledak. Ben hanya menunduk sembari memainkan genangan air dengan ujung sepatunya.
“Hujan semalam telah menghapus segalanya. Sidik jari, noda darah, jejak kaki, bukti penting, semuanya,” ucap Ben agak serak.
Ia kemudian beralih melihatku dan tersenyum. “Dan jika hari ini kembali turun hujan, maka semua kesedihanmu juga akan dihapuskan, Gwen.”
Perkataan Ben seperti ramalan, karena sepanjang hari itu aku tidak menangis. Aku melihat anak laki-laki bertopi baret itu pergi dengan menaruh janji di genggaman tanganku, bahwa ia akan menangkap pelakunya suatu saat nanti ketika sudah diakui sebagai detektif. Janji dari calon detektif itu membuat sebagian sesak di dadaku tersapu bersih.
Tidak seperti Ayah, Ibu dan Abang yang menangis menjerit-jerit, aku hanya memekik pilu dalam hati dan menciptakan gerimis di wajah kebas ini. Hujan yang turun menghapuskan semua kesedihanku, seperti yang Ben katakan tadi.
Satu hal yang pada akhirnya membuatku jatuh tersungkur dan meloloskan ribuan air mata adalah tubuh mengenaskan Kak Hara. Kak Hara terlalu baik untuk pergi dalam keadaan seperti itu dan dengan cara yang memilukan. Aku bahkan tak sanggup memandang Kak Hara, hanya berani menatap lekat-lekat gelang rajut di pergelangannya yang kami buat bersama.
Namun, hujan di akhir hari menyedihkan itu membantuku menghapus patahan hati yang tercecer di tanah. Seperti yang Ben katakan, hujan akan menghapus segalanya, termasuk perbuatan keji pembunuh Kak Hara. Saat terbaring di kasur, sebuah kenangan terputar di dinding bagai film dalam layar. Kak Hara terlihat sehat dan cantik di sana, duduk memangku gitar bersamaku sembari menikmati pesona Danau Kenanga di penghujung senja.
“Gwen, ketika kita beranjak dewasa, akan semakin banyak orang-orang yang membenci kita dan ingin berbuat jahat pada kita. Jadi nanti ketika sudah waktunya, kamu tak perlu takut. Memang begitulah duniamu. Kamu hanya perlu menjadi cahaya terang yang mengalahkan bayangan gelap itu.”
“Gwen bingung, Kak. Mengapa harus ada kejahatan di dunia ini? Dan kalau semua manusia hidup dengan baik, apa kejahatan akan hilang?”
“Kejahatan tidak akan pernah hilang, dan tidak perlu menjadi jahat untuk dibenci atau dijahati. Karena malaikat juga diperlakukan seperti itu oleh iblis di dunia ini.”
“Mengapa?”
“Gwen, ingat kalimat penting ini dan jangan pernah lupakan. Janji?”
“Iya, janji.”
“Hati manusia adalah jurang tanpa dasar. Jangan pernah melemparkan kebencian ke dalamnya. Pikiran manusia seperti sumur yang sangat dalam. Jangan mencoba tenggelam terlalu lama di dalamnya.”
Janji dengan Kak Hara di hari itu mengingatkanku pada Ben dan janjinya. Kami masih kecil, kami belum dewasa, tapi Ben sudah mengetahui betapa busuknya manusia. Dan aku sudah melihat kekejian yang ada di dunia.
“Kak, aku belum dewasa, tapi sudah kulihat betapa jahatnya manusia.”
***