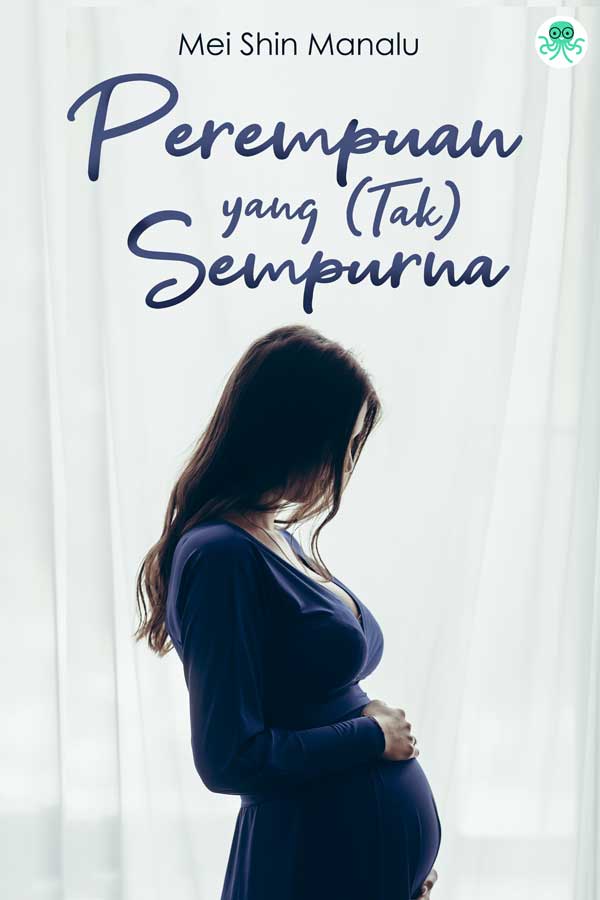
Perempuan yang (Tak) Sempurna
By Mei Shin Manalu
“Nduk, menjadi perempuan itu harus melalui tiga fase. Pertama sebagai putri, kedua sebagai istri, dan ketiga sebagai ibu. Kalau kamu sudah mencapai ketiga fase itu, barulah kamu bisa dikatakan sebagai seorang perempuan yang sempurna.”
Savita Ishwari ingat betul dengan nasihat yang disampaikan oleh ibunya sebelum ia beranjak dewasa. Fase menjadi perempuan yang sempurna. Namun, nasihat itu tidak sepenuhnya bisa dijalankan oleh Savita karena masih ada satu fase lagi yang belum ditempuhnya, yakni menjadi seorang ibu.
Sudah tujuh tahun Savita menikah dengan Dipta, dosen filsafat di kampusnya dulu, dan selama itu pulalah Savita sama sekali belum mampu memberikan keturunan bagi sang suami.
Yang paling menyakitkan adalah ketika Savita harus menjenguk adik ipar Dipta yang baru melahirkan di rumah sakit. Seperti yang terjadi sekarang, di mana Savita tidak bisa masuk ke ruangan dan hanya berdiri mematung di depan pintu.
Bagaimana bisa Savita melangkah ke sana? Rasanya sangat berat, apalagi saat melihat paras bersinar cerah dan senyuman melebar yang ditampilkan oleh sang suami. Sejak pertama kali menginjakkan kaki di ruangan itu, Dipta sudah langsung berhambur ke brankar adik iparnya. Tangannya yang kokoh itu tak canggung mengangkat bayi montok nan lucu yang baru sehari terlahir di dunia ini. Savita merasa tempatnya tidak berada di dalam, melainkan di luar ruangan agar tidak merusak kebahagiaan yang ada di tengah-tengah keluarga sang suami.
“Savita sini!” panggil Dipta sambil menoleh ke arah Savita. “Dia lucu, kan? Siapa namanya tadi?” Dipta menoleh ke arah adik iparnya, meminta konfirmasi atas nama anak itu.
“Viktor, Mas,” jawab perempuan yang sedang berbaring di atas brankar.
“Oh ya, Viktor. Habis namanya bule sekali. Aditya, Bunga, kok sekarang tiba-tiba Viktor?”
“Suamiku yang membuatnya, Mas. Katanya, karena ada klien baru yang bekerja sama, namanya Viktor.”
“Astaga, benar-benar aneh si Dewa ini,” celoteh Dipta sambil menggeleng-gelengkan kepala. Lalu, ia menaruh lagi bayi mungil itu ke tempat tidur.
Benar bukan? Savita tidak dibutuhkan di sana. Hanya keberadaan Dipta saja sudah cukup untuk keluarga ini. Seandainya Savita tadi menolak untuk ikut dengan berbagai alasan, mungkin saja ia tidak akan merasakan perasaan iri sebesar ini kepada istri dari adik iparnya. Rasa iri karena bisa mengandung dan melahirkan anak.
“Beri aku anak, Vit. Aku benar-benar ingin punya anak,” pinta Dipta dengan suara serak di tengah-tengah pergulatan ranjang mereka malam itu. Tidak hanya sekali Dipta mengungkapkan keinginan terbesarnya untuk memiliki keturunan. Sudah ratusan kali, atau mungkin ribuan. Entahlah. Saking seringnya Savita bahkan tidak bisa menghitungnya sama sekali. Yang ia ingat kalimat tersebut dilontarkan Dipta 10 hari yang lalu dalam pelukan mesra mereka ketika pria itu hendak mencapai puncaknya. Dan itu adalah malam terakhir mereka melakukan hubungan suami-istri, sebelum flu menyerang Savita dan menyebabkan perempuan itu harus menjauh dari sang suami.
“Astaga, cucuku laki-laki lagi!”
Mendadak suara perempuan tua memecah percakapan di ruangan. Suara itu tidak asing bagi semua orang yang ada di ruangan, tapi semua diam ketika mendengarnya. Sejenak semuanya membeku, menunggu ucapan yang terlontar selanjutnya.
Saat perempuan tua itu mendekati brankar, sontak Savita menyingkir dari tempatnya dan merapat ke sisi sang suami yang kini duduk di sofa. Namun, belum sampai Savita ke sisi sang suami, rentetan kalimat terdengar kembali dari mulut perempuan yang merupakan ibu mertuanya tersebut.
“Senangnya bisa menggendong cucu dari menantu sehat yang tidak mandul. Apa kamu tidak iri melihat ini, Vit?”
Jantung Savita bergemuruh. Mulai lagi, pikirnya. Dengan sekuat tenaga ia mengatur napas, mencoba untuk tetap tenang tatkala hatinya dihunjam rasa marah yang luar biasa.
Tak masalah jika perempuan tua itu menghinanya. Toh, selama ini ia sudah terbiasa mendengarnya. Akan tetapi, perlukah sampai sejauh ini? Menghina di depan semua anggota keluarga?
Savita berbalik badan. Di ujung embusan panjang, ia pun menjawab, “Iya Ma. Mama benar.”
“Jangan hanya bilang benar saja! Kamu harus buktikan dong ucapanmu itu. Beri Mama cucu!”
“Kami sedang berusaha sekuat tenaga, Ma,” balas Savita.
Dipta yang melihat pertengkaran itu merasa jengkel. Ia berdiri dari sofa dan menghampiri sang istri. “Ayo kita pulang, Sayang. Aku ada pekerjaan,” katanya seraya membawa Savita keluar dari ruangan itu. Menyelamatkan sang istri dari sindiran ibunya.
Sebenarnya usaha apa yang tidak pernah dilakukan Savita? Segala hal telah ia coba. Setelah lulus kuliah, Savita pernah bekerja di perpustakaan kementerian pendidikan dan kebudayaan selama 10 bulan. Namun, secara tiba-tiba, Dipta meminta Savita mengundurkan diri. Supaya tidak kelelahan katanya. Maklum lokasi tempat kerjanya yang berada di Senayan cukup jauh dari tempat tinggal mereka yang berada di Jakarta Timur.
Yang dikatakan Dipta ada benarnya. Savita tidak memungkiri bahwa perjalanan ke tempat kerjanya cukup melelahkan. Setiap hari ia harus pulang pergi dengan menaiki bus TransJakarta. Kalau beruntung, ia bisa dapat tempat duduk. Namun, kalau sedang padat-padatnya, perempuan itu akan berdiri selama hampir satu jam. Belum lagi ia harus turun di berbagai halte untuk berpindah bus. Mungkin sudah saatnya ia berhenti. Apalagi Dipta mengingatkannya tentang kehamilan, yang membuat Savita tidak punya pilihan lain kecuali menurut.
Sayangnya, walaupun sudah berhenti bekerja, Savita belum juga menampakkan tanda-tanda kehamilan. Satu tahun pertama pernikahan mereka, semuanya baik-baik saja. Keinginan untuk memiliki keturunan tidak terlalu menggebu. Namun, begitu menginjak tahun kedua, omongan-omongan miring mulai bermunculan, terutama dari mulut sang ibu mertua. Keadaan semakin parah, karena tahun itu Dewa mengabarkan bahwa istri yang baru ia nikahi beberapa bulan langsung mengandung anak pertama mereka.
“Mbak, coba masak taoge seminggu sekali. Katanya taoge bagus untuk kesuburan,” saran dari istri Dewa kepada Savita. Dan Savita pun mengikutinya. Mulai dari dijadikan sayur di menu makan malam, sambal, sup, pelengkap lauk pauk, bahkan sampai gorengan berbahan taoge sudah pernah dimasak oleh Savita. Alhasil, bukannya mendapatkan anak, perempuan itu malah mendapatkan omelan dari sang suami yang marah karena bosan melihat benda itu selalu muncul di meja makan.
“Bagaimana kalau Mbak datang ke dokter kandunganku? Coba diperiksa ke dokter supaya bisa dicari sumber masalahnya.” Kali ini Rara yang mengusulkannya saat adik kedua Dipta itu tengah mengandung anak pertamanya. Savita pun mengikuti arahan tersebut. Ia menyisihkan uang bulanan yang diberikan oleh Dipta untuk pergi ke dokter.
Saat itu ia belum berani memberi tahu sang suami tentang rencananya. Perempuan itu takut jika yang dituduhkan ibu mertuanya benar-benar terbukti, bahwa ia bukanlah perempuan yang subur alias mandul.
“Apa ibu merokok? Suka minum-minuman keras? Ada kendala dalam periode menstruasi? Atau pernah mengalami masalah dalam hubungan seksual?” tanya dokter ahli kandungan yang Rara anjurkan pada Savita kala itu.
“Tidak Dok,” jawab perempuan itu sambil menggelengkan kepala karena nyatanya semuanya terasa normal-normal saja.
“Ada banyak penyebab infertilitas, Bu. Ada baiknya jika Anda dan suami Anda menjalani proses pemeriksaan lanjutan.”
Begitulah saran dari sang dokter yang juga dituruti oleh Savita. Sekali lagi, Savita datang ke rumah sakit untuk melewati rentetan pemeriksaan yang panjang dan terbilang cukup lama. Kemudian, hasilnya pun didapatkan. Savita dinyatakan baik-baik saja. Sang dokter sama sekali tidak menemukan kelainan di dalam rahim perempuan itu.
Karena tidak ada masalah pada dirinya, Savita memberanikan diri untuk mengajak suaminya ke dokter. Namun, sebelum rencana itu terealisasi, sang ibu mertua sudah telanjur mendengar dan menentangnya dengan tegas. Savita tidak bisa berbuat apa-apa lagi.
***